.jpg)
Pada tulisan yang telah lalu telah dibahas mengenai hal-hal yang diharomkan bagi wanita haid. Pada tulisan bagian kedua ini, akan dipaparkan tiga permasalahan penting terkait wanita haid, yaitu mengenai boleh tidaknya wanita haid masuk ke dalam masjid serta menyentuh dan membaca Al Qur’an.
Bolehkah seorang wanita yang sedang haid masuk dan duduk di dalam masjid ?
Sebagian ulama melarang seorang wanita masuk dan duduk di dalam masjid dengan dalil:
لاَأُحِلُّ الْمَسْجِدُ ِلحَائِضٍُ وَلا َجُنُبٍ
“Aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haidh dan orang yang junub.” (Diriwayatkan oleh Abu Daud no.232, al Baihaqi II/442-443, dan lain-lain)
Akan tetapi hadits di atas merupakan hadits dho’if (lemah) meski memiliki beberapa syawahid (penguat) namun sanad-sanadnya lemah sehingga tidak bisa menguatkannya dan tidak dapat dijadikan hujjah. Syaikh Albani -rahimahullaah- telah menjelaskan hal tersebut dalam ‘Dho’if Sunan Abi Daud’ no. 32 serta membantah ulama yang menshahihkan hadits tersebut seperti Ibnu Khuzaimah, Ibnu al Qohthon, dan Asy Syaukani. Beliau juga menyebutkan ke-dho’if-an hadits ini dalam Irwa’ul Gholil’ I/201-212 no. 193.
Berikut ini sebagian dalil yang digunakan oleh ulama yang membolehkan seorang wanita haid duduk di masjid (Jami’ Ahkamin Nisa’ I/191-192):
Adanya seorang wanita hitam yang tinggal di dalam masjid pada zaman Nabi shallallahu’alaihi wa sallam. Namun tidak ada dalil yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu’alaihi wa sallam memerintahkannya untuk meninggalkan masjid ketika ia mengalami haidh.
Sabda Nabi shallallahu’alaihi wa sallam kepada ‘Aisyah radhiyallahu’anha, “Lakukanlah apa yang bisa dilakukan oleh orang yang berhaji selain thowaf di Baitullah.” Larangan thowaf ini dikarenakan thowaf di Baitullah termasuk sholat, maka wanita itu hanya dilarang untuk thowaf dan tidak dilarang masuk ke dalam masjid. Apabila orang yang berhaji diperbolehkan masuk masjid, maka hal tersebut juga diperbolehkan bagi seorang wanita yang haidh.
Kesimpulan:
Wanita yang sedang haid diperbolehkan masuk dan duduk di dalam masjid karena tidak ada dalil yang jelas dan shohih yang melarang hal tersebut. Namun, hendaknya wanita tersebut menjaga diri dengan baik sehingga darahnya tidak mengotori masjid.
Bolehkah seorang wanita yang sedang haid membaca Al Qur’an (dengan hafalannya) ?
Sebagian ulama berpendapat bahwa wanita yang haid dilarang untuk membaca Al Qur’an (dengan hafalannya) dengan dalil:
لاَ تَقرَأِ الْحَا ءضُ َوَلاََ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْانِ
“Orang junub dan wanita haid tidak boleh membaca sedikitpun dari Al Qur’an.” (Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi I/236; Al Baihaqi I/89 dari Isma’il bin ‘Ayyasi dari Musa bin ‘Uqbah dari Nafi’ dari Ibnu ‘Umar)
Al Baihaqi berkata, “Pada hadits ini perlu diperiksa lagi. Muhammad bin Ismail al Bukhari menurut keterangan yang sampai kepadaku berkata, ‘Sesungguhnya yang meriwayatkan hadits ini adalah Isma’il bin Ayyasi dari Musa bin ‘Uqbah dan aku tidak tahu hadits lain yang diriwayatkan, sedangkan Isma’il adalah munkar haditsnya (apabila) gurunya berasal dari Hijaz dan ‘Iraq’.”
Al ‘Uqaili berkata, “Abdullah bin Ahmad berkata, ‘Ayahku (Imam Ahmad) berkata, ‘Ini hadits bathil. Aku mengingkari hadits ini karena adanya Ismail bin ‘Ayyasi’ yaitu kesalahannya disebabkan oleh Isma’il bin ‘Ayyasi’.”
Syaikh Al Albani berkata, “Hadits ini diriwayatkan dari penduduk Hijaz maka hadits ini dhoif.” (Diringkas dari Larangan-larangan Seputar Wanita Haid dari Irwa’ul Gholil I/206-210)
Kesimpulan dari komentar para imam ahli hadits mengenai hadits di atas adalah sanad hadits tersebut lemah sehingga tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk melarang wanita haid membaca Al Qur’an.
Hadits dari ‘Aisyah radhiyallahu’anha beliau berkata, “Aku datang ke Mekkah sedangkan aku sedang haidh. Aku tidak melakukan thowaf di Baitullah dan (sa’i) antara Shofa dan Marwah. Saya laporkan keadaanku itu kepada Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam, maka beliau bersabda, ‘Lakukanlah apa yang biasa dilakukan oleh haji selain thowaf di Baitullah hingga engkau suci’.” (Hadits riwayat Imam Bukhori no. 1650)
Seorang yang melakukan haji diperbolehkan untuk berdzikir dan membaca Al Qur’an. Maka, kedua hal tersebut juga diperbolehkan bagi seorang wanita yang haid karena yang terlarang dilakukan oleh wanita tersebut -berdasar hadits di atas- hanyalah thowaf di Baitullah. (Jami’ Ahkamin Nisa’ I/183)
Kesimpulan:
Wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk berdzikir dan membaca Al Qur’an karena tidak ada dalil yang jelas dan shohih dari Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam yang melarang hal tersebut. Wallahu Ta’ala a’lam.
Bolehkah seorang wanita yang sedang haid menyentuh mushhaf Al Qur’an ?
Telah terjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ulama yang melarang hal tersebut berdalil dengan ayat:
لاَّ يَمَسَّةُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ
Artinya:
“Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.” (QS. Al Waqi’ah: 79)
يَمُسُّ maksudnya adalah menyentuh mushhaf al Qur’an. المُطَهَّرُونَ maksudnya adalah orang-orang yang bersuci. Oleh karena itu tidak boleh menyentuh mushaf al Qur’an kecuali bagi orang-orang yang telah bersuci dari hadats besar atau kecil.
Mereka juga berdalil dengan hadits Abu Bakar bin Muhammad bin ‘Amr bin Hazm dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Nabi shallallahu’alaihi wa sallam menulis surat kepada penduduk Yaman dan di dalamnya terdapat perkataan:
لاَّ يَمَسُّ الْقُرْاَنَ إِلاَّ طَا هِرٌ
“Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci.” (Hadits Al Atsram dari Daruqutni)
Sanad hadits ini dho’if namun memiliki sanad-sanad lain yang menguatkannya sehingga menjadi shahih li ghairihi (Irwa’ul Ghalil I/158-161, no. 122)
Ulama yang membolehkan wanita haid menyentuh mushhaf Al Qur’an memberikan penjelasan sebagai berikut:
إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيْمٌ فِي كِتَابٍ مَّكْنُو نٍ لاَّ يَمَسَّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ تَتِريلٌ مِّن رَّبِّ الْعَا لَمِينَ
Artinya:
“Sesungguhnya Al qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara. Tidak menyentuhya kecuali (hamba-hamba) yang disucikan. Diturunkan oleh Robbul ‘Alamin.” (QS. Al Waqi’ah: 77-80)
Kata ganti ﻪ (-nya pada “Tidak menyentuhnya”) kembali kepada ﻛﺘﺎﺏ ﻣﻜﻨﻮﻥ (Kitab yang terpelihara). Ibnu ‘Abbas, Jabir bin Zaid, dan Abu Nuhaik berkata, “(yaitu) kitab yang ada di langit”.
Adh Dhahhak berkata, “Mereka (orang-orang kafir) menyangka bahwa setan-setanlah yang menurunkan Al Qur’an kepada Muhammad shallallaahu’alaihi wa sallam, maka Allah memberitakan kepada mereka bahwa setan-setan tidak kuasa dan tidak mampu melakukannya.” (Tafsir Ath Thobari XI/659).
Mengenai ﺍﻟﻤُﻄَﻬَّﺮُﻭﻥَ menurut pendapat beberapa ulama, di antaranya:
Ibnu ‘Abbas berkata, “Adalah para malaikat. Demikian pula pendapat Anas, Mujahid, ‘Ikrimah, Sa’id bin Jubair, Adh Dhahhak, Abu Sya’tsa’ , Jabir bin Zaid, Abu Nuhaik, As Suddi, ‘Abdurrohman bin Zaid bin Aslam, dan selain mereka.” [Tafsir Ibnu Katsir (Terj.)]
Ibnu Zaid berkata, “yaitu para malaikat dan para Nabi. Para utusan (malaikat) yang menurunkan dari sisi Allah disucikan; para nabi disucikan; dan para rasul yang membawanya juga disucikan.” (Tafsir Ath Thobari XI/659)
Imam Asy Syaukani berkata dalam Nailul Author, Kitab Thoharoh, Bab Wajibnya Berwudhu Ketika Hendak Melaksanakan Sholat, Thowaf, dan Menyentuh Mushhaf: “Hamba-hamba yang disucikan adalah hamba yang tidak najis, sedangkan seorang mu’min selamanya bukan orang yang najis berdasarkan hadits:
الْمُؤْمِنُ لاَ يَنْجُسُ
“Orang mu’min itu tidaklah najis.” (Muttafaqun ‘alaih)
Maka tidak sah membawakan arti (hamba) yang disucikan bagi orang yang tidak junub, haid, orang yang berhadats, atau membawa barang najis. Akan tetapi, wajib untuk membawanya kepada arti: Orang yang tidak musyrik sebagaimana dalam firman Allah Ta’ala yang artinya, “Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis.” (QS. At Taubah: 28)
Di samping itu lafadz yang digunakan dalam ayat tersebut adalah dalam bentuk isim maf’ul-nya (orang-orang yang disucikan), bukan dalam bentuk isim fa’il (orang-orang yang bersuci). Tentu hal tersebut mengandung makna yang sangat berbeda.
Mengenai hadits “Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci”, Syaikh Nashiruddin Al Albani rahimahullah berkata, “Yang paling dekat -Wallahu a’lam- maksud “orang yang suci” dalam hadits ini adalah orang mu’min baik dalam keadaan berhadats besar, kecil, wanita haid, atau yang di atas badannya terdapat benda najis karena sabda beliau shallallahu’alaihi wa sallam: “Orang mu’min tidakah najis” dan hadits di atas disepakati keshahihannya. Yang dimaksudkan dalam hadits ini (yaitu hadits Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci) bahwasanya beliau melarang memberikan kuasa kepada orang musyrik untuk menyentuhnya, sebagaimana dalam hadits:
نَهَى أَنْ يُسَا فَرَ بِا لْقُرْانِ إِلَى أَرْضِ اْلعَدُو
“Beliau melarang perjalanan dengan membawa Al Qur’an menuju tanah musuh.” (Hadits riwayat Bukhori). (Dinukil dari Larangan-larangan Seputar Wanita Haid dari Tamamul Minnah, hal. 107).
Meski demikian, bagi seseorang yang berhadats kecil sedang ia ingin memegang mushaf untuk membacanya maka lebih baik dia berwudhu terlebih dahulu. Mush’ab bin Sa’ad bin Abi Waqash berkata, “Aku sedang memegang mushhaf di hadapan Sa’ad bin Abi Waqash kemudian aku menggaruk-garuk. Maka Sa’ad berkata, ‘Apakah engkau telah menyentuh kemaluanmu?’ Aku jawab, ‘Ya.’ Dia berkata, ‘Berdiri dan berwudhulah!’ Maka aku pun berdiri dan berwudhu kemudian aku kembali.” (Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al Muwaththa’ dengan sanad yang shahih)
Ishaq bin Marwazi berkata, “Aku berkata (kepada Imam Ahmad bin Hanbal), ‘Apakah seseorang boleh membaca tanpa berwudhu terlebih dahulu?’ Beliau menjawab, ‘Ya, akan tetapi hendaknya dia tidak membaca pada mushhaf sebelum berwudhu”.
Ishaq bin Rahawaih berkata, “Benar yang beliau katakan, karena terdapat hadits yang dari Nabi shallallahu’alaihi wa sallam. Beliau bersabda, ‘Tidak boleh menyentuh Al Qur’an kecuali orang yang suci’ dan demikian pula yang diperbuat oleh para shahabat Nabi shallallahu’alaihi wa sallam.” (Dari Larangan-larangan Seputar Wanita Haid, dari Irwaul Gholil I/161 dari Masa’il Imam Ahmad hal. 5)
Abu Muhammad bin Hazm dalam Al Muhalla I/77 berkata, “Menyentuh mushhaf dan berdzikir kepada Allah merupakan ibadah yang diperbolehkan untuk dilakukan dan pelakunya diberi pahala. Maka barangsiapa yang melarang dari hal tersebut, maka ia harus mendatangkan dalil.” (Jami’ Ahkamin Nisa’ I/188).
Kesimpulan:
Wanita yang sedang haid diperbolehkan menyentuh mushhaf Al Qur’an karena tidak ada dalil yang jelas dan shohih yang melarang hal tersebut. Wallaahu Ta’ala A’lam.
Rujukan:
Larangan-larangan Seputar Wanita Haid, artikel Majalah As Sunnah 01/ IV/ 1420-1999, Abu Sholihah Muslim al Atsari.
Jami’ Ahkamin Nisa’, Syaikh Musthofa al ‘Adawi.
Tafsir Al Qur’an Al ‘Adziim (Terj. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8), Ibnu Katsir.
***********
Penulis: Ummu Hamzah
Muroja’ah: Ustadz Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar
http://muslimah.or.id/fikih/hukum-seputar-darah-wanita-haid.html/comment-page-1
Friday, 29 October 2010
~ Hukum Seputar Darah Wanita: HAID ~
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 9:19 pm 0 comments
Labels: ~ Fiqh Dan Ibadah ~
Thursday, 28 October 2010
~ Hukum Seputar Darah Wanita: Darah Nifas ~

Waktu persalinan adalah salah satu momen paling mendebarkan bagi seorang wanita. Karena momen ini merupakan bagian dari jihad teragung kaum wanita. Di mana seorang wanita yang meninggal saat melahirkan bahkan termasuk golongan manusia yang mati syahid (HR. Abu Dawud dan Ahmad). Setelah momen ini, seorang wanita akan memulai babak baru kehidupannya menjadi seorang ibu yang mempunyai kewajiban mendidik buah hatinya. Dan sebaik-baik pendidikan untuk anak adalah dengan pendidikan agama.
Ternyata, momen penting ini pun tak lepas dari perhatian syariat karena pada saat persalinan seorang wanita akan mengeluarkan darah nifas. Sebagaimana haid dan istihadhah, darah nifas termasuk jenis darah yang biasa terjadi pada wanita. Oleh karena itu, para muslimah hendaknya mengetahui hukum-hukum seputar darah nifas.
Apakah Darah Nifas itu??
Nifas adalah darah yang keluar dari rahim karena melahirkan. Baik darah itu keluar bersamaan ketika proses melahirkan, sesudah atau sebelum melahirkan, yang disertai dengan dirasakannya tanda-tanda akan melahirkan, seperti rasa sakit, dll. Rasa sakit yang dimaksud adalah rasa sakit yang kemudian diikuti dengan kelahiran. Jika darah yang keluar tidak disertai rasa sakit, atau disertai rasa sakit tapi tidak diikuti dengan proses kelahiran bayi, maka itu bukan darah nifas.
Selain itu, darah yang keluar dari rahim baru disebut dengan nifas jika wanita tersebut melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia. Jika seorang wanita mengalami keguguran dan ketika dikeluarkan janinnya belum berwujud manusia, maka darah yang keluar itu bukan darah nifas. Darah tersebut dihukumi sebagai darah penyakit (istihadhah) yang tidak menghalangi dari shalat, puasa dan ibadah lainnya.
Perlu ukhty ketahui bahwa waktu tersingkat janin berwujud manusia adalah delapan puluh hari dimulai dari hari pertama hamil. Dan sebagian pendapat mengatakan sembilan puluh hari.
Sebagaimana hadits dari Ibnu Mas’ud sradhiyallahu ‘anhu , bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberitahukan kepada kami, dan beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang benar dan yang mendapat berita yang benar, “Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah, kemudian menjadi ‘alaqah seperti itu pula, kemudian menjadi mudhghah seperti itu pula. Kemudian seorang malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya, dan diperintahkan kepadanya untuk menulis empat hal, yaitu menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Menurut Ibnu Taimiyah, “Manakala seorang wanita mendapati darah yang disertai rasa sakit sebelum masa (minimal) itu, maka tidak dianggap sebagai nifas. Namun jika sesudah masa minimal, maka ia tidak shalat dan puasa. Kemudian apabila sesudah kelahiran ternyata tidak sesuai dengan kenyataan (bayi belum berbentuk manusia-pen) maka ia segera kembali mengerjakan kewajiban. Tetapi kalau ternyata demikian (bayi sudah berbentuk manusia-pen), tetap berlaku hukum menurut kenyataan sehingga tidak perlu kembali mengerjakan kewajiban.” (kitab Syarhul Iqna’)
Secara ringkas dapat disimpulkan beberapa hal untuk mengenali darah nifas:
Nifas adalah darah yang keluar dari rahim disebabkan melahirkan, baik sebelum, bersamaan atau sesudah melahirkan
Disertai dengan tanda-tanda akan melahirkan (seperti rasa sakit, dll) yang diikuti dengan proses kelahiran
Bayi yang dilahirkan/ dikeluarkan sudah berbentuk manusia (terdapat kepala, badan dan anggota tubuh lain seperti tangan dan kaki, meskipun belum sempurna benar)
Lama Keluarnya Darah Nifas
Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin dalam Risalah fid Dima’ Ath-Thabi’iyah lin Nisa mengatakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang apakah nifas itu ada batas minimal dan maksimalnya.
Adapun Syaikh ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al Khalafi di dalam Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz mengatakan bahwa nifas ada batas maksimalnya, yaitu empat puluh hari. Pendapat beliau berdasarkan hadits dari Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha. Ummu Salamah radhiyallahu ‘anha berkata, “Kaum wanita yang nifas tidak shalat pada masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selama empat puluh hari.” (HR. Ibnu Majah dan Tirmidzi. Hadits hasan shahih). Waktu empat puluh hari dihitung sejak keluarnya darah, baik darahnya itu keluar bersamaan, sebelum atau sesudah melahirkan.
Pendapat yang kuat, insyaa Allah, pada dasarnya tidak ada batasan minimal atau maksimal lama waktu nifas. Waktu empat puluh hari adalah kebiasaan sebagian besar kaum wanita. Akan tetapi apabila sebelum empat puluh hari wanita tersebut telah suci, maka ia wajib mandi dan melakukan ibadah wajibnya lagi.
Mengenai banyaknya darah, juga tidak ada batasan sedikit atau banyaknya. Selama darah nifas masih keluar maka sang wanita belum wajib mandi (bersuci).
Secara ringkas, ada beberapa kondisi wanita yang sedang nifas:
Darah nifas berhenti keluar sebelum 40 hari dan tidak keluar lagi setelah itu. Maka sang wanita wajib mandi (bersuci) dan kemudian melakukan ibadah wajibnya lagi, seperti shalat dan puasa, dll.
Darah nifas berhenti keluar sebelum 40 hari, akan tetapi kemudian darah keluar lagi sebelum hari ke-40. Maka, jika darah berhenti ia mandi (bersuci) untuk shalat dan puasa. Jika darah keluar, ia harus meninggalkan shalat dan puasa. Akan tetapi, bila berhentinya darah kurang dari sehari, maka tidak dihukumi suci.
Darah nifas terus keluar dan baru berhenti setelah hari ke-40. Maka sang wanita harus mandi (bersuci).
Darah terus keluar hingga melebihi waktu 40 hari. Ada beberapa kondisi:
Darah nifas berhenti dilanjutkan keluarnya darah haid (berhentinya darah nifas bertepatan waktu haid), maka sang wanita tetap meninggalkan shalat dan puasa. Darah yang keluar setelah 40 hari dihukumi sebagai darah haid. Sang wanita baru wajib mandi (bersuci) setelah darah haid tidak keluar lagi.
Darah tetap keluar setelah 40 hari dan tidak bertepatan dengan kebiasaan masa haid, ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Menurut ulama yang berpendapat bahwa lama maksimal nifas adalah 40 hari, menilai darah yang keluar setelah 40 hari sebagai darah fasadh (penyakit) yang statusnya adalah sebagaimana istihadhah. Sedangkan menurut ulama yang berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal dan maksimal lama nifas, mereka menilai darah yang keluar setelah 40 hari tetap sebagai darah nifas. Pendapat inilah yang lebih kuat, insya Allah.
Akan tetapi, jika ingin berhati-hati, setelah 40 hari dinilai suci. Sehingga sang wanita bersuci untuk melaksanakan shalat dan puasa, meski darah tetap keluar. Akan tetapi hal ini tidak berlaku pada 2 keadaan:
Ada tanda bahwa darah akan berhenti/ makin sedikit. Maka sang wanita menunggu darah berhenti keluar, baru kemudian mandi (bersuci)
Ada kebiasaan dari kelahiran sebelumnya, maka itu yang dipakai. Misal, sang wanita telah mengalami beberapa kali nifas yang lamanya 50 hari. Maka batasan ini yang dipakai.
Hal-hal yang Diharamkan bagi Wanita yang Nifas
Para ulama telah bersepakat bahwa wanita yang sedang nifas diharamkan melakukan apa saja yang diharamkan bagi wanita yang haid. Antara lain,
Sholat.
Wanita yang haid dan nifas haram melakukan shalat fardhu maupun sunnah, dan mereka tidak perlu menggantinya apabila suci. (Ibnu Hazm di dalam kitabnya al-Muhalla)
Puasa.
Wanita yang sedang nifas tidak boleh melakukan puasa wajib maupun sunnah. Akan tetapi ia wajib mengqadha puasa wajib yang ia tinggalkan pada masa nifas. Berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu ‘anha, “Ketika kami mengalami haid, kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (Muttafaq ‘alaih)
Thawaf.
Wanita haid dan nifas diharamkan melakukan thawaf keliling ka’bah, baik yang wajib maupun sunnah, dan tidah sah thawafnya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu ‘anha, “Lakukanlah apa yang dilakukan jamaah haji, hanya saja jangan melakukan thawaf di ka’bah sampai kamu suci.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Jima’.
(lihat sub judul “Hukum Suami yang Bercampur dengan Istri yang sedang Nifas”)
Tidak bleh diceraikan.
Diharamkan bagi suami menceraikan istrinya yang sedang haid atau nifas. Allah Ta’ala berfirman, yang artinya, “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (dengan wajar).” (Qs. ath-Thalaq: 1)
Hukum-hukum Seputar Nifas
Tidak ada perbedaan hukum antara haid dan nifas, kecuali beberapa hal di bawah ini:
1. Iddah
Apabila wanita tidak sedang hamil, masa iddah dihitung dengan haid, bukan dengan nifas. Sebagaimana firman Allah Ta’ala, “Wanita-wanita yang dicerai hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’…” (Qs. al-Baqarah: 228)
Menurut Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang dimaksud ‘quru‘ adalah haid, dan inilah pendapat yang lebih kuat, insyaa Allah. Oleh karena itu, masa iddah dihitung berdasarkan haid, bukan nifas. Sebab, jika suami menceraikan istrinya sebelum melahirkan, masa iddahnya habis karena melahirkan, bukan karena nifas. Adapun jika suami menceraikan istrinya setelah melahirkan, maka masa iddahnya adalah sampai sang istri mendapat 3 kali haid.
2. Masa Ila’
Ila’ adalah sumpah seorang laki-laki untuk tidak melakukan jima’ terhadap istrinya selamanya atau lebih dari empat bulan. Setelah masa empat bulan, bila sang istri meminta untuk berhubungan, maka sang suami harus memilih antara jima’ atau bercerai.
Masa haid termasuk hitungan masa ila’, sedangkan masa nifas tidak. Jadi, apabila seorang suami bersumpah untuk tidak berjima’ dengan istrinya, sedangkan istrinya sedang dalam keadaan nifas, maka masa ila’ ditetapkan empat bulan ditambah masa nifas. Setelah masa itu, bila sang istri meminta untuk melakukan jima’, sang suami harus memilih apakah jima’ atau bercerai.
3. Balighnya seorang wanita dihitung dari saat haid pertama kali, bukan nifas.
Hukum Suami yang Bercampur dengan Istri yang sedang Nifas
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata, “Menggauli wanita nifas sama halnya dengan wanita haid, hukumnya haram menurut kesepakatan ulama.” (Lihat Majmu’ Fatawa)
Allah Ta’ala berfirman, yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang wanita haid, maka katakanlah, “Bahwa haid adalah suatu kotoran, maka janganlah kalian mendekati mereka sebelum mereka suci.” (Qs. al-Baqarah: 222)
Seorang suami boleh sekedar bercumbu dengan istri yang sedang nifas asal tidak sampai jima’. Akan tetapi bila sampai terjadi jima’, para ulama berselisih pendapat apakah wajib membayar kaffarah (denda) ataukah tidak (Lihat al-Mughni oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah).
Pendapat yang lebih kuat, insya Allah, wajib membayar kaffarah. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas sradhiyallahu ‘anhu . Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam , ketika berbicara tentang seorang suami yang mencampuri istrinya di waktu haid, Rasulullah bersabda, “Hendaklah ia bershadaqah satu dinar atau separuh dinar.” (Shahih Ibnu Majah no:523, ‘Aunul Ma’bud 1:445 no:261, Nasa’ai I:153, Ibnu Majah 1:210 no:640. Hadits ini dishahihkan oleh Al-Albani)
Adapun apabila seorang wanita telah suci dari nifas sebelum 40 hari, kebanyakan ulama berpendapat bahwa suami tidak dilarang untuk menggaulinya. Dan inilah pendapat yang kuat. Karena tidak ada dalil syar’i yang melarangnya.
Riwayat yang ada hanyalah dari Imam Ahmad dari Utsman bin Abu Al-Ash bahwa istrinya datang kepadanya sebelum empat puluh hari, lalu ia berkata, “Jangan engkau dekati aku!” Akan tetapi, ucapan Utsman tersebut bukan berarti seorang suami terlarang menggauli istrinya. Sikap Utsman tersebut mungkin timbul karena kehati-hatiannya, yaitu khawatir istrinya belum suci benar, atau takut dapat mengakibatkan pendarahan disebabkan senggama atau hal lain. (Lihat al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz)
Karena itu, apabila pada diri seorang suami atau istri timbul keragu-raguan, maka hendaklah memastikan dahulu, apakah sang istri benar-benar telah suci dari darah nifasnya. Karena secara medis, jima’ aman dilakukan bila sang istri telah melewati masa nifas, kecuali bila saat itu sang istri langsung mengalami haid, terjadi perdarahan, atau sedang menjalani terapi tertentu. Apabila masih ragu, hendaklah berkonsultasi dengan dokter. Apakah kondisi sang istri telah normal dan benar-benar pulih secara medis sehingga bisa dicampuri oleh suaminya. Karena dalam hal ini kondisi setiap wanita berbeda-beda. Tidak selayaknya seorang muslim melakukan hal yang berbahaya dan membahayakan orang lain.
Wallahu Ta’ala a’lam.
Maraaji’ :
Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitabil ‘Aziz (Terj.), Syaikh ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al Khalafi (Pustaka As Sunnah)
Darah Kebiasaan Wanita (terjemahan Risalah fid Dima’ Ath-Thabi’iyah lin Nisa), Syaikh Muhammad bin Shalih al Utsaimin (penerbit Darul Haq)
Catatan Daurah Muslimah “Darah Kebiasaan Wanita” oleh ustadz Abu Ukkasyah Aris Munandar, tahun 2007
Catatan Kajian Al Wajiz oleh ustadz Muslam, tahun 2004
**************
Penulis: Ummu Rumman Siti Fatimah
Muraja’ah: ustadz Abu Ukkasyah Aris Munandar
http://muslimah.or.id/fikih/hukum-seputar-darah-wanita-darah-nifas.html
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 6:42 pm 0 comments
Labels: ~ Fiqh Dan Ibadah ~
Wednesday, 27 October 2010
~ Hukum Seputar Darah Wanita: Istihadlah ~
.jpg)
Definisi Istihadlah
Di kalangan wanita ada yang mengeluarkan darah dari farji’ (vagina)-nya di luar kebiasaan bulanan dan bukan karena sebab kelahiran. Darah ini diistilahkan sebagai darah istihadlah. Al Imam An Nawawi rahimahullaah dalam penjelasaannya terhadap Shahih Muslim mengatakan: “Istihadlah adalah darah yang mengalir dari kemaluan wanita bukan pada waktunya dan keluarnya dari urat.” (Shahih Muslim bi Syarhin Nawawi 4/17, Fathul Bari 1/511)
Al Imam Al Qurthubi rahimahullaah mensifatkannya dengan darah segar yang di luar kebiasaan seorang wanita disebabkan urat yang terputus (Jami’ li Ahkamil Qur’an 3/57).
Syaikh Al Utsaimin rahimahullaah memberikan definisi istihadlah dengan darah yang terus menerus keluar dari seorang wanita dan tidak terputus selamanya atau terputus sehari dua hari dalam sebulan. Dalil keadaan yang pertama (darahnya tidak terputus selama-lamanya) dibawakan Al Imam Al Bukhari dalam Shahihnya dari hadits ‘Aisyah radhiallaahu ‘anha, ia berkata: “Fathimah bintu Abi Hubaisy berkata kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak pernah suci…’ “ (HR. Bukhari no. 306, 328, dan Muslim 4/16-17) Dalam riwayat lain: ‘Aku istihadlah tidak pernah suci… .’
Adapun dalil keadaan kedua adalah hadits Hamnah bintu Jahsyin radhiallaahu ‘anha ketika dia datang kepada Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam dan mengadukan keadaan dirinya: “Aku pernah ditimpa istihadlah (darah yang keluar) sangat banyak dan deras…” (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi dan dishahihkannya. Dinukilkan dari Al Imam Ahmad akan penshahihan beliau terhadap hadits ini dan dari Al Imam Al Bukhari penghasanannya). (Terj. Risalah fid Dima’, hal. 40)
Antara Darah Haid dan Darah Istihadlah
Ketika Rasulullah Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam diadukan oleh Hamnah radhiallaahu ‘anha tentang istihadlah yang menimpanya, beliau berkata, “Yang demikian hanyalah satu gangguan/dorongan dari setan.”
Atau dalam riwayat Shahihain dari hadits Fathimah bintu Abi Hubaisy, beliau mengatakan tentang istihadlah, “Yang demikian itu hanyalah darah dari urat, bukan haid.”
Hal ini menunjukkan bahwa istihadlah tidak sama dengan haid yang sifatnya alami, yaitu yang pasti dialami oleh setiap wanita normal sebagai salah satu tanda baligh. Namun istihadlah adalah satu penyakit yang menimpa kaum hawa dari perbuatan setan yang ingin menimbulkan keraguan pada anak Adam dalam pelaksanaan ibadahnya. Kata Al Imam As Shan’ani dalam Subulus Salam (1/159): “Makna sabda Nabi: (’Yang demikian hanyalah satu dorongan/gangguan dari syaithan’) adalah setan mendapatkan jalan untuk membuat kerancuan terhadapnya dalam perkara agamanya, masa sucinya dan shalatnya hingga setan menjadikannya lupa terhadap kebiasaan haidnya.” Al Imam As Shan’ani melanjutkan: “Hal ini tidak menafikkan sabda Nabi yang mengatakan bahwa darah istihadlah dari urat yang dinamakan ‘aadzil karena dimungkinkan syaithan mendorong urat tersebut hingga terpancar darah darinya.” (Subulus Salam 1/159)
Keberadaan darah istihadlah bersama darah haid merupakan suatu masalah yang rumit. Sehingga menurut Ibnu Taimiyyah, keduanya harus dibedakan. Caranya bisa dengan ‘adat (kebiasaan haid) atau dengan tamyiz (membedakan sifat darah).
Perbedaan antara darah istihadlah dengan darah haid adalah darah haid merupakan darah alami, biasa dialami wanita normal dan keluarnya dari rahim sedangkan darah istihadlah keluar karena pecahnya urat, sifatnya tidak alami (tidak mesti dialami setiap wanita) serta keluar dari urat yang ada di sisi rahim. Ada perbedaan lain dari sifat darah haid bila dibandingkan dengan darah istihadlah:
Perbedaan warna. Darah haid umumnya hitam sedangkan darah istihadlah umumnya merah segar.
Kelunakan dan kerasnya. Darah haid sifatnya keras sedangkan istihadlah lunak.
Kekentalannya. Darah haid kental sedangkan darah istihadlah sebaliknya.
Aromanya. Darah haid beraroma tidak sedap/busuk.
Keadaan Wanita yang Istihadlah
Wanita yang istihadlah ada beberapa keadaan:
Pertama: Dia memiliki kebiasaan haid yang tertentu sebelum ia ditimpa istihadlah. Hingga tatkala keluar darah dari kemaluannya untuk membedakan apakah darah tersebut darah haid atau darah istihadlah, ia kembali kepada kebiasaan haidnya yang tertentu. Dia meninggalkan shalat dan puasa di hari-hari kebiasaan haidnya dan berlaku padanya hukum-hukum wanita haid, adapun di luar kebiasaan haidnya bila keluar darah maka darah tersebut adalah darah istihadlah dan berlaku padanya hukum-hukum wanita yang suci.
Misalnya: Seorang wanita haidnya datang selama enam hari di tiap awal bulan. Kemudian dia ditimpa istihadlah dimana darahnya keluar terus-menerus. Maka cara dia menetapkan apakah haid dan istihadlah adalah enam hari yang awal di tiap bulannya adalah darah haid sedangkan selebihnya adalah darah istihadlah. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah radhiallahu ‘anha yang mengabarkan kedatangan Fathimah bintu Abi Hubaisy guna mengadu kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, “Wahai Rasulullaah, sesungguhnya aku tidak suci maka apakah aku harus meninggalkan shalat?” Nabi menjawab : “(Tidak, engkau tetap mengerjakan shalat). Itu hanyalah darah karena terputusnya urat. Apabila datang saat haidmu tinggalkanlah shalat dan bila telah berlalu hari-hari yang kau biasa haid, kemudian mandilah dan shalatlah.” (HR. Bukhari)
Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwasannya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam berkata kepada Ummu Habibah bintu Jahsyin, “Diamlah engkau (tinggalkan shalat) sekadar hari-hari haidmu kemudian mandilah dan setelah itu shalatlah.” (HR. Muslim 4/25-26)
Dengan demikian, wanita yang keadaannya seperti ini dia meninggalkan shalat di hari-hari kebiasaan haidnya kemudian dia mandi, setelah itu ia boleh mengerjakan shalat dan tidak perlu mempedulikan darah yang keluar setelah itu karena darah tersebut adalah darah istihadlah dan dia hukumnya sama dengan wanita yang suci.
Keadaan kedua: Wanita itu tidak memiliki kebiasaan haid yang tertentu (mubtada’ah) sebelum ia ditimpa istihadlah namun ia bisa membedakan darah (mumayyizah). Maka untuk membedakan sifat darah haid dan darah istihadlah menggunakan cara tamyiz (pembedaan sifat darah). Darah haid dikenal dengan warnanya yang hitam, kental dan beraroma tidak sedap. Bila dia dapatkan demikian, maka berlaku padanya hukum-hukum haid sedangkan di luar dari itu berarti dia istihadlah.
Misalnya: seorang wanita melihat darah keluar dari kemaluannya terus-menerus, akan tetapi sepuluh hari yang awal dia melihat darahnya hitam sedangkan selebihnya berwarna merah, atau sepuluh hari awal berbau darah haid selebihnya tidak berbau, berarti sepuluh hari yang awal itu dia haid, selebihnya istihadlah, berdasarkan ucapan Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kepada Fathimah bintu Abi Hubaisy, “Apabila darah itu darah haid maka dia berwarna hitam yang dikenal. Apabila demikian berhentilah dari shalat. Namun bila bukan demikian keadaannya berwudlulah dan shalatlah karena itu adalah darah penyakit.” (HR. Abu Daud, An Nasa’i, dan lain-lain. Dishahihkan oleh As Syaikh Al Albani rahimahullaah)
Bila seorang wanita yang istihadlah punya ‘adat haid dan bisa membedakan sifat darah (tamyiz), manakah yang harus dia dahulukan, ‘adat atau tamyiz? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu. Ada yang berpendapat tamyiz yang didahulukan sebagaimana pendapatnya Imam Malik, Ahmad, dan Syafi’i. Mereka berdalil dengan hadits Fathimah bintu Abu Hubaisy di atas. Ada pula yang berpendapat ‘adat didahulukan sebagaimana pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat ini yang dikuatkan Ibnu Taimiyyah dan juga Syaikh Ibnu Utsaimin. Dengan demikian bila ada seorang wanita memiliki ‘adat (kebiasaan haid) 5 hari, pada hari keempat dari ‘adat-nya keluar darah berwarna merah (sebagaimana darah istihadlah) namun pada hari kelima darah yang keluar kembali berwarna hitam maka ia berpegang dengan ‘adat-nya yang lima hari, sehingga hari keempat (yang keluar darinya darah berwarna merah) tetap terhitung dalam hari haidnya. Pendapat inilah yang lebih kuat. Wallahu A’lam.
Keadaan ketiga: Wanita itu tidak memiliki kebiasaan haid dan tidak pula dapat membedakan darahnya. Darah keluar terus-menerus sejak awal dia melihat darah keluar dari kemaluannya dan sifatnya sama atau tidak jelas perbedaannya. Maka untuk membedakan haid dan istihadlahnya adalah melihat kebiasaan kebanyakan wanita yaitu dia menganggap dirinya haid selama enam atau tujuh hari pada setiap bulannya dan dimulai sejak awal dia melihat keluarnya darah. Selebihnya berarti istihadlah.
Misalnya: seorang wanita melihat darah pertama kalinya pada hari Kamis bulan Ramadhan dan darah itu terus keluar tanpa dapat dibedakan apakah haid ataukah selainnya maka dia menganggap dirinya haid selama enam atau tujuh hari, dimulai dari hari Kamis.
Hal ini berdasarkan hadits Hamnah bintu Jahsyin radhiallaahu ‘anha dimana beliau mengalami istihadlah yang banyak dan deras, maka beliau meminta fatwa pada Nabi Shallallaahu’alaihi wa sallam. Beliau Shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda, ‘Yang demikian itu hanyalah satu gangguan dari syaithan maka berhaidlah engkau selama enam atau tujuh hari, kemudian setelah lewat dari itu mandilah, hingga engkau lihat dirimu telah suci maka shalatlah selama 24 atau 23 siang malam, puasalah dan shalatlah. Maka hal tersebut mencukupimu. Demikianlah, lakukan hal ini setiap bulannya sebagaimana para wanita berhaid.’” (Hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi. Menurut Ahmad dan Tirmidzi hadits shohih, sedang menurut Imam Bukhoriy, hadits hasan)
Kata Al Imam As Shan’ani: “Dalam hadits ini (untuk menentukan haid dengan yang selainnya) Nabi mengembalikan kepada kebiasaan umumnya para wanita.” (Subulus Salam 1/159)
Wanita yang memiliki keadaan seperti ini, ia menganggap dirinya suci selama 24 hari bila kebiasaan haidnya enam hari atau ia menganggap dirinya suci selama 23 hari bila kebiasaan haidnya tujuh hari. Untuk menentukan enam atau tujuh hari bukan dengan seenaknya memilih namun dengan melihat kepada wanita lain yang paling dekat kekerabatannya dan berdekatan umur dengannya. Al Imam As Shan’ani mengatakan : “Ucapan Nabi dalam hadits: ((Berhaidlah engkau selama enam atau tujuh hari)) ini bukanlah syak (keraguan) dari rawi (yakni rawi ragu apakah Nabi mengatakan enam atau tujuh) dan bukan pula takhyir (disuruh memilih antara enam atau tujuh, -pent). Nabi mengatakan demikian untuk mengumumkan bahwasannya para wanita memiliki salah satu dari dua ‘adat (enam atau tujuh). Di antara mereka ada yang berhaid enam hari dan ada yang tujuh hari. Maka seorang wanita (yang meiliki kebiasaan seperti itu) mengembalikan kebiasaannya kepada wanita yang sama usia dengannya dan memiliki keserupaan (rahim) dengannya.” (Subulus Salam hal. 160)
Para ahli fikih berkata: “Apabila wanita yang istihadlah memiliki ‘adat (kebiasaan) yang tetap dan pasti, maka ia berhenti shalat dan puasa pada hari-hari ‘adat-nya tersebut (bila ia melihat darah) karena ‘adat lebih kuat dari selainnya. Apabila ia tidak mengetahui ‘adat-nya maka ia melakukan tamyiz (membedakan darah). Apabila ia tidak mampu membedakan darah maka ia melihat kebiasaan umumnya wanita.” (Bulughul Maram dengan catatan kaki yang berisi pembahasan As Syaikh Al Albani. Penjelasan Abdullah Al Bassam dan beberapa ulama Salaf, halaman 54)
Apabila kebiasaan wanita yang seumur dan paling dekat kekerabatan dengannya itu bukan enam atau tujuh hari (misalnya sepuluh hari), maka dia tetap harus berpedoman dengan kebiasaan wanita tersebut yaitu sepuluh hari. Allahu Ta’ala A’lam.
Kondisi keempat dan kelima: Jika wanita tersebut memliki kebiasaan haid tertentu, namun haidnya tidak teratur bilangannya (muktaribah), maka jika masih memungkinkan melakukan tamyiz, maka kondisinya disesuaikan dengan wanita dengan kondisi kedua di atas.
Kondisi keenam: Wanita yang memiliki kebiasaan, namun lupa waktu dan bilangan hari haidnya dan tidak dapat membedakannya sementara darah terus-menerus keluar, maka ulama berselisih pendapat mengenai masalah ini. Ada yang berkata hukumnya sama dengan wanita baru haid yang tidak dapat membedakan darahnya (mubtada-ah). Ada yang berkata: Untuk kehati-hatian dia anggap dirinya haid hingga tidak halal bagi suaminya untuk menggaulinya dan di sisi lain dia anggap dirinya suci hingga ia terus shalat dan puasa. Ada yang mengatakan dia menetapkan hari-hari haidnya setiap awal bulan dan jumlah harinya sama dengan wanita di sekitarnya. Yang lain mengatakan dia harus berusaha sungguh-sungguh untuk membedakan darahnya semampu dia dan berusaha mengingat keadaan haidnya. (Majmu’ Syarhil Muhadzdzab 2/396). Yang rojih, menurut Syaikh Utsaimin dalam Syarhul Mumti’, adalah mengembalikannya pada kebiasaan wanita yang lain namun dalam hal ini lebih dipersempit. Misalnya wanita itu hanya ingat bahwa ia haid di awal bulan, namun lupa tanggal berapa. Kemudian keluar darah terus menerus. Ibu wanita tersebut memiliki haid yang teratur setiap awal bulan pada tanggal tertentu, demikian pula dengan saudara wanitanya hanya saja di akhir bulan. Maka wanita tersebut harus menetapkan tanggal haidnya sesuai tanggal haid ibunya, meski kekerabatan rahim dan umurnya lebih mendekati saudara wanitanya.
Kondisi ketujuh: Jika ia tahu bilangan/durasi haidnya dan letaknya (awal, tengah atau akhir), namun ia lupa tepatnya tanggal berapa ia haid, maka ada perbedaan pendapat di antara ulama. Sebagian mengatakan bahwa dia harus mengambil tanggal haidnya di awal bulan (meski ia yakin biasa haid di tengah bulan). Akan tetapi, menurut Syaikh ‘Utsaimin dalam Syarhul Mumti’ yang lebih mendekati pada kenyataan sebenarnya adalah mengambil tanggal pasti dari awal, tengah, atau akhir bulan. Misal wanita tersebut yakin ia haid di tengah bulan namun lupa tanggal berapa. Maka yang lebih mendekati kebenaran adalah ia menetapkan tanggal haidnya adalah tanggal 13, daripada menetapkan tanggal haidnya di awal bulan.
Hukum-Hukum Istihadlah
Hukum wanita yang istihadlah sama seperti hukum wanita yang suci kecuali pada hal berikut ini:
1. Wanita istihadlah bila ingin wudlu maka ia mencuci bekas darah dari kemaluannya dan menahan darahnya dengan kain (pembalut) berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam kepada Hamnah radhiyallaahu’anha: “Aku beritahukan kepadamu (untuk menggunakan) kapas karena dia mampu menyerap darah’. Hamnah radhiyallaahu’anha berkata, ‘Darahnya lebih banyak dari itu. Beliau Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda,’Gunakan kain’. Hamnah berkata,’darahnya lebih banyak dari itu’. Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda, ‘Gunakan penahan’.”
Dalam hal senggama dengan istri yang sedang istihadlah, ulama telah berselisih tentang kebolehannya, namun tidak dinukilkan dari Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam adanya larangan, padahal banyak wanita yang ditimpa istihadlah pada masa beliau. Dan juga Allah Ta’ala berfirman yang artinya, “Maka jauhilah (jangan menyetubuhi) para istri ketika mereka sedang haid.” (Al Baqarah: 222). Dalam ayat ini, Allah Ta’ala hanya menyebutkan haid, yang berarti selain haid tidak diperintahkan untuk menjauhi istri. (Risalah fid Dimaa’ hal. 50)
Apakah Wajib Mandi Setiap Akan Shalat?
‘Aisyah radhiallahu ‘anha mengatakan bahwa Ummu Habibah istihadlah selama 7 tahun dan ia menanyakan perkaranya kepada Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Maka beliau memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi dan beliau mengatakan: “Darah itu dari urat. Adalah Ummu Habibah mandi setiap akan shalat.” (HR. Bukhari dalam Shahih-nya nomor 317 dan Muslim halaman 23)
Al Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalan Al Laits bin Sa’ad dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah. Dan pada akhir hadits, Al Laits berkata: “Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memerintahkan Ummu Habibah bintu Jahsyin radhiallahu ‘anha untuk mandi setiap akan shalat, akan tetapi hal itu dilakukan atas kehendak Ummu Habibah sendiri. Dengan demikian Al Laits berpendapat mandi setiap akan shalat bagi wanita istihadlah bukanlah dari perintah Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam. Dan apa yang dipandang oleh Al Laits ini juga merupakan pendapat jumhur ulama sebagaimana dinukil dari mereka oleh Al Imam An Nawawi dalam Syarhu Muslim (4/19) dan Al Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari 1/533. Al Imam An Nawawi berkata: “Ketahuilah tidak wajib bagi wanita istihadlah untuk mandi ketika akan mengerjakan shalat, tidak pula wajib mandi dari satu waktu yang ada kecuali sekali saja setiap berhentinya haid. Dengan ini berpendapat Jumhur Ulama dari kalangan Salaf dan Khalaf.” (4/19-20)
Adapun hadits yang ada tambahan lafadz: “Nabi memerintahkannya (Ummu Habibah) untuk mandi setiap akan shalat.” Adalah tambahan yang syadz karena Ibnu Ishaq -seorang perawi hadits ini- salah dalam membawakan riwayat sementara para perawi lainnya yang lebih kuat, meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab dengan lafadh: “Adalah Ummu Habibah mandi setiap akan shalat.” Dan perbedaan antara kedua lafadh ini jelas sekali. Bahkan Laits bin Sa’ad dan Sufyan Ibnu ‘Uyainah -dua dari perawi yang kuat- jelas-jelas mengatakan dalam riwayat Abu Daud bahwasannya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak memerintah Ummu Habibah untuk mandi. (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/220-221) jelas sekali. Bahkan Laits bin Sa’ad dan Sufyan Ibnu ‘Uyainah -dua dari perawi yang kuat- jelas-jelas mengatakan dalam riwayat Abu Daud bahwasannya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak memerintah Ummu Habibah untuk mandi. (Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/220-221)
As Syaikh Shiddiq berkata dalam Syarah Ar Raudlah: “Tidak datang dalam satu hadits pun (yang shahih) adanya kewajiban mandi untuk setiap shalat (bagi wanita istihadlah), tidak pula mandi setiap dua kali shalat dan tidak pula setiap hari. Tapi yang shahih adalah kewajiban mandi ketika selesai dari waktu haid yang biasanya (menurut ‘adat) atau selesainya waktu haid dengan tamyiz sebagaimana datang dalam hadits Aisyah dalam Shahihain dan selainnya dengan lafadz: “Maka apabila datang haidmu, tinggalkanlah shalat dan bila berlalu cucilah darah darimu dan shalatlah.” Adapun dalam Shahih Muslim disebutkan Ummu Habibah mandi setiap akan shalat maka ini bukanlah dalil karena hal itu dilakukan atas kehendaknya sendiri dan bukan diperintahkan oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam, bahkan yang ada, Nabi mengatakan kepadanya: “Diamlah engkau (tinggalkan shalat) sekadar hari haidmu kemudian (bila telah suci) mandilah.” (Bulughul Maram halaman 53 dengan catatan kaki pembahasan As Syaikh Al Albani dan lain-lain)
Ibnu Taimiyyah berpendapat sebagaimana dinukil dalam kitab Bulughul Maram (halaman 53 dengan catatan kaki) bahwasannya mandi setiap shalat ini hanyalah sunnah, tidak wajib menurut pendapat imam yang empat, bahkan yang wajib bagi wanita istihadlah adalah wudlu setiap shalat lima waktu menurut pendapat jumhur, di antaranya Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad.
Apakah Wajib Wudlu Setiap Akan Shalat?
Al Imam Al Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada ‘Aisyah radhiallahu ‘anha bahwasannya Fathimah bintu Abi Hubaisy datang kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam dan mengadukan istihadlah yang menimpanya dan ia bertanya: “‘Apakah aku harus meninggalkan shalat?’ Maka Nabi mengatakan, ‘Tidak itu hanyalah urat bukan haid, maka apabila datang haidmu tinggalkanlah shalat dan jika berlalu maka cucilah darah haidmu kemudian shalatlah.’ “ (HR. Bukhari: 228)
Hadits di atas dalam riwayat Nasa’i dari jalan Hammad bin Zaid ada tambahan lafadz: “Berwudlulah” setelah lafadz: “Cucilah darah haidmu”. Sehingga dalam riwayat Nasa’i, lafadz hadits di atas adalah: “Cucilah darah haidmu, wudlulah, dan shalatlah.” (HR. Nasa’i 1/185)
Al Imam Muslim ketika meriwayatkan hadits ini dalam Shahih-nya (4/21) tanpa tambahan di atas sebagaimana Al Imam Al Bukhari membawakan tanpa tambahan. Al Imam Muslim memberikan isyarat lemahnya tambahan tersebut dengan ucapannya: “Dalam hadits Hammad bin Zaid ada tambahan yang kami tinggalkan penyebutannya.”
Kata Al Imam An Nawawi rahimahullah dalam Syarah Muslim mengutip ucapan Qadli ‘Iyyadl: “Tambahan yang ditinggalkan penyebutannya oleh Al Imam Muslim adalah: ((“watawadl-dla’i/ berwudlulah”)). An Nasa’i dan lainnya menyebutkan tambahan ini, sedangkan Imam Muslim membuangnya karena Hammad, salah seorang perawi hadits ini, bersendiri dalam menyebutkan tambahan tersebut (adapun perawi-perawi lain tidak menyebut tambahan: ‘Berwudlulah’ pent.). An Nasa’i sendiri mengatakan: “Kami tidak mengetahui adanya seorang pun selain Hammad yang mengatakan/menyebutkan: ‘Berwudlulah’ ” (Syarah Muslim 4/22)
Demikian pula Imam Tirmidzi, Darimi, Ahmad, dan Nasa’i sendiri dari jalan Khalid Ibnul Harits dan Malik meriwayatkan tanpa tambahan di atas. (Lihat Jami’ Ahkamin Nisa’ 1/224- 226).
Kesimpulannya: Perintah wudlu bukanlah datang dari Nabi Shallallaahu ‘Alaihi Wa Sallam dan perintah yang datang dalam masalah ini adalah lemah sebagaimana dilemahkan oleh para ulama. Namun jangan sampai dipahami bahwa yang wajib adalah mandi setiap shalat dan sudah lewat penyebutan kami tentang masalah mandi bagi wanita istihadlah ini. Walhamdulillah.
Maroji’:
Darah yang Menimpa Wanita, [MUSLIMAH Rubrik Kajian Kita Edisi 37/1421 H/2001 M], Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyyah.
Istihadlah, [MUSLIMAH Edisi 41/1423 H/2002 M Rubrik Kajian Kita ]., Ummu Ishaq Zulfa Husein Al Atsariyah.
Risalah fi Ad Dima’ Ath Thabi’iyyah lin Nisa’ (Terj. Darah Kebiasaan Wanita), Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin.
Darah Kebiasaan Wanita, rekaman dauroh, al Ustadz Ibnu Yunus.
**************
Penulis: Ummu Muhammad
Muroja’ah: Ustadz Abu ‘Ukkasyah Aris Munandar
http://muslimah.or.id/fikih/hukum-seputar-darah-wanita-istihadlah.html
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 7:05 pm 0 comments
Labels: ~ Fiqh Dan Ibadah ~
Monday, 25 October 2010
~ Derita Bisa Jadi Nikmat ~

Sebuah pelajaran berharga dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Semoga dapat menghibur hati yang sedang luka atau merasakan derita.
Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan:
Di antara sempurnanya nikmat Allah pada para hamba-Nya yang beriman, Dia menurunkan pada mereka kesulitan dan derita. Disebabkan derita ini mereka pun mentauhidkan-Nya (hanya berharap kemudahan pada Allah, pen). Mereka pun banyak berdo’a kepada-Nya dengan berbuat ikhlas. Mereka pun tidak berharap kecuali kepada-Nya. Di kala sulit tersebut, hati mereka pun selalu bergantung pada-Nya, tidak beralih pada selain-Nya. Akhirnya mereka bertawakkal dan kembali pada-Nya dan merasakan manisnya iman. Mereka pun merasakan begitu nikmatnya iman dan merasa berharganya terlepas dari syirik (karena mereka tidak memohon pada selain Allah). Inilah sebesar-besarnya nikmat atas mereka. Nikmat ini terasa lebih luar biasa dibandingkan dengan nikmat hilangnya sakit, hilangnya rasa takut, hilangnya kekeringan yang menimpa, atau karena datangnya kemudahan atau hilangnya kesulitan dalam kehidupan. Karena nikmat badan dan nikmat dunia lainnya bisa didapati orang kafir dan bisa pula didapati oleh orang mukmin. (Majmu’ Al Fatawa, Ibnu Taimiyah, Darul Wafa’, 10/333)
***
Begitu sejuk mendengar kata indah dari Ibnu Taimiyah ini. Akibat derita, akibat musibah, akibat kesulitan, kita pun merasa dekat dengan Allah dan ingin kembali pada-Nya. Jadi tidak selamanya derita adalah derita. Derita itu bisa jadi nikmat sebagaimana yang beliau jelaskan. Derita bisa bertambah derita jika seseorang malah mengeluh dan jadikan makhluk sebagai tempat mengeluh derita. Hanya kepada Allah seharusnya kita berharap kemudahan dan lepas dari berbagai kesulitan.
Nikmat ketika kita kembali kepada Allah dan bertawakkal pada-Nya serta banyak memohon pada-Nya, ini terasa lebih nikmat dari hilangnya derita dunia yang ada. Karena kembali pada Allah dan tawakkal pada-Nya hanyalah nikmat yang dimiliki insan yang beriman dan tidak didapati para orang yang kafir. Sedangkan nikmat hilangnya sakit dan derita lainnya, itu bisa kita dapati pada orang kafir dan orang beriman.
Ingatlah baik-baik nasehat indah ini. Semoga kita bisa terus bersabar dan bersabar. Sabar itu tidak ada batasnya. Karena Allah Ta’ala janjikan,
إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ
“Sesungguhnya orang-orang yang bersabar, ganjaran bagi mereka adalah tanpa hisab (tak terhingga).” (QS. Az Zumar: 10).
Al Auza’i mengatakan bahwa ganjarannya tidak bisa ditakar dan ditimbang. Ibnu Juraij mengatakan bahwa pahala bagi orang yang bersabar tidak bisa dihitung sama sekali, akan tetapi ia akan diberi tambahan dari itu. Maksudnya, pahala mereka tak terhingga. Sedangkan As Sudi mengatakan bahwa balasan bagi orang yang bersabar adalah surga.[1]
Semoga yang singkat ini bermanfaat. Alhamdulillahilladzi bi ni’matihi tatimmush sholihaat.
Written before Shubuh on 16 Dzulqo’dah 1431 H (24/10/2010), in KSU, Riyadh, KSA
By: Muhammad Abduh Tuasikal
www.rumaysho.com
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 10:39 pm 0 comments
Labels: ~ Bekalan Rohani ~
Friday, 15 October 2010
~ Wasiat Perpisahan ~ *****

Diriwayatkan dari al-‘Irbâdh bin Sâriyah radhiallahu'anhu bahwa ia berkata, “Suatu hari Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam pernah shalat bersama kami, kemudian beliau menghadap kepada kami, lalu memberikan nasehat kepada kami dengan nasehat yang membekas pada jiwa, yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati menjadi takut, maka seseorang berkata, ‘Wahai Rasulullâh! Seolah-olah ini adalah nasehat dari orang yang akan berpisah, maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami?’
Maka Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Aku wasiatkan kepada kalian agar tetap bertakwa kepada Allah, tetaplah mendengar dan taat, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, niscaya ia akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib atas kalian berpegang teguh dengan Sunnahku dan Sunnah Khulafâ Râsyidîn yang mendapat petunjuk. Peganglah erat-erat dan gigitlah dia dengan gigi geraham kalian. Dan jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru (dalam agama), karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid‘ah, dan setiap bid‘ah itu adalah sesat."
Takhrij Hadist
Hadits ini shahîh, diriwayatkan oleh Imam-imam Ahlul Hadits, di antaranya adalah Imam Ahmad dalam Musnadnya 7/126-127, Imam Abu Dâwud no. 4607 dan ini lafazhnya, Imam at-Tirmidzi no. 2676, Imam Ibnu Mâjah no. 42, Imam ad-Dârimi 1/44, Imam Ibnu Hibbân dalam Shahîhnya no. 5, At-Ta’lîqâtul Hisân dan no. 102, al-Mawârid, Imam al-Hâkim 1/95-96, Imam Ibnu Abi ‘Ashim dalam As-Sunnah no. 54-59, Imam al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah 1/205, no. 102, Imam al-Baihaqi dalam Sunannya 10/114, Imam al-Lâlikâi dalam Syarah Ushûl I’tiqâd Ahlis Sunnah wal Jamâ’ah 1/ 83, no. 81 dan lain-lain.
Hadits ini dishahîhkan oleh para Imam Ahlul Hadits. Imam at-Tirmidzi rahimahullah mengatakan, “Hadits ini hasan shahîh.” Imam al-Bazzâr rahimahullah mengatakan, “Hadits ini tsâbit shahîh.” Imam Ibnu ‘Abdil Barr mengatakan, “Hadits ini tsâbit.” Imam al-Hâkim rahimahullah mengatakan, “Hadits ini shahîh dan tidak ada cacatnya,” dan disetujui oleh Imam adz-Dzahabi rahimahullah. Hadits ini dishahîhkan juga oleh Imam al-‘Allâmah al-Muhaddits Muhammad Nâshiruddîn al-Albâni rahimahullah dalam Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah no. 937 dan 2735 dan dalam Irwâ-ul Ghalîl 8/107-109, no. 2455
Disyariatkannya Memberikan Nasihat
Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam memberikan nasehat kepada para Sahabatnya, kemudian seorang Sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullâh! Nasihat ini seakan-akan nasihat dari orang yang akan berpisah, maka apakah yang engkau wasiatkan kepada kami?".
Ini menunjukkan bahwa Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam amat serius dalam memberikan nasehat tersebut dan tidak seserius itu pada nasehat yang lainnya. Oleh karena itu, para Sahabat paham bahwa nasehat tersebut adalah nasehat orang yang akan berpisah, karena orang yang akan berpisah dapat mempunyai pengaruh dalam perkataan dan perbuatan yang tidak bisa dikerjakan orang lain. Karenanya, Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam memerintahkan seseorang shalat seperti shalatnya orang yang akan berpisah, ia akan mengerjakannya sesempurna mungkin.
Agama adalah nasehat. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda yang artinya, “Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Mereka (para Sahabat) bertanya: ‘Untuk siapa, wahai Rasulullâh?’ Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalammenjawab: ‘Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin kaum Muslimin atau Mukminin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.”
Nasehat merupakan hak seorang Muslim atas Muslim yang lainnya. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda yang artinya, “Hak orang Muslim atas Muslim lainnya ada enam. Ditanyakan, “Apa saja keenam hak tersebut, wahai Rasulullâh?” Beliau menjawab, “Jika engkau bertemu dengannya maka ucapkanlah salam kepadanya, jika ia mengundangmu maka penuhilahnya, jika ia meminta nasihat kepadamu maka nasihatilah dia, jika ia bersin kemudian memuji Allah maka doakan dia (dengan ucapan: yarhamukallâh), jika ia sakit maka jenguklah, dan jika ia meninggal dunia maka antarkan (jenazah)nya.”
Prinsip dalam memberikan nasehat ialah harus ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala dan mengikuti contoh Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam, bukan dengan membuka aib orang yang dinasehati. Sebab, orang yang aibnya dibuka tidak akan mau menerima nasehat. Begitu juga dengan menuduh orang lain. Orang yang dituduh, akan sulit baginya untuk menerima nasehat karena menuduh tidaklah sama dengan memberi nasehat. Sebaliknya juga orang yang diberikan nasehat jangan menuduh orang yang memberikan nasehat dengan tuduhan yang jelek.
Keutamaan Salafush Shalih
Perkataan al-‘Irbâdh bin Sâriyah radhiallahu'anhu,
“Lalu memberikan nasehat kepada kami dengan nasehat yang membekas pada jiwa, yang menjadikan air mata berlinang dan membuat hati menjadi takut...”
Di dalamnya terdapat isyarat tentang baiknya keadaan para Sahabat, bersihnya jiwa-jiwa mereka, dan selamatnya hati-hati mereka. Mereka mengambil pelajaran dari sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam, merasa takut tatkala mendengar firman Allah Ta'ala , dan ini merupakan tanda keimanan dan kebaikan. Menangis dan rasa takut hati ketika mendengar peringatan dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya adalah dua sifat kaum Mukminin yang dipuji oleh Allah Ta'ala . Seperti firman Allah Ta'ala yang artinya,
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut Nama Allah gemetar (takutlah) hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Rabb mereka bertawakkal.”
(Qs al-Anfâl/8:2)
Sesungguhnya orang yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala , matanya itu tidak akan disentuh api neraka. Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda, Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api Neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah Ta'ala dan mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah Ta'ala.
Maksud dari dua mata yang begadang untuk berjaga di jalan Allah Ta'ala ialah ketika berjuang di jalan Allah Ta'ala melawan musuh, ia senantiasa berjaga-jaga di perbatasan karena khawatir kaum Muslimin diserang oleh musuh. Oleh karena itu, wajib mencintai para Sahabat radhiallahu'anhum, memuliakan mereka, memohonkan ampunan dan keridhaan Allah Ta'ala untuk mereka, dan mengikuti contoh teladan mereka. Mereka adalah pendahulu umat ini yang telah menyampaikan al-Qur‘ân dan Sunnah Nabi-Nya kepada kita.
Para Ulama menjelaskan bahwa siapapun tidak boleh mencela dan mencaci-maki para Sahabat radhiallahu'anhum karena baiknya hati mereka. ‘Abdullâh bin Mas’ûd radhiallahu'anhu mengatakan tentang para Sahabat Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam, Barangsiapa di antara kalian yang ingin mengambil teladan, hendaklah mengambil teladan dari para Sahabat Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam. Karena sesungguhnya mereka adalah umat yang paling baik hatinya, paling dalam ilmunya, paling sedikit bebannya, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Suatu kaum yang Allah Ta'ala telah pilih untuk menemani Nabi-Nya dan untuk menegakkan agama-Nya, maka kenalilah keutamaan mereka serta ikutilah atsar-atsarnya karena mereka berada di atas jalan yang lurus.
Para Salafush Shalih memiliki sekian banyak keutamaan, maka kewajiban kita adalah mencintai, menghormati dan mengikuti jejak mereka, serta memohonkan ampunan, rahmat, dan keridhaan Allah Ta'ala untuk mereka. Maka dianjurkan untuk mengucapkan radhiyallâhu ‘anhum ketika kita menyebut para Sahabat, sebagai realisasi dari firman Allah Ta'ala yang artinya,
“Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Anshar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.” (Qs at-Taubah/9:100)
Tidak boleh ada seorang pun yang mencela dan menjelekkan para Sahabat. Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda, Janganlah kalian mencaci para Sahabatku! Demi Dzat Yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh, jika seandainya salah seorang dari kalian berinfak sebesar Gunung Uhud berupa emas, maka belum mencapai nilai infak mereka meskipun (mereka infak hanya) satu mud (yaitu sepenuh dua telapak tangan) dan tidak juga separuhnya.
Karena itulah Imam Abu Zur’ah ar-Râzi rahimahullah (wafat th. 264 H) berkata, “Apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang dari Sahabat Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam maka ketahuilah bahwa ia adalah zindiq (munafik). Karena sesungguhnya Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam itu benar, sesungguhnya al-Qur`ân itu benar, dan yang menyampaikan al-Qur`ân kepada kita adalah mereka, para Sahabat Rasulullâh. Dan orang-orang yang mencela itu hendak merusak persaksian kita demi membatalkan al-Qur`ân dan Sunnah. Maka celaan itu hanyalah pantas untuk mereka. Mereka adalah orang-orang zindiq.”
Kaum Muslimin dianjurkan untuk mendoakan para Sahabat dengan doa yang terdapat di dalam al-Qur‘ân yang artinya,
“Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu daripada kami, dan janganlah Engkau biarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.” (Qs al-Hasyr/59:10)
Bertakwalah Kepada Allah Ta'ala
Sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah…"
Wasiat takwa adalah wasiat yang paling mulia, wasiat yang menjamin kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang berpegang teguh kepadanya. Dan wasiat takwa merupakan wasiat Allah Ta'ala kepada manusia generasi pertama dan akhir, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya,
“Dan sungguh Kami telah memerintahkan kepada orang yang telah diberikan kitab suci sebelum kamu dan (juga) kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka (ketahuilah) milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”
(Qs an-Nisâ’/4:31)
Takwa yang dimaksud menurut penjelasan para Ulama bukan sekedar melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, namun harus dirinci lagi. Perintah paling besar dalam syari’at adalah mentauhidkan Allahk dan larangan yang terbesar adalah menjauhkan syirik.
Thalq bin Habîb rahimahullah mengatakan, “Takwa ialah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dengan cahaya dari Allah Ta'ala karena mengharap ganjaran dari Allah Ta'ala , dan engkau meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala dengan cahaya dari Allah Ta'ala karena takut terhadap adzab Allah Ta'ala .
Di antara pesan Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam kepada kita semua ialah agar selalu bertakwa dimana pun kita berada. Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda yang artinya, “Bertakwalah kepada Allah dimana pun engkau berada dan iringilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya ia akan menghapuskannya serta bergaullah bersama manusia dengan akhlak yang baik.
Mendengar Dan Taat Kepada Ulil Amri (Penguasa Kaum Muslimin)
Sabda Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"...Mendengar dan taat..."
Maksudnya, mendengar dan taat kepada ulil amri (penguasa) kaum Muslimin. Mendengar apabila mereka berbicara dan menaati apabila mereka memerintahkan sesuatu.
Dalam surat an-Nisâ ayat 59, Allah Ta'ala berwasiat kepada kaum Muslimin agar mereka menaati Allah Ta'ala , Rasul-Nya, dan ulil amri dari kalangan kaum Muslimin yang artinya,
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur`ân) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Qs an-Nisâ’/4:59)
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Tidak boleh taat terhadap perintah yang di dalamnya terdapat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebajikan."
Di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah wajib taat kepada pemimpin kaum Muslimin selama mereka tidak menyuruh berbuat maksiat, meskipun mereka berbuat zhalim. Karena menaati mereka termasuk dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, sedangkan ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah wajib.
Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali kalau ia disuruh untuk berbuat maksiat, jika ia disuruh untuk berbuat maksiyat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat."
Imam al-Qâdhi ‘Ali bin ‘Ali bin Muhammad bin Abil-‘Izz ad-Dimasyqi rahimahullah (yang terkenal dengan Ibnu Abil ‘Izz wafat th. 792 H) berkata, “Hukum menaati ulil amri adalah wajib (selama tidak dalam kemaksiatan) meskipun mereka berbuat zhalim, karena keluar dari ketaatan kepada mereka akan menimbulkan kerusakan yang berlipat ganda dibanding dengan kezhaliman penguasa itu sendiri. Bahkan bersabar terhadap kezhaliman mereka dapat melebur dosa-dosa dan dapat melipat-gandakan pahala. Karena Allah Ta'ala tidak akan menguasakan mereka atas diri kita melainkan disebabkan kerusakan amal perbuatan kita juga. Ganjaran itu bergantung pada amal perbuatan. Maka hendaklah kita bersungguhsungguh memohon ampunan, bertaubat, dan memperbaiki amal perbuatan. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahankesalahan).” (Qs asy-Syûrâ/42:30)
Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, “Dan demikianlah Kami jadikan sebagian orang-orang yang zhalim itu menjadi pemimpin bagi sebagian yang lain disebabkan apa yang mereka usahakan.” (Qs al-An’âm/6:129)
Apabila rakyat ingin selamat dari kezhaliman pemimpin mereka, hendaklah mereka meninggalkan kezhaliman itu juga.”
Syaikh al-Albâni rahimahullah berkata, “Penjelasan di atas sebagai jalan selamat dari kezhaliman para penguasa yang ‘warna kulit mereka sama dengan kulit kita, berbicara sama dengan bahasa kita (bahasa Arab)’ karena itu agar umat Islam selamat:
Hendaklah kaum Muslimin bertaubat kepada Allah Ta'ala.
Hendaknya mereka memperbaiki ‘akidah mereka.
Hendaklah mereka mendidik diri dan keluarganya di atas Islam yang benar sebagai penerapan firman Allah Ta'ala yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri mereka sendiri.” (Qs ar-Ra’d/13:11)
Untuk menghindarkan diri dari kezhaliman penguasa bukan dengan cara mengikuti sangkaan sebagian orang yaitu dengan memberontak, mengangkat senjata ataupun dengan cara kudeta, karena yang demikian itu termasuk bid’ah dan menyalahi nash-nash syariat yang memerintahkan untuk merubah diri kita lebih dahulu. Karena itu harus ada perbaikan kaidah dalam pembinaan, dan pasti Allah Ta'ala menolong hamba-Nya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Kuat, Maha Perkasa.” (Qs al-Hajj/22:40)
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah rahimahullah mengatakan, “Sesungguhnya di antara hikmah Allah Ta'ala dalam keputusan-Nya menjadikan para raja, pemimpin, dan pelindung umat manusia berada satu jenis dengan amal perbuatan mereka, bahkan amal perbuatan mereka seakan-akan tampak tercermin pada pemimpin dan penguasa mereka. Jika mereka lurus, maka akan lurus juga penguasa mereka, dan jika mereka adil, maka akan adil pula penguasa mereka terhadap mereka, tetapi jika mereka zhalim, maka akan zhalim pula penguasa dan pemimpin mereka. Jika tampak tipu muslihat dan penipuan di tengah-tengah mereka, maka demikian pula yang terjadi pada pemimpin mereka. Dan jika menolak hak-hak Allah Ta'ala atas mereka dan enggan memenuhinya, maka para penguasa dan pemimpin mereka pun akan menolak hak-hak yang ada pada mereka dan kikir untuk menerapkannya pada mereka. Dan jika dalam muamalah mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya dari orang-orang lemah, maka para penguasa pun akan mengambil hal-hal yang bukan haknya serta menimpakan berbagai beban dan tugas kepada mereka.
Setiap yang mereka keluarkan (yang mereka ambil) dari orang-orang lemah, maka akan dikeluarkan (diambil) pula oleh para penguasa itu dari diri mereka dengan kekuatan (paksaan). Dengan demikian amal perbuatan mereka tercermin pada amal perbuatan penguasa dan pemimpin mereka. Dan menurut hikmah Ilâhiyyah, tidaklah diangkat seorang pemimpin atas orang-orang jahat lagi berbuat keji, kecuali orang-orang yang sejenis dengan mereka. Ketika pada kurun-kurun pertama merupakan kurun yang paling baik, maka demikian itu pula para pemimpin mereka. Dan ketika mereka mulai tercemari, maka pemimpin mereka pun mulai tercemari pula.
Dengan demikian, hikmah Allah Ta'ala menolak jika kita di zaman ini dipimpin oleh orang-orang seperti Mu’awiyah dan ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz, apalagi orang-orang seperti Abu Bakar dan ‘Umar, tetapi pemimpin kita itu sesuai dengan keadaan kita. Dan pemimpin orang-orang sebelum kita pun sesuai dengan kondisi mereka. Masing-masing dari kedua hal tersebut merupakan konsekuensi dan tuntutan hikmah Allah Ta'ala .”
Pada masa pemerintahan ‘Ali bin Abi Thâlib radhiallahu'anhu ada seseorang yang bertanya kepada beliau, “Kenapa pada zaman kamu ini banyak terjadi pertengkaran dan fitnah, sedangkan pada zaman Abu Bakar dan ‘Umar tidak?” ‘Ali radhiallahu'anhu menjawab, “Karena pada zaman Abu Bakar dan ‘Umar yang menjadi rakyatnya adalah aku dan Sahabat yang lainnya. Sedangkan pada zamanku yang menjadi rakyatnya adalah kalian.”
Oleh karena itu, untuk mengubah keadaan kaum Muslimin agar menjadi baik, Allah Ta'ala memerintahkan agar kita mengubah diri kita sendiri terlebih dulu, bukan mengubah penguasa yang ada. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (Qs ar-Ra’d/13:11)
Kita harus memperhatikan kewajiban mendengar dan taat kepada ulil amri. Bila tidak, maka akan terjadi kehinaan, kekacauan, pertumpahan darah, kaum Muslimin menjadi korban, dan lain sebagainya. Sedangkan darah kaum Muslimin itu lebih mulia dari pada Ka’bah yang mulia dan lebih berat di sisi Allah Ta'ala dari pada hancurnya dunia.
Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Hancurnya dunia ini lebih ringan dosanya di sisi Allah dari pada terbunuhnya seorang Muslim."
Terjadinya Perpecahan Dan Perselisihan Di Tengah Kaum Muslimin
Sabda Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"Sungguh, orang yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku, maka ia akan melihat perselisihan yang banyak."
Sesungguhnya perpecahan dan perselisihan dalam Islam itu tercela. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
“Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat adzab yang berat."
(Qs Ali ‘Imrân/3:105)
Allah Ta'ala berfirman yang artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terserah) atas Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.
(Qs al-An’âm/6:159)
Syaikh ‘Abdurrahmân bin Nâshir as-Sa’di rahimahullah mengatakan, “Ayat ini menjelaskan bahwa agama Islam memerintahkan untuk berjama’ah dan bersatu serta melarang perpecahan dan perselisihan dalam prinsip agama, bahkan dalam setiap permasalahan agama, baik yang pokok maupun cabangnya.”
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang Ahlul Kitab sebelum kalian telah berpecah-belah menjadi 72 golongan. Sesungguhnya umat Islam akan berpecah-belah menjadi 73 golongan, 72 golongan tempatnya di neraka dan hanya satu golongan di Surga, yaitu al-Jama’âh."
Dalam riwayat lain disebutkan:
"Semua golongan tersebut tempatnya di Neraka, kecuali satu (yaitu) yang aku dan para Sahabatku berjalan di atasnya."
Jalan Selamat Dari Perpecahan Dan Perselisihan
Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah dengan berpegang teguh kepada al-qur-an dan as-sunnah menurut pemahaman salafush shalih. Sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"Maka wajib atas kalian berpegang teguh kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafâur Râsyidin yang mendapat petunjuk."
Sabda beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam di atas terdapat perintah untuk berpegang teguh dengan Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam dan Sunnah Khulafâur Râsyidin sepeninggal beliau. Sunnah adalah jalan yang dilalui, termasuk di dalamnya berpegang teguh kepada keyakinan-keyakinan, perkataan-perkataan, dan perbuatan perbuatan Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam dan para Khulafâur Râsyidin. Itulah Sunnah yang paripurna. Oleh karena itu, generasi Salaf dahulu tidak menamakan Sunnah, kecuali kepada apa saja yang mencakup ketiga aspek tersebut. Hal ini diriwayatkan dari al-Hasan, al-Auzâ’i, dan Fudhail bin ‘Iyâdh.
Keempat Khalifah tersebut disebut Râsyidîn karena mereka mengetahui kebenaran dan memutuskan segala perkara dengan kebenaran. Râsyîd adalah lawan kata dari ghâwi. Ghâwi ialah orang yang mengetahui kebenaran, namun mengamalkan kebalikannya. Sedangkan kata Mahdiyyîn maksudnya adalah Allah Ta'ala membimbing mereka kepada kebenaran dan tidak menyesatkan mereka darinya. Jadi, manusia terbagi menjadi tiga: râsyid, ghâwi, dan dhâll.
Râsyid ialah orang yang mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Dhâll ialah orang yang tidak mengetahui kebenaran secara total. Jadi, seluruh orang râsyid itu ialah orang yang mendapatkan petunjuk, dan orang yang diberi petunjuk dengan petunjuk paripurna ialah orang yang râsyid (mendapatkan petunjuk), karena petunjuk hanya sempurna dengan mengetahui kebenaran dan mengamalkannya.
Perintah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam untuk mengikuti Sunnah beliau dan Sunnah Khulafâ Râsyidin setelah perintah mendengar dan taat kepada ulil amri adalah bukti bahwa Sunnah para Khulafâur Râsyidin harus diikuti seperti halnya mengikuti Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam . Ini tidak berlaku bagi Sunnah para pemimpin selain Khulafâ Râsyidin.
Ini menunjukkan bahwa kita wajib berpegang kepada al-Qur‘ân dan Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih. Selain itu, kita diwajibkan mengikuti manhaj para Salafush Shalih karena Allah Ta'ala menyebutkan dalam al-Qur‘ân tentang wajibnya kita mengikuti mereka.
Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
“Maka jika mereka beriman sebagaimana kamu telah beriman, sungguh, mereka telah mendapat petunjuk; dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada
dalam permusuhan (dengan kamu). Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. dan Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”
(Qs al-Baqarah/2:137)
Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan selain jalan orang-orang Mukmin, Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu dan akan Kami masukkan dia ke dalam neraka Jahannam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali.
(Qs an-Nisâ’/4:115)
Kita berpegang dengan pemahaman Salaf, mengikuti jejak Salafus Shalih, dengan tujuan ingin selamat dunia akhirat dan ingin masuk Surga, bukan untuk mencari kedudukan, harta, dan ketenaran. Kita mengikuti jejak mereka supaya selamat di dunia dan di akhirat dan agar Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam Surga-Nya, bukan untuk memperoleh kesenangan dunia, harta, jabatan, maupun kekuasaan.
Kita wajib mengikuti jejak Salafush Shalih karena mereka adalah khairun nâs (sebaik-baik manusia), dan khairu hâdzhihil ummah (dan sebaik-baik umat ini).
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Sebaik-baik manusia adalah pada masaku ini (yaitu masa para Sahabat), kemudian yang sesudahnya (masa Tâbi’in), kemudian yang sesudahnya (masa Tâbi’ut Tâbi’în)."
Mengenai berpegang kepada al-Qur‘ân dan Sunnah dengan pemahaman Salafush Shalih ini, Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam bukan hanya menyuruh berpegang saja. Tetapi menyuruh kita agar memegangnya dengan sangat kuat dan erat sehingga beliau mengungkapkannya melalui sabda beliau,
"Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian."
Sabda beliau merupakan kiasan tentang kuatnya berpegang teguh kepada Sunnah. Hal itu karena sudah begitu banyaknya fitnah dan syubhat yang ada. Kadang-kadang ada orang berpegang pada manhaj Salaf lalu keluar dari manhaj Salaf karena banyaknya fitnah, syubhat, dan syahwat. Fitnah terbagi menjadi dua: fitnah syahwat dan syubhat. Fitnah syubhat ialah fitnah yang terkait dengan pemahaman, aliran, kelompok, firqah, keyakinan, dan lainnya. Sedangkan fitnah syahwat ialah yang berkenaan dengan harta, wanita, jabatan, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya.
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, “Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam telah menggabungkan Sunnah Sahabatnya dengan Sunnahnya, dan memerintahkan untuk mengikutinya seperti memerintahkan untuk mengikuti Sunnahnya, sampai-sampai beliau memerintahkan agar menggigitnya dengan gigi geraham. Dan ini meliputi apa yang mereka fatwakan dan apa yang mereka contohkan walaupun sebelumnya Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam tidak melakukannya.
Hal ini juga meliputi apa yang mereka fatwakan secara keseluruhan atau sebagian besar dari mereka atau sebagian mereka saja karena Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam mengaitkannya dengan apa yang disunnahkan (dicontohkan) oleh Khulafâ Râsyidin. Dan sudah dimaklumi, jika mereka mencontohkan hal itu pada saat yang bersamaan, maka bisa diketahui bahwa Sunnah tiap orang dari mereka (Sahabat) pada masa beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam adalah termasuk Sunnah Khulafâur Râsyidin.”
Hadits ini sebagai pukulan keras yang menghujam di kepala para ahlul bid’ah yang menyelisihi manhaj Salaf, karena hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal:
Pertama:
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam menggabungkan Sunnah Khulafâur Râsyidin, yaitu pemahaman Salaf, dengan Sunnah beliau. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak bisa dipahami kecuali dengan manhaj Salaf.
Kedua:
Beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam menjadikan Sunnah Khulafâur Râsyidin sebagai Sunnah beliau, beliau mengatakan, “Gigitlah ia dengan gigi geraham.” Dan tidak mengatakan, “Gigitlah keduanya dengan gigi geraham.” Dengan demikian jelaslah bahwa Sunnah Khulafâ`ur Râsyidin termasuk Sunnah beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam.
Ketiga:
Beliau menghadapkan (menjadikan berlawanan) semua itu dengan peringatan terhadap bid’ah, maka hal ini menunjukkan setiap yang menyelisihi manhaj Salaf berarti ia terjerumus dalam bid’ah tanpa ia sadari.
Keempat:
Beliau menjadikan hal itu (manhaj Salaf) sebagai solusi dari perselisihan dan kebid’ahan, barangsiapa yang berpegang teguh kepada Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam dan Sunnah Khulafâ‘ur Râsyidin maka ia termasuk dalam golongan yang selamat kelak di hari Kiamat.
Kelima:
Beliau tidak menjadikan Sunnahnya dan Sunnah Khulafâ Râsyidin dalam perselisihan yang banyak itu. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya itu berasal dari Allah Ta'ala , karena terjadinya perselisihan yang banyak tidak mungkin dari Allah Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya,
“Sekiranya (al-Qur`ân) itu bukan dari Allah, pasti mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya.” (Qs an-Nisâ’/4:82)
Dari poin-poin yang berkaitan ini maka jelaslah bahwa jalan keselamatan dari perselisihan dan perpecahan serta jalan untuk melindungi kehidupan dari kesesatan hawa nafsu dan rusaknya syubhat dan syahwat adalah dengan memahami Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam dengan pemahaman mereka. Karena mereka telah mendapat bagian melimpah dari Sunnah tersebut, mereka berhasil menempati posisi terdepan dan memimpin masa, sehingga tidak menyisakan kesempatan bagi generasi setelahnya untuk menyusul dan menyamai mereka karena mereka berhenti di atas petunjuk, telah dicukupkan dengan ilmu, dan dengan ketajaman pandangan mereka melihat Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam menjadi sesuatu yang paling agung di hati mereka, paling hebat dalam jiwa mereka.
Jika Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam mengajak mereka pada suatu perintah, secepatnya mereka segera memenuhinya baik beramai-ramai maupun sendiri-sendiri. Mereka segera membawa jiwa raganya untuk melaksanakan perintah tersebut tanpa perlu bertanya tentang dalil atau buktinya.
Oleh karena itu, mereka adalah orang yang paling berhak terhadap Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam dan Sunnahnya, baik dalam pemahaman, pengamalan, maupun dakwah. Dan yang wajib bagi orang setelah mereka adalah berpegang teguh kepada manhaj mereka, agar bisa bersambung dengan Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam dan agama Allah Ta'ala . Jika tidak, maka ia bagaikan pohon buruk yang tercabut dari dalam tanah dan ia tidak memiliki ketetapan.26
Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam mengabarkan tentang akan terjadinya perpecahan dan perselisihan pada umatnya, kemudian Rasulullah Salallahu 'Alaihi Wassalam memberikan jalan keluar agar selamat dunia dan akhirat yaitu dengan mengikuti Sunnahnya dan Sunnah para Sahabat. Hal ini menunjukkan wajibnya mengikuti Sunnahnya (Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam) dan Sunnah para Sahabatnya radhiallahu'anhum.
Jauhilah Perbuatan Bid’ah!
Sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"Dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru (dalam agama), karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid‘ah."
Yang dimaksud di sini adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Sebab, perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam urusan dunia ada yang bermanfaat dan itu merupakan kebaikan dan ada pula yang berbahaya dan itu merupakan keburukan. Sedangkan perkara-perkara baru yang diada-adakan dalam agama adalah buruk. Allah Ta'ala berfirman yang artinya,
“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam itu jadi agama bagimu.”
(Qs al-Mâ`idah/5:3)
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Tidak tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan ke Surga dan menjauhkan dari Neraka, kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian."
Dalam hadits di atas disebutkan, “Setiap perkara yang baru adalah bid’ah” maka apakah yang dimaksud dengan bid’ah?
Definisi Bid’ah
Imam asy-Syâthibi rahimahullah (wafat th. 790 H) mengatakan,
"Bid’ah adalah cara baru dalam agama yang dibuat menyerupai syari’at dengan maksud untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala."
Artinya, bid’ah adalah cara baru yang dibuat tanpa ada contoh dari syari’at. Sebab, bid’ah adalah sesuatu yang keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam syari’at.
Ungkapan “menyerupai syari’at” sebagai penegasan bahwa sesuatu yang diada-adakan dalam agama itu pada hakekatnya tidak ada dalam syari’at, bahkan bertentangan dengan syari’at dari beberapa sisi, seperti mengharuskan cara dan bentuk tertentu yang tidak ada dalam syari’at. Juga mengharuskan ibadah-ibadah tertentu yang dalam syari’at tidak ada ketentuannya.
Ungkapan “untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala“, adalah pelengkap makna bid’ah. Sebab, demikian itulah tujuan para pelaku bid’ah, yaitu menganjurkan untuk tekun beribadah, karena manusia diciptakan Allah Ta'ala hanya untuk beribadah kepada-Nya sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya,
“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (Qs adz-Dzâriyât/51:56)
Seakan-akan orang yang membuat bid’ah melihat bahwa maksud dalam membuat bid’ah adalah untuk beribadah sebagaimana maksud ayat tersebut. Dia merasa bahwa apa yang telah ditetapkan dalam syari’at tentang undang-undang dan hukum-hukum belum mencukupi sehingga dia berlebih-lebihan dan menambahkan serta mengulang-ulanginya.
Imam al-Hâfizh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah (wafat th. 795 H) mengatakan, “Yang dimaksud dengan bid’ah adalah apa yang tidak memiliki dasar hukum dalam ajaran syari’at yang menunjukkan keabsahannya. Adapun yang memiliki dasar dalam syari’at yang menunjukkan kebenarannya, maka secara syari’at tidaklah dikatakan sebagai bid’ah, meskipun secara bahasa dikatakan bid’ah. Maka setiap orang yang membuat-buat sesuatu lalu menisbatkannya kepada ajaran agama, namun tidak memiliki landasan dari ajaran agama yang bisa dijadikan sandaran, berarti itu adalah kesesatan. Ajaran Islam tidak ada hubungannya dengan bid’ah semacam itu. Tak ada bedanya antara perkara yang berkaitan dengan keyakinan, amalan ataupun ucapan, lahir maupun bathin.
Terdapat beberapa riwayat dari sebagian Ulama Salaf yang menganggap baik sebagian perbuatan bid’ah, padahal yang dimaksud tidak lain adalah bid’ah secara bahasa, bukan menurut syari’at.
Contohnya adalah ucapan ‘Umar bin al-Khaththâb radhiallahu'anhu ketika beliau mengumpulkan kaum Muslimin untuk melaksanakan shalat malam di bulan Ramadhan (shalat Tarawih) dengan mengikuti satu imam di masjid. Ketika beliau radhiallahu'anhu keluar, dan melihat mereka shalat berjamaah. Maka, beliau radhiallahu'anhu berkata, “Sebaik-baik bid’ah adalah yang semacam ini.”
Tidak diragukan lagi bahwa setiap bid’ah dalam agama adalah sesat dan haram, berdasarkan sabda Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam yang artinya,
“Jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat.”
Juga sabda beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam yang artinya,
“Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak".
Kedua hadits di atas menunjukkan bahwa perkara baru yang dibuat-buat dalam agama ini adalah bid’ah, dan setiap bid’ah itu sesat dan tertolak. Bid’ah dalam agama itu diharamkan. Namun tingkat keharamannya berbeda-beda tergantung jenis bid’ah itu sendiri.
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam juga bersabda,
"Barangsiapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak didasari atas perintah kami maka amalannya tertolak".
Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam sendiri yang mengatakan amalan bid’ah itu tertolak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat dari dua syarat diterimanya ibadah, yaitu mutâba’ah (mengikuti contoh Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam).
Syarat diterimanya ibadah ada dua: pertama, niat ikhlas karena Allah Ta'ala dan kedua, sesuai dengan Sunnah; yakni sesuai dengan Kitab-Nya atau yang dijelaskan Rasul-Nya dan Sunnahnya.
Jika salah satunya tidak dipenuhi, maka amalnya tersebut tidak bernilai shalih dan tertolak, hal ini ditunjukkan dalam firman-Nya yang artinya :
"Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah dia mengerjakan amal shalih dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabb-nya".(Qs al-Kahfi/18:110)
Dalam ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan agar menjadikan amal itu bernilai shalih, yaitu sesuai dengan Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam, kemudian memerintahkan agar orang yang mengerjakan amal shalih itu mengikhlaskan niatnya karena Allah Ta'ala semata, tidak menghendaki selain-Nya.
Al-Hâfizh Ibnu Katsîr rahimahullah berkata dalam tafsirnya, “Inilah dua landasan amalan yang diterima: Pertama, ikhlas karena Allah Ta'ala dan Kedua, sesuai dengan Sunnah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam.”
Menjelaskan tentang bahaya bid’ah dan ahlul bid’ah kepada umat tidaklah termasuk memecah-belah persatuan kaum Muslimin, bahkan menjelaskan bahaya bid’ah dan membantah ahlul bid’ah termasuk dalam kategori jihad. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata,
“Orang yang membantah ahlul bid’ah adalah mujahid, sampai Yahya bin Yahya berkata, ‘Membela Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam lebih utama daripada jihad (fî sabîlillâh).’”
Setiap Bid’ah Adalah Sesat
Sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam,
"Dan setiap bid’ah adalah sesat"
Sabda beliau di atas termasuk dari jawâmi’ul kalim beliau di mana tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya, dan merupakan kaidah agung dalam prinsip-prinsip agama. Sabda beliau tersebut mirip dengan sabda beliau, Barangsiapa yang mengada-ada dalam urusan (agama) kami ini, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka ia tertolak.
Jadi, siapa saja yang mengada-adakan perkara-perkara baru dan menisbatkannya kepada agama padahal tidak memiliki landasan hukum di agama, maka itu merupakan kesesatan dan agama berlepas diri darinya, baik dalam masalah keyakinan, perbuatan, atau perkataan yang tampak maupun perkataan yang tersembunyi.
Imam Mâlik bin Anas radhiallahu'anhu mengatakan:
"Barangsiapa yang mengadakan suatu bid’ah dalam Islam yang ia pandang hal itu baik (bid’ah hasanah), maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam mengkhianati risalah agama ini. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman: “Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu...” (Qs al-Mâ`idah/5:3) Maka, sesuatu yang pada hari itu (pada masa beliau masih hidup) bukanlah ajaran agama, maka hari ini pun sesuatu itu bukanlah ajaran agama."
Maksud dari kullu bid'ah adalah semua bid’ah. Tidak ada kata kullu bid'ah yang bermakna sebagian bid’ah. Apakah Sebagian sesat dan sebagian tidak??!!.
Apabila kita bawakan hadits yang lain, yang diriwayatkan oleh Imam an-Nasâ‘i, dari Sahabat Jâbir radhiallahu'anhu:
"Setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka."
Maka akankah mereka mengatakan bahwa ada kesesatan yang tempatnya di Surga?? Semua kesesatan tempatnya adalah Neraka. Kullu dhalâlah fin naar, artinya setiap kesesatan tempatnya di Neraka. Kullu bid’atin dhalâlah, artinya setiap bidah adalah sesat. Sama-sama menggunakan kata kullu. Ada sebagian orang yang memahami kata kullu dalam “kullu bid'atin dhalâlah" itu sebagian bid’ah, tetapi ketika mereka mengartikan “kullu dhalâlatin finnâr” tidak diartikan sebagian kesesatan tempatnya di Neraka, tetapi semua kesesatan tempatnya di Neraka. Inilah cara berfikir mereka yang kontradiksi.
Sabda Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam juga difahami Sahabat demikian, yaitu semua perbuatan bid’ah dalam agama adalah sesat. ‘Abdullâh bin Mas’ûd radhiallahu'anhu berkata,
"Hendaklah kalian mengikuti dan janganlah kalian berbuat bid’ah. Sungguh kalian telah dicukupi (dengan Islam ini), dan setiap bid’ah adalah sesat.
‘Abdullâh bin ‘Umar radhiallahu'anhu berkata,
"Setiap bid’ah itu sesat, meskipun manusia memandang baik."
Imam Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Khalaf al-Barbahâri rahimahullah (beliau adalah Imam Ahlus Sunnah wal Jamâ’ah pada zamannya, wafat th. 329 H) berkata:
“Jauhilah setiap perkara bid’ah sekecil apa pun, karena bid’ah yang kecil lambat laun akan menjadi besar. Demikian pula kebid’ahan yang terjadi pada umat ini berasal dari perkara kecil dan remeh yang mirip kebenaran sehingga banyak orang terpedaya dan terkecoh, lalu mengikat hati mereka sehingga susah untuk keluar dari jeratannya dan akhirnya mendarah daging lalu diyakini sebagai agama. Tanpa disadari, pelan-pelan mereka menyelisihi jalan lurus dan keluar dari Islam.”
Imam Sufyân ats-Tsauri rahimahullah (wafat th. 161 H) berkata,
"Perbuatan bid’ah lebih dicintai oleh Iblis daripada kemaksiatan. Pelaku kemaksiatan masih mungkin ia untuk bertaubat dari kemaksiatannya sedangkan pelaku kebid’ahan sulit untuk bertaubat dari kebid’ahannya."
Di antara contoh bid’ah yang dianggap baik oleh manusia antara lain:
Bid’ah Khawârij, yaitu memberontak kepada penguasa kaum Muslimin yang zhalim dan mengkafirkan pelaku dosa besar.
Bid’ah Syi’ah, yaitu meyakini bahwa mushaf kaum Muslimin adalah kurang dan yang benar adalah mushaf yang ada pada mereka yang disebut dengan mushaf Fathimah, nikah mut’ah (kawin kontrak), mengkafirkan para Sahabat, dan lainnya.
Bid’ah Jahmiyah, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala, mengatakan bahwa al-Qur‘ân adalah makhluk, meyakini bahwa Allah Ta'ala ada di mana-mana, dan
lain-lain.
Bid’ah Murji’ah, yaitu mereka berpendapat bahwa amal tidak masuk dalam iman, iman tidak bertambah dan berkurang, dan lain-lain.
Bid’ah Mu’tazilah, yaitu mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar berada di satu kedudukan di antara dua kedudukan yakni tidak Muslim tidak juga kafir, dan lain-lain.
Bid’ah kaum Shufi dan para penyembah kubur, yaitu tawasul dengan kuburan dan orang shalih yang telah meninggal dunia, dzikir berjama’ah, dan lain-lain.
Merayakan maulid (hari kelahiran) Nabi Muhammad Salallahu 'Alaihi Wassalam.
Merayakan Isrâ’ Mi’râj.
Merayakan tahun baru Hijriyyah.
Tahlilan dan mengirimkan pahala bacaan al-Qur‘ân kepada orang yang sudah mati.
Shalat Nishfu Sya’ban.
Dan bid’ah-bid’ah lainnya yang sangat banyak.
Setiap Kesesatan Tempatnya Di Neraka
Dalam riwayat an-Nasâ‘i dari Jâbir bin ‘Abdillâh radhiallahu'anhu, Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam bersabda,
"Dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka."
Yang harus diperhatikan mengenai hadits ini bahwa kita tidak boleh memastikan orang yang berbuat bid’ah dan maksiat itu tempatnya di Neraka. Kita tidak punya hak sama sekali. Sebagaimana kita juga tidak boleh memastikan orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, tempatnya di Surga. Kecuali orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala dan Rasul-Nya Salallahu 'Alaihi Wassalam.
Sabda beliau di atas merupakan ancaman yang terdapat di dalam banyak hadits dan ayat al-Qur‘ân sebagaimana yang disebutkan oleh para Ulama. Artinya orang yang melakukan perbuatan bid’ah diancam masuk Neraka. Adapun memastikan dia masuk Neraka, maka tidak boleh dilakukan dan sangat berbahaya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah mengatakan, “Seseorang yang berilmu terkadang menyebutkan ancaman terhadap sesuatu yang dipandangnya sebagai perbuatan dosa, padahal dia mengetahui bahwa orang yang menakwilnya diampuni dan tidak terkena ancaman. Tetapi dia menyebutkan hal itu untuk menjelaskan bahwa perbuatan dosa mengakibatkan mendapatkan siksa. Dia hanya mengingatkan untuk menghalangi manusia dari perbuatan yang dipandangnya sebagai dosa.”
Beliau rahimahullah juga berkata, “Karena nash-nash ancaman bentuknya umum, maka kita tidak menyatakan dengannya kepada orang tertentu bahwa dia termasuk penghuni Neraka. Sebab memungkinkan tidak berlakunya hukum yang ditetapkan pada orang yang melakukannya karena adanya penghalang yang kuat seperti taubat, atau kebaikan-kebaikan yang menghapuskan keburukan, atau musibah-musibah yang menghapuskan dosa, atau syafa’at yang diterima, dan lain-lain.”
Maka sabda Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam, “Setiap kesesatan tempatnya di Neraka,” adalah sifat bagi amal yang dilakukan seseorang dan sifat bagi buah amal yang dilakukannya, jika tidak disusuli dengan taubat dan meninggalkannya.
Kemudian sabda beliau Salallahu 'Alaihi Wassalam, “...di Neraka.” Tidak mengharuskan kekal di dalam Neraka atau berada lama di dalamnya. Tetapi seseorang masuk Neraka sesuai maksiat yang dilakukannya, baik bentuknya bid’ah maupun selainnya.
Berdasarkan hal ini, berlaku hukum lain, yaitu menghalalkan sesuatu yang diharamkan agama. Barangsiapa menghalalkan suatu bid’ah atau selainnya dari perbuatan maksiat dengan menghalalkan dalam hatinya padahal dia mengetahui dan mengakui bahwa sesuatu yang dilakukan tidak memiliki dasar dalam Sunnah, bahkan dia mengetahui bahwa tindakannya itu merupakan bentuk “mengoreksi” syariat maka ketika itu ia berada di dalam Neraka karena dia kufur.
Imam ath-Thahawi rahimahullah dalam kitab ‘akidahnya (hlm. 316-disertai syarah Ibnu Abil ‘Izz) mengatakan, “Kita tidak mengkafirkan seorang pun dari Ahlul Kiblat (kaum Muslimin) karena perbuatan dosa selama ia tidak menghalalkannya.”
Dan tidak diragukan lagi bahwa bid’ah adalah dosa yang sangat jelas dan maksiat yang sangat nyata. Dan dalil-dalil yang mengecamnya dan memerintahkan untuk menjauhinya sangat banyak sekali.
Fawaa-Id (Pelajaran Dari Hadits Ini)
Disyari’atkan memberikan nasehat. Akan tetapi, hendaknya dilakukan pada tempatnya dan jangan terlalu sering agar tidak membosankan.
Nasehat atau wasiat perpisahan biasanya menyentuh hati.
Nasehat Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam semuanya bermanfaat dan menyentuh hati para Sahabat.
Boleh bagi seseorang untuk meminta nasehat dari orang alim (Ulama), dan dalam hal ini apabila ada sebabnya, yakni seseorang membutuhkan nasehat.
Wasiat yang paling baik adalah wasiat takwa kepada Allah Ta'ala .
Seseorang akan mencapai takwa kepada Allah Ta'ala apabila ia menuntut ilmu syar’i, mengamalkannya, dan mentauhidkan Allah Ta'ala dan menjauhkan syirik.
Takwa adalah melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan menjauhkan larangan-Nya. Perintah yang paling besar adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dan larangan yang terbesar adalah syirik.
Takwa mempunyai keutamaan yang sangat banyak.
Wajib mendengar dan taat kepada ulil amri (penguasa) dari kaum Muslimin dalam hal yang ma’ruf.
Tidak boleh taat kepada ulil amri dalam hal maksiat.
Perintah taat kepada ulil amri meskipun dia seorang hamba sahaya (budak), menunjukkan pentingnya taat kepada ulil amri.
Di antara mukjizat Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam , beliau mengabarkan akan terjadinya perpecahan dan perselisihan di tengah-tengah kaum Muslimin.
Jalan selamat dari perpecahan dan perselisihan adalah berpegang kepada al-Qur‘ân dan Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam serta memahaminya sebagaimana yang difahami oleh para Sahabat radhiallahu'anhum .
Keutamaan Khulâfaur Râsyidin.
Keutamaan para Sahabat radhiallahu'anhum, karena mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya.
Baiknya hati para Sahabat radhiallahu'anhum, karena mereka takut kepada Allah Ta'ala
Wajib atas setiap Muslim mempelajari Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam.
Kita wajib mengikuti Sunnah Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam dan Sunnah Khulafâ‘ur Râsyidin serta berpegang teguh dengan keduanya.
Kita wajib waspada dan hati-hati kepada setiap perkara yang baru yang tidak ada asalnya dari Nabi Salallahu 'Alaihi Wassalam.
Setiap perkara yang baru yang diada-adakan dalam agama adalah bid’ah.
Semua bid’ah adalah sesat, tidak ada bid’ah hasanah dalam Islam dan tidak ada juga pembagian bid’ah menjadi lima (hasanah, mubah, makruh, haram, dan wajib). Yang mengatakan semua bid’ah sesat adalah Rasulullâh Salallahu 'Alaihi Wassalam. Beliau adalah orang yang paling tahu tentang Islam, paling fasih berbahasa Arab, dan paling jujur.
Semua kesesatan tempatnya di Neraka.
Menjelaskan tentang bahaya bid’ah kepada umat tidak termasuk memecah belah kaum Muslimin, namun termasuk dalam kategori amar ma’ruf nahi munkar.
Tidak boleh memastikan para pelaku bid’ah dengan masuk Neraka karena kita tidak tahu akhir kehidupannya. Bisa jadi ia bertaubat dari perbuatan bid’ahnya tersebut.
Bid’ah merusak hati, akal, dan agama.
Wallâhu a’lam.
Oleh: Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas
(Majalah As-Sunnah Edisi 10/Thn. XIII/Muharram 1431H/Januari 2010M)
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 11:47 am 0 comments
Labels: ~ Aqidah Sohihah ~, ~ Bekalan Rohani ~, ~ Ilmu Dan Dakwah ~

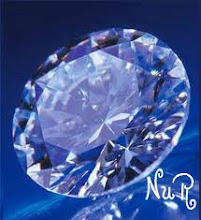



.JPG)








