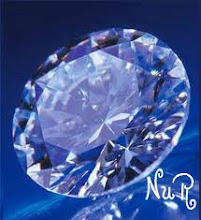Syubhat-syubhat para pendukung bid'ah hasanah
(Imam Syafii mendukung bid'ah hasanah??)
Syubhat pertama :
Mereka berdalil dengan perkataan beberapa ulama yang mengesankan dukungan terhadap adanya bid'ah hasanah.
Diantaranya adalah perkataan Imam As-Syafi'i dan perkatan Al-Izz bin Abdissalam rahimahumallah.
Adapun perkataan Imam As-Syafi'i maka sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Al-Hilyah dengan sanad beliau hingga Harmalah bin Yahya-,
ثَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى قَالَ : سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِدْرِيْسَ الشَّافِعِي يَقُوْلُ : البِدْعَةُ بِدْعَتَانِ بِدْعَةٌ مَحْمُوْدَةٌ وَبِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ، فَمَا وَافَقَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَحْمُوْدٌ وَمَا خَالَفَ السُّنَّةَ فَهُوَ مَذْمُومٌ، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هِيَ
Dari Harmalah bin Yahya berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, "Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid'ah yang menyelisihi sunnah adalah bid'ah yang tercela", dan Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottob tentang sholat tarawih di bulan Ramadhan "Sebaik-baik bid'ah adalah ini" (Hilyatul Auliya' 9/113)
Sebelum menjelaskan maksud dari perkataan Imam As-Syafii ini apalah baiknya jika kita menelaah definisi bid'ah menurut beberapa ulama, sebagaiamana berikut ini:
Definisi bid'ah menurut para ulama
Imam Al-'Iz bin 'Abdissalam berkata :
هِيَ فِعْلُ مَا لَمْ يُعْهَدْ فِي عَهْدِ الرَّسُوْلِ
((Bid'ah adalah mengerjakan perkara yang tidak ada di masa Rasulullah)) (Qowa'idul Ahkam 2/172)
Imam An-Nawawi berkata :
هِيَ إِحْدَاثُ مَا لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ
((Bid'ah adalah mengada-ngadakan sesuatu yang tidak ada di masa Rasulullah)) (Tahdzibul Asma' wal lugoot 3/22)
Imam Al-'Aini berkata :
هِيَ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَقِيْلَ: إِظْهَارُ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ وَلاَ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ
((Bid'ah adalah perkara yang tidak ada asalnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dan dikatakan juga (bid'ah adalah) menampakkan sesuatu yang tidak ada pada masa Rasulullah dan tidak ada juga di masa para sahabat)) (Umdatul Qori' 25/37)
Ibnu 'Asaakir berkata :
مَا ابْتُدِعَ وَأُحْدِثَ مِنَ الأُمُوْرِ حَسَناً كَانَ أَوْ قَبِيْحًا
((Bid'ah adalah perkara-perkara yang baru dan diada-adakan baik yang baik maupun yang tercela)) (Tabyiinu kadzibil muftari hal 97)
Al-Fairuz Abadi berkata :
الحَدَثُ فِي الدَّيْنِ بَعْدَ الإِكْمَالِ، وَقِيْلَ : مَا استَحْدَثَ بَعْدَهُ مِنَ الأَهْوَاءِ وَالأَعْمَالِ
((Bid'ah adalah perkara yang baru dalam agama setelah sempurnanya, dan dikatakan juga : apa yang diada-adakan sepeninggal Nabi berupa hawa nafsu dan amalan)) (Basoir dzawi At-Tamyiiz 2/231)
Dari defenisi-defenisi di atas maka secara umum dapat kita simpulkan bahwa bid'ah adalah segala perkara yang terjadi setelah Nabi, sama saja apakah perkara tersebut terpuji ataupun tercela dan sama saja apakah perkara tersebut suatu ibadah maupun perkara adat.
Karena keumuman ini maka kita dapati sekelompok ulama yang membagi hukum bid'ah menjadi dua yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah, bahkan ada yang membagi bid'ah sesuai dengan hukum taklifi yang lima (haram, makruh, wajib, sunnah, dan mubah), sebagaimana pembagian bid'ah menurut Al-'Iz bin Abdissalam yang mengklasifikasikan bid'ah menjadi lima (wajib, mustahab, haram, makruh, dan mubah), beliau berkata,
"Bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang wajib, bid'ah yang haram, bid'ah yang mandub (mustahab), bid'ah yang makruh, dan bid'ah yang mubah. Cara untuk mengetahui hal ini yaitu kita hadapkan bid'ah tersebut dengan kaidah-kaidah syari'at, jika bid'ah tersebut masuk dalam kaidah-kaidah pewajiban maka bid'ah tersebut wajib, jika termasuk dalam kaidah-kaidah pengharaman maka bid'ah tersebut haram, jika termasuk dalam kaidah-kaidah mustahab maka hukumnya mustahab, dan jika masuk dalam kaidah-kaidah mubah maka bid'ah tersebut mubah. Ada beberapa contoh bid'ah yang wajib, yang pertama berkecimpung dengan ilmu nahwu yang dengan ilmu tersebut dipahami perkataan Allah dan perkataan Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam, hal ini hukumnya wajib karena menjaga syari'at hukumnya wajib dan tidak mungkin menjaga syari'at kecuali dengan mengenal ilmu nahwu, dan jika suatu perkara yang wajib tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain maka perkara yang lain tersebut hukumnya wajib.
Contoh yang kedua adalah menjaga kata-kata yang ghorib (asing maknanya karena sedikit penggunaannya dalam kalimat) dalam Al-Qur'an dan hadits, contoh yang ketiga yaitu penulisan ushul fiqh, contoh yang keempat pembicaraan tentang al-jarh wa at-ta'dil untuk membedakan antara hadits yang shahih dengan hadits yang lemah. Kaidah-kaidah syari'at menunjukan bahwa menjaga syari'at hukumnya fardlu kifayah pada perkara-perakra yang lebih dari ukuran yang ditentukan dan tidaklah mungkin penjagaan syari'at kecuali dengan apa yang telah kami sebutkan (di atas)."
Ada beberapa contoh bid'ah yang haram, diantaranya madzhab Qodariyah, madzhab Al-Jabariah, madzhab Al-Murji'ah, dan membantah mereka termasuk bid'ah yang wajib.
Ada beberapa contoh bid'ah yang mustahab diantaranya pembuatan Ar-Robt dan sekolah-sekolah, pembangunan jembatan-jembatan, dan setiap hal-hal yang baik yang tidak terdapat pada masa generasi awal, diantaranya juga sholat tarawih, pembicaraan pelik-pelik tasowwuf (sejenis mau'idzoh yang sudah ma'ruf), perdebatan di tengah keramaian orang banyak dalam rangka untuk beristidlal tentang beberapa permasalahan jika dimaksudkan dengan hal itu wajah Allah. Contoh-contoh bid'ah yang makruh diantaranya menghiasi masjid-masjid, menghiasi mushaf (Al-Qur'an), adapun melagukan Al-Qur'an hingga berubah lafal-lafalnya dari bahasa Arab maka yang benar ia termasuk bid'ah yang haram.
Contoh-contoh bid'ah yang mubah diantaranya berjabat tangan setelah sholat subuh dan sholat ashar, berluas-luas dalam makanan dan minuman yang lezat, demikian juga pakaian dan tempat tinggal, memakai at-thoyaalisah (sejenis pakaian yang indah/mahal) dan meluaskan pergelangan baju. Terkadang beberapa perkara diperselisihkan (oleh para ulama) sehingga sebagian ulama memasukannya dalam bid'ah yang makruh dan sebagian ulama yang lain memasukannya termasuk sunnah sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah shalallahu 'alaihi wa sallam dan sepeninggal beliau shalallahu 'alaihi wa sallam, hal ini seperti beristi'adzah dalam sholat dan mengucapkan basmalah." (Qowa'idul ahkam 2/173-174)
Ada 3 hal penting berkaitan dengan pengklasifikasian ini:
Pertama : Jika kita perhatikan perkataan Al-'Iz bin Abdissalam secara lengkap dengan memperhatikan contoh-contoh penerapan dari pengklasifikasiannya terhadap bid'ah maka sangatlah jelas maksud beliau adalah pengklasifikasian bid'ah menurut bahasa, karena contoh-contoh yang beliau sebutkan dalam bid'ah yang wajib maka contoh-contoh tersebut adalah perkara-perkara yang termasuk dalam al-maslahah al-mursalah (yaitu perkara-perkara yang beliau contohkan yang berkaitan dengan bid'ah wajib) bahkan beliau dengan jelas menyatakan bahwa syari'at tidak mungkin dijalankan kecuali dengan bid'ah yang wajib tersebut.
As-Syathibi berkata "Sesungguhnya Ibnu Abdissalam yang nampak darinya ia menamakan maslahah mursalah dengan bid'ah karena perkara-perkara maslahah mursalah secara dzatnya tidak terdapat dalam nas-nas yang khusus tentang dzat-dzat mashlahah mursalah tersebut meskipun sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at…dan ia termasuk para ulama yang berpendapat dengan mashlahah mursalah, hanya saja ia menamakannya bid'ah sebagaimana Umar menamakan sholat tarawih bid'ah" (Al-I'tishom 1/192)
Demikian juga bid'ah yang mustahab, berkaitan dengan wasilah dalam menegakkan agama. Sholat tarawih adalah termasuk perbuatan Nabi shalallahu 'alaihi wa sallam. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melaksanakan sholat tarawih secara berjama'ah bersama para sahabatnya beberapa malam. Dan pada tahun yang lain Nabi meninggalkan tarawih karena dikawatirkan akan diwajibkan karena tatkala itu masih zaman diturunkannya wahyu (ta'syri'). Hal ini menunjukan pada asalnya Nabi sholat malam bersama para sahabatnya dan di waktu yang lain beliau meninggalkannya karena kekawatiran akan diwajibkan. Namun kekawatiran ini tidak terdapat lagi di zaman Abu Bakar dan Umar. Hanya saja Abu akar tidak melaksanakan sholat tarawih karena ada dua kemungkinan, yang pertama karena mungkin saja ia memandang bahwa sholat orang-orang di akhir malam dengan keadaan mereka masing-masing lebih baik dari pada sholat di awal malam dengan mengumpulkan mereka pada satu imam (hal ini sebagaimana disebutkan oleh At-Thurtusi), atau karena kesibukan beliau mengurus negara terutama dengan munculnya orang-orang yang murtad sehingga beliau harus memerangi mereka yang hal ini menyebabkan beliau tidak sempat mengurusi sholat tarawih. (lihat Al-I'tishom 2/194)
Demikian contoh-contoh lain dari bid'ah mustahab (hasanah) yang disampaikan oleh beliau diantaranya : pembangunan sekolah-sekolah merupakan sarana untuk menuntut ilmu, dan pembicaraan tentang pelik-pelik tasawwuf yang terpuji adalah termasuk bab mau'izhoh (nasehat) yang telah dikenal.
Kedua : Dalam contoh-contoh bid'ah yang disyari'atkan (baik bid'ah yang wajib maupun bid'ah yang mustahab) sama sekali beliau tidak menyebutkan bid'ah-bid'ah yang dikerjakan oleh para pelaku bid'ah (Seperti sholat rogoib, maulid Nabi, peringatan isroo mi'rooj, tahlilan, dan lain-lain) dengan dalih bahwa bid'ah tersebut adalah bid'ah hasanah, bahkan beliau dikenal dengan seorang yang memerangi bid'ah.
Ketiga : Beliau dikenal dengan orang yang keras membantah bid'ah-bid'ah yang disebut-sebut sebagai bid'ah hasanah.
Berkata Abu Syamah (salah seorang murid Al-'Iz bin Abdissalam),
"Beliau (Al-'Iz bin Abdissalam) adalah orang yang paling berhak untuk berkhutbah dan menjadi imam, beliau menghilangkan banyak bid'ah yang dilakukan oleh para khatib seperti menancapkan pedang di atas mimbar dan yang lainnya. Beliau juga membantah sholat rogoib dan sholat nishfu sya'ban dan melarang kedua sholat tersebut" (Tobaqoot Asy-Syafi'iah al-Kubro karya As-Subki 8/210, pada biografi Al-'Iz bin Abdissalam)
Beliau ditanya : Berjabat tangan setelah sholat subuh dan ashar hukumnya mustahab atau tidak? Doa setelah salam dari seluruh sholat mustahab bagi imam atau tidak? Jika engkau berkata hukumnya mustahab maka (tatkala berdoa) sang imam balik mengahadap para makmum dan membelakangi kiblat atau tetap menghadap kiblat?...
Jawab : Berjabat tangan setelah sholat subuh dan ashar termasuk bid'ah kecuali bagi orang yang baru datang dan bertemu dengan orang yang dia berjabat tangan dengannya sebelum sholat, karena berjabat tangan disyari'atkan tatkala datang.
Setelah sholat Nabi berdzikir dengan dzikir-dzikir yang disyari'atkan dan beristighfar tiga kali kemudian beliau berpaling (pergi)… dan kebaikan seluruhnya pada mengikuti Nabi. Imam As-Syafi'i suka agar imam berpaling setelah salam. Dan tidak disunnahkan mengangkat tangan tatkala qunut sebagaimana tidak disyari'atkan mengangkat tangan tatkala berdoa di saat membaca surat al-Fatihah dan juga tatkala doa diantara dua sujud…
Dan tidaklah mengusap wajah setelah doa kecuai orang jahil. Dan tidaklah sah bersholawat kepada Nabi tatkala qunut, dan tidak semestinya ditambah sedikitpun atau dikurangi atas apa yang dikerjakan Rasulullah tatkala qunut" (Kittab Al-Fataawaa karya Imam Al-'Izz bin Abdis Salaam hal 46-47, kitabnya bisa didownload di http://majles.alukah.net/showthread.php?t=39664)
Beliau juga menyatakan bahwa mengirim bacaan qur'an kepada mayat tidaklah sampai (lihat kitab fataawaa beliau hal 96). Beliau juga menyatakan bahwasanya mentalqin mayat setelah dikubur merupakan bid'ah (lihat kitab fataawaa beliau hal 96)
Pengklasifikasian bid'ah menjadi bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah juga diikuti oleh Imam An-Nawawi, beliau berkata, "Dan bid'ah terbagi menjadi bid'ah yang jelek dan bid'ah hasanah", kemudian beliau menukil perkataan Al-'Iz bin Abdissalam dan perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas (lihat Tahdzibul Asma' wal lugoot 3/22-23).
Kembali pada perkataan Imam Asy-Syafi'i :
Dari Harmalah bin Yahya berkata, "Saya mendengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berkata, "Bid'ah itu ada dua, bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercela, maka bid'ah yang sesuai dengan sunnah adalah terpuji dan bid'ah yang menyelisihi sunnah adalah bid'ah yang tercela", dan Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottob tentang sholat tarawih di bulan Ramadhan "Sebaik-baik bid'ah adalah ini" (Hilyatul Auliya' 9/113)
Ada beberapa hal penting yang berkaitan dengan perkataan Imam As-Syafi'i ini :
Pertama : Sangatlah jelas bahwasanya maksud Imam As-Syafii adalah pengklasifikasian bid'ah ditinjau dari sisi bahasa. Oleh karenanya beliau berdalil dengan perkataan Umar bin Al-Khottoob :"Sebaik-baik bid'ah adalah ini (yaitu sholat tarawih berjamaah)". Padahal telah diketahui bersama –sebagaimana telah lalu penjelasannya- bahwasanya sholat tarwih berjamaah pernah dikerjakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
Kedua : Kita menafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i ini dengan perkataannya yang lain sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam Tahdziib Al-Asmaa' wa Al-Lughoot (3/23)
"Dan perkara-perkara yang baru ada dua bentuk, yang pertama adalah yang menyelisihi Al-Kitab atau As-Sunnah atau atsar atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat. Dan yang kedua adalah yang merupakan kebaikan, tidak seorang ulamapun yang menyelisihi hal ini (bahwasanya ia termasuk kebaikan-pen) maka ini adalah perkara baru yang tidak tercela"(lihat juga manaqib As-Syafi'i 1/469)
Lihatlah Imam As-Syafi'i menyebutkan bahwa bid'ah yang hasanah sama sekali tidak seorang ulama pun yang menyelisihi. Jadi seakan-akan Imam Asy-Syafi'i menghendaki dengan bid'ah hasanah adalah perkara-perkara yang termasuk dalam bab al-maslahah al-mursalah, yaitu perkara-perkara adat yang mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan tidak terdapat dalil (nas) khusus, karena hal ini tidaklah tercela sesuai dengan kesepakatan para sahabat meskipun hal ini dinamakan dengan muhdatsah (perkara yang baru) atau dinamakan bid'ah jika ditinjau dari sisi bahasa.
Berkata Ibnu Rojab, "Adapun maksud dari Imam Asy-Syafi'i adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan bahwasanya pokok dari bid'ah yang tercela adalah perkara yang sama sekali tidak ada dasarnya dalam syari'ah yang bisa dijadikan landasan, dan inilah bid'ah yang dimaksudkan dalam definisi syar'i (terminology). Adapun bid'ah yang terpuji adalah perkara-perkara yang sesuai dengan sunnah yaitu yang ada dasarnya dari sunnah yang bisa dijadikan landasan dan ini adalah definisi bid'ah menurut bahasa bukan secara terminology karena ia sesuai dengan sunnah" (Jami'ul 'Ulum wal Hikam 267)
Ketiga : Oleh karena itu tidak kita dapati Imam Asy-Syafii berpendapat dengan suatu bid'ahpun dari bid'ah-bid'ah yang tersebar sekarang ini dengan dalih hal itu adalah bid'ah hasanah. Karena memang maksud beliau dengan bid'ah hasanah bukanlah sebagaimana yang dipahami oleh para pelaku bid'ah zaman sekarang ini.
Diantara amalan-amalan yang dianggap bid'ah hasanah yang tersebar di masyarakat namun diingkari Imam As-Syafii adalah :
- Acara mengirim pahala buat mayat yang disajikan dalam bentuk acara tahlilan.
Bahkan masyhuur dari madzhab Imam Asy-Syafii bahwasanya beliau memandang tidak sampainya pengiriman pahala baca qur'an bagi mayat. Imam An-Nawawi berkata:
"Dan adapun sholat dan puasa maka madzhab As-Syafi'i dan mayoritas ulama adalah tidak sampainya pahalanya kepada si mayat…adapun qiroah (membaca) Al-Qur'aan maka yang masyhuur dari madzhab As-Syafi'I adalah tidak sampai pahalanya kepada si mayat…" (Al-Minhaaj syarh shahih Muslim 1/90)
- Meninggikan kuburan dan dijadikan sebagai mesjid atau tempat ibadah
Imam As-Syafi'I berkata :
وأكره أن يعظم مخلوق حتى يُجعل قبره مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس
"Dan aku benci diagungkannya seorang makhluq hingga kuburannya dijadikan mesjid, kawatir fitnah atasnya dan atas orang-orang setelahnya" (Al-Muhadzdzab 1/140, Al-Majmuu' syarhul Muhadzdzab 5/280)
Bahkan Imam As-Syafii dikenal tidak suka jika kuburan dibangun lebih tinggi dari satu jengkal. Beliau berkata :
وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُزَادَ في الْقَبْرِ تُرَابٌ من غَيْرِهِ وَلَيْسَ بِأَنْ يَكُونَ فيه تُرَابٌ من غَيْرِهِ بَأْسٌ إذَا زِيدَ فيه تُرَابٌ من غَيْرِهِ ارْتَفَعَ جِدًّا وَإِنَّمَا أُحِبُّ أَنْ يُشَخِّصَ على وَجْهِ الْأَرْضِ شِبْرًا أو نَحْوَهُ وَأُحِبُّ أَنْ لَا يُبْنَى وَلَا يُجَصَّصَ فإن ذلك يُشْبِهُ الزِّينَةَ وَالْخُيَلَاءَ... وقد رَأَيْت من الْوُلَاةِ من يَهْدِمَ بِمَكَّةَ ما يُبْنَى فيها فلم أَرَ الْفُقَهَاءَ يَعِيبُونَ ذلك
"Aku suka jika kuburan tidak ditambah dengan pasir dari selain (galian) kuburan itu sendiri. Dan tidak mengapa jika ditambah pasir dari selain (galian) kuburan jika ditambah tanah dari yang lain akan sangat tinggi. Akan tetapi aku suka jika kuburan dinaikan diatas tanah seukuran sejengkal atau yang semisalnya. Dan aku suka jika kuburan tidak dibangun dan tidak dikapur karena hal itu menyerupai perhiasan dan kesombongan…
Aku telah melihat di Mekah ada diantara penguasa yang menghancurkan apa yang dibangun diatas kuburan, dan aku tidak melihat para fuqohaa mencela penghancuran tersebut"(Al-Umm 1/277)
- Pengkhususan Ibadah pada waktu-waktu tertentu atau cara-cara tertentu
Berkata Abu Syaamah :
"Imam As-Syafi'i berkata : Aku benci seseroang berpuasa sebulan penuh sebagaimana berpuasa penuh di bulan Ramadhan, demikian juga (Aku benci) ia (mengkhususkan-pent) puasa suatu hari dari hari-hari yang lainnya. Hanyalah aku membencinya agar jangan sampai seseorang yang jahil mengikutinya dan menyangka bahwasanya perbuatan tersebut wajib atau merupakan amalan yang baik" (Al-Baa'its 'alaa inkaar Al-Bida' wa Al-Hawaadits hal 48)
Perhatikanlah, Imam As-Syafii membenci amalan tersebut karena ada nilai pengkhususan suatu hari tertentu untuk dikhususkan puasa. Hal ini senada dengan sabda Nabi
« لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِى صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ »
"Janganlah kalian mengkhususkan malam jum'at dari malam-malam yang lain dengan sholat malam, dan janganlah kalian mengkhususkan hari jum'at dari hari-hari yang lain dengan puasa, kecuali pada puasa yang dilakukan oleh salah seorang dari kalian" (yaitu maksudnya kecuali jika bertepatan dengan puasa nadzar, atau ia berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, atau puasa qodho –lihat penjelasan Imam An-Nawawi dalam Al-Minhaaj 8/19)
Perhatikanlah, para pembaca yang budiman, puasa adalah ibadah yang disyari'atkan, hanya saja tatkala dikhususkan pada hari-hari tertentu tanpa dalil maka hal ini dibenci oleh Imam As-Syafi'i.
Maka bagaimana jika Imam As-Syafii melihat ibadah-ibadah yang asalnya tidak disyari'atkan??!
Apalagi ibadah-ibadah yang tidak disyari'atkan tersebut dikhususkan pada waktu-waktu tertentu??
Beliau juga berkata dalam kitabnya Al-Umm
"Dan aku suka jika imam menyelesaikan khutbahnya dengan memuji Allah, bersholawat kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, menyampaikan mau'izhoh, dan membaca qiroa'ah, dan tidak menambah lebih dari itu".
Imam As-Syafii berkata : "Telah mengabarkan kepada kami Abdul Majiid dari Ibnu Juraij berkata : Aku berkata kepada 'Athoo : Apa sih doa yang diucapkan orang-orang tatkala khutbah hari itu?, apakah telah sampai kepadamu hal ini dari Nabi?, atau dari orang yang setelah Nabi (para sahabat-pent)?. 'Athoo berkata : Tidak, itu hanyalah muhdats (perkara baru), dahulu khutbah itu hanyalah untuk memberi peringatan.
Imam As-Syafii berkata, "Jika sang imam berdoa untuk seseorang tertentu atau kepada seseorang (siapa saja) maka aku membenci hal itu, namun tidak wajib baginya untuk mengulang khutbahnya" (Al-Umm 2/416-417)
Para pembaca yang budiman, cobalah perhatikan ucapan Imam As-Syafi'i diatas, bagaimanakah hukum Imam As-Syafii terhadap orang yang menkhususkan doa kepada orang tertentu tatkala khutbah jum'at?, beliau membencinya, bahkan beliau menyebutkan riwayat dari salaf (yaitu 'Athoo') yang mensifati doa tertentu dalam khutbah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya dengan "Muhdats" (bid'ah). Bahkan yang dzohir dari perkataan Imam As-Syafii diatas dengan "aku benci" yaitu hukumnya haram, buktinya Imam Syafii menegaskan setelah itu bahwasanya perbuatan muhdats tersebut tidak sampai membatalkan khutbahnya sehingga tidak perlu diulang. Wallahu A'lam.
Keempat : Para imam madzhab syafiiyah telah menukil perkataan yang masyhuur dari Imam As-Syafii, yaitu perkataan beliau;
مَنِ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَّعَ
"Barangsiapa yang menganggap baik (suatu perkara) maka dia telah membuat syari'at"
(Perkataan Imam As-Syafi'i ini dinukil oleh para Imam madzhab As-Syafi'i, diantaranya Al-Gozaali dalam kitabnya Al-Mustashfa, demikian juga As-Subki dalam Al-Asybaah wa An-Nadzooir, Al-Aaamidi dalam Al-Ihkaam, dan juga dinukil oleh Ibnu Hazm dalam Al-Ihkaam fi Ushuul Al-Qur'aan, dan Ibnu Qudaamah dalam Roudhotun Naadzir)
Oleh karenanya barangsiapa yang menganggap baik suatu ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi maka pada hakekatnya ia telah menjadikan ibadah tersebut syari'at yang baru.
Kesimpulan :
Pertama : Ternyata banyak ulama yang menyebutkan mashlahah mursalah dengan istilah bid'ah hasanah. Karena memang dari sisi bahasa bahwasanya perkara-perkara yang merupakan mashlahah mursalah sama dengan perkara-perkara bid'ah dari sisi keduanya sama-sama tidak terdapat di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.
Oleh karenanya semua sepakat bahwa ilmu jarah wa ta'dil hukumnya adalah wajib, demikian juga mempelajari ilmu nahwu, namun sebagian mereka menamakannya bid'ah hasanah atau bid'ah yang wajib (sebagaimana Al-Izz bin Abdissalam) dan sebagian yang lain menamakannya maslahah mursalah (sebagaimana Imam As-Syathibi dalam kitabnya Al-I'tishoom). Demikian juga semuanya sepakat bahwa membangun madrasah-madrasah agama hukumnya adalah mandub (dianjurkan) namun sebagian mereka menamakannya bid'ah hasanah (bid'ah mandubah) dan sebagian yang lain menamakannya maslahah mursalah.
Meskipun terjadi khilaf diantara mereka tentang hukum permasalahan tertentu maka hal itu adalah khilaf dalam penerapan saja yang khusus berkaitan dengan permasalahan itu saja yang khilaf itu kembali dalam memahami dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, khilaf mereka bukan pada asal (pokok kaidah) tentang pencelaan terhadap bid'ah dan pengingkarannya.
Namun bagaimanapun lebih baik kita meninggalkan istilah klasifikasi bid'ah menjadi bid'ah dholalah dan bid'ah hasanah karena dua sebab berikut
a. Beradab dengan sabda Nabi, karena bagaimana pantas bagi kita jika kita telah mendengarkan sabda Nabi ((semua bid'ah itu sesat)) lantas kita mengatakan ((tidak semua bid'ah itu sesat, tapi hanya sebagian bid'ah saja))
b. Pengklasifikasian seperti ini terkadang dijadikan tameng oleh sebagian orang untuk melegalisasikan sebagian bid'ah (padahal para imam yang berpendapat dengan pengkasifikasian bid'ah mereka berlepas diri dari hal ini), yang hal ini mengakibatkan terancunya antara sunnah dan bid'ah
Kedua : Para ulama yang dituduh mendukung bid'ah hasanah (seperti Imam As-Syafii dan Imam Al-Izz bin Abdis Salaam As-Syafi'i) ternyata justru membantah bid'ah-bid'ah yang tersebar di masyarakat yang dinamakan dengan bid'ah hasanah
Ketiga : Imam As-Syafii dan Imam Al-Izz bin Abdis Salaam yang juga bermadzhab syafiiyah yang dituduh mendukung bid'ah hasanah ternyata tidak mendukung bid'ah-bid'ah hasanah yang sering dilakukan oleh orang-orang yang mengaku bermadzhab syafi'i. Oleh karenanya saya meminta kepada orang-orang yang melakukan bid'ah -dan berdalil dengan perkataan Imam As-Syafii atau perkataan Al-Izz bin Abdisalaam- agar mereka memberikan satu contoh atau dua contoh saja bid'ah hasanah yang dipraktekan oleh kedua imam ini !!???
Sebagai tambahan penjelasan, berikut ini penulis menyampaikan perbedaan antara bid'ah hasanah dengan maslahah mursalah :
Maslahah mursalah harus memenuhi beberapa kriteria yaitu
1 Maslahah mursalah sesuai dengan maqosid syari'ah yaitu tidak bertentangan dengan salah satu usul dari usul-usul syari'ah maupun dalil dari dalil-dalil syar'i, berbeda dengan bid'ah
2 Maslahah mursalah hanyalah berkaitan dengan perkara-perkara yang bisa dipikirkan kemaslahatannya dengan akal (karena sesuatu yang bisa diketahui memiliki maslahah yang rajihah atau tidak adalah seauatu yang bisa dipikirkan dan dipandang dengan akal), artinya jika maslahah mursalah dipaparkan kepada akal-akal manusia maka akan diterima
Oleh karena itu maslahah mursalah tidaklah berkaitan dengan perkara-perkara peribadatan karena perkara-perkara peribadatan merupakan perkara yang tidak dicerna oleh akal dengan secara pasti (jelas) dan secara terperinci (hanyalah mungkin diketahui hikmah-hikmahnya), seperti wudhu, tayammum, sholat, haji, puasa, dan ibadaah-ibadah yang lainnya.
Contohnya thoharoh (tata cara bersuci) dengan berbagai macamnya yang dimana setiap macamnya berkaitan khusus dengan peribadatan yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran. contohnya keluarnya air kencing dan kotoran yang merupakan najis maka penyuciannya tidak hanya cukup dengan membersihkan tempat keluar kedua benda tersebut namun harus juga dengan berwudhu (meskipun anggota tubuh untuk berwudhu dalam keadaan bersih dan suci), kenapa demikian ??, sebaliknya jika anggota tubuh untuk berwudhu kotor namun tanpa disertai hadats maka tidak wajib untuk berwudhu, kenapa demikian?? kita tidak bisa mencernanya secara terperinci. Demikian juga halnya dengan tayammum, tanah yang sifatnya mengotori bisa menggantikan posisi air (yang sifatnya membersihkan) tatkala tidak ada air, kenapa demikan??, tidak bisa kita cerna dengan jelas, pasti dan terperinci. Demikan juga ibadah-ibadah yang lainnya seperti sholat dan haji terlalu banyak perkara-perkara yang tidak bisa kita cernai. Contohnya tentang tata cara sholat, jumlah rakaat, waktu-waktu sholat, hal-hal yang dilarang tatkala berihrom, dan lain sebagainya. Sungguh benar perkataan Ali لَوْ كَانَ الدِّيْنُ بِالرَّأْيِ لكان أَسفَلُ الخُفِّ أولى بالمسحِ من أعلاه ((Kalau memang agama dengan akal tentu yang lebih layak untuk di usap adalah bagian bawah khuf dari pada mengusap bagian atasnya)).
3 Maslahah mursalah kembali pada salah satu dari dua perkara dibawah ini
a. Bab wasilah (perantara) bukan tujuan, dan termasuk dalam kaidah مَا لاَ يَتِمُّ الوَلجبُ إلاَّ بِهِ فَهُوَ وَاجب ((sesuatu yang wajib jika tidak bisa sempurna pelaksanaannya kecuali dengan perkara yang lain maka perkara tersebut juga hukumnya wajib)), hal ini jika maslahah mursalah dalam rangka penyempurnaan pelaksaan salah satu dari dhoruriaat dalam agama. Contohnya seperti pengumpulan Al-Qur'aan, pemberian harokat pada Al-Qur'aan, mempelajari ilmu nahwu, mempelajari ilmu jarh wa ta'diil, yang semua ini merupakan perkara-perkara yang tidak ada di zman Nabi hanya saja merupakan maslahah mursalah
b. Bab takhfif (peringanan), hal ini jika maslahah mursalah dalam rangka menolak kesulitan yang selalu melazimi.
Jika demikian maka kita mengetahui bahwa bid'ah berbeda bahkan bertentangan dengan maslahah mursalah, karena obyek dari maslahah mursalah adalah perkara yang bisa dicerna dan ditangkap dengan akal secara terperinci seperti perkara-perkara adat, berbeda dengan perkara-perkara ibadat, oleh karena peribadatan sama sekali bukanlah obyek dari maslahah mursalah. Adapun bid'ah adalah sebalikinya yang menjadi obyeknya adalah peribadatan. Oleh karena itu tidak butuh untuk mengadakan peribadatan-peribadatan yang baru karena tidak bisa dicerna secara terperinci berbeda dengan perkara-perkara adat yang berkaitan tata cara kehidupan maka tidak mengapa diadakannya perkara-perkara yang baru. Para ulama telah menjelaskan bahwa asal hukum dalam peribadatan adalah haram hingga ada dalil yang menunjukan akan keabsahannya, berbeda dengan perkara-perkara adat asal hukumnya adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Demikian juga perkara-perkara bid'ah biasanya maksudnya adalah untuk berlebih-lebihan dalam beribadah karena pelakunya tidak puas dengan syariat yang dibawa oleh Nabi, maka ia bukanlah termasuk maslahah mursalah karena di antara tujuan dari maslahah mursalah adalah untuk peringanan.
Dan perbedaan yang paling jelas bahwasanya masalahah mursalah adalah wasilah untuk bisa melaksanakan seeuatu perkara dan bukan tujuan utama, berbeda dengan bid'ah.
Madinah, 21 Dzul Hijjah 1431 / 27 November 2010
Abu ‘Abdilmuhsin Firanda Andirja (www.firanda.com)
Tuesday, 14 December 2010
~ Syubhat-Syubhat Para Pendukung Bid'ah Hasanah ~
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 11:52 pm 0 comments
Labels: ~ Aqidah Sohihah ~, ~ Sunnah Dan Bid'ah ~
~ Shalat dengan Pakaian yang Terkena Mani, Madzi dan Wadi ~

Pertanyaan:
Bolehkah shalat dengan pakaian yang terkena mani, atau madzi, ataupun wadi?
Jawaban:
Tidak terdapat satu dalil pun yang mengatakan najisnya mani. Ada sebuah pembahasan yang panjng, yang ditulis oleh Ibnul Qayyim dalam kitab I’lamul Muwaqqi’in, yang mana di dalamnya terdapat diskusi panjang antara orang yang menganggap mani itu najis dengan orang yang berpendapat bahwa mani itu suci. Tampak jelas dalam diskusi tersebut bahwa mani itu suci.
Berdasarkan hal ini, maka seseorang dibolehkan shalat dengan pakaian yang terkena mani, tetapi disunnahkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu ketika beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam shalat denagn pakaian yang terkena mani yang kering, maka mani kering tersebut dikerik terlebih dahulu, dan jika basah maka beliau menghilangkannya dengan “idzkhir” tumbuhan, seperti rumput yang wangi, atau dengan benda lain.
Adapun madzi dan wadi, dua-duanya adalah najis, sehingga wajib dibersihkan sebagaimana kencing.
Sumber: Fatwa-Fatwa Syekh Nashiruddin Al-Albani, Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Media Hidayah, 1425 H — 2004 M.
(Dengan beberapa pengubahan tata bahasa oleh redaksi www.konsultasisyariah.com)
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 4:12 pm 0 comments
Labels: ~ Fiqh Dan Ibadah ~
Saturday, 11 December 2010
~ Agama adalah NASIHAT ~

(Oleh : Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas)
عَنْ أَبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،
عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ، الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ،
قَالُوْا : لِمَنْ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟
قَالأَ : لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ
أَوْ لِلمُؤْمِنِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ
Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dâri radhiyallâhu'anhu,
dari Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bahwasanya beliau bersabda:
“Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat”.
Mereka (para sahabat) bertanya, ”Untuk siapa, wahai Rasûlullâh?”
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam menjawab,
”Untuk Allâh, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Imam kaum Muslimin atau Mukminin,
dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.”
TAKHRIJ HADITS
Hadits ini diriwayatkan dari jalan Suhail bin Abi Shalih, dari ‘Atha’ bin Yazid al-Laitsi, dari Abu Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dâri radhiyallâhu'anhu. Hadits ini diriwayatkan oleh:
Imam Muslim (no. 55 [95]).
Imam Abu ‘Awanah (I/36-37).
Imam al-Humaidi (no. 837).
Imam Abu Dawud (no. 4944).
Imam an-Nasâ-i (VII/156-157).
Imam Ahmad (IV/102-103).
Imam Ibnu Hibbân. Lihat at-Ta’lîqâtul-Hisân ‘alâ Shahîh Ibni Hibbân (no. 4555) dan Ra-udhatul- ‘Uqalâ` (no. 174).
Imam al-Baihaqi (VIII/163).
Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi dalam Ta’zhîm Qadrish-Shalâh (II/681 no. 747,749,751,755).
Imam ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabîr (no. 1260-1268).
Imam al-Baghawi dalam Syarhus-Sunnah (XIII/93, no. 3514).
Hadits ini memiliki syawâhid (penguat) dari beberapa sahabat, yaitu:
Abu Hurairah; diriwayatkan oleh Imam an-Nasâ-i (VII/157), at-Tirmidzi (no. 1926), Ahmad (II/297), dan Ibnu Nashr al-Marwazi, dalam Ta’zhîm Qadrish-Shalâh (II/682 no. 748). At-Tirmidzi berkata,”Hadits hasan shahih.”
Ibnu Umar; diriwayatkan oleh Imam ad-Dârimi (II/311) dan Ibnu Nashr al-Marwazi (no. 757-758).
Ibnu ‘Abbas; diriwayatkan oleh Imam Ahmad (I/351) dan ath-Thabrani dalam al-Mu’jamul-Kabîr (no. 11198).
Para ulama ahli hadits menjelaskan bahwa hadits di atas shahih.
BIOGRAFI SINGKAT PERAWI HADITS
Beliau adalah seorang sahabat Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam, Abu Ruqayyah, Tamîm bin Aus bin Kharijâh bin Su-ud bin Jadzimah al-Lakhmi al-Falasthini ad-Dâri. Dahulu, beliau seorang yang beragama Nasrani dan sebagai rahib dan ahli ibadah penduduk Palestina. Kemudian pindah ke Madinah lalu masuk Islam bersama saudaranya, Nu’aim, pada tahun 9H. Beliau menetap di Madinah sampai akhirnya pindah ke Syam setelah terjadinya pembunuhan Khalifah ‘Utsmân bin ‘Affân radhiyallâhu'anhu.
Beliau adalah seorang yang tekun melakukan shalat Tahajjud, selalu menghatamkan Al-Qur‘ân. Beliau pernah menceritakan tentang kisah Jassasah dan Dajjal kepada Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam, kemudian Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam menyampaikan kisah tersebut kepada para sahabat di atas mimbar. Ini menunjukkan keutamaan beliau. Beliau juga ikut berperang bersama Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam.
Tamim ad-Dâri adalah orang yang pertama kali memasang lampu di dalam masjid dan membacakan kisah-kisah. Ini dilakukan pada zaman pemerintahan ‘Umar bin al-Khaththâb radhiyallâhu'anhu. Beliau meriwayatkan delapan belas hadits dari Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam. Satu hadits diantaranya terdapat dalam Shahîh Muslim. Beliau wafat di Palestina pada tahun 40 H. [1]
PENGERTIAN NASIHAT
Kata “nasihat” berasal dari bahasa Arab. Diambil dari kata kerja “nashaha” (نَصَحَ), yang maknanya “khalasha” (خَلَصَ). Yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Bisa juga bermakna “khâtha” (خَاطَ), yaitu menjahit.[2]
Imam al-Khaththabi rahimahullâhmenjelaskan arti kata “nashaha”, sebagaimana dinukil oleh Imam an- Nawawi rahimahullâh, “Dikatakan bahwa “nashaha” diambil dari “nashahar-rajulu tsaubahu” (نَصَحَ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ) apabila dia menjahitnya. Maka mereka mengumpamakan perbuatan penasihat yang selalu menginginkan kebaikan orang yang dinasihatinya, dengan usaha seseorang memperbaiki pakaiannya yang robek.”[3]
Imam Ibnu Rajab rahimahullâh menukil ucapan Imam al- Khaththabi rahimahullâh:
“Nasihat, ialah kata yang menjelaskan sejumlah hal. Yaitu menginginkan kebaikan pada orang yang diberi nasihat”.
Hal ini juga dikemukakan oleh Ibnul-Atsîr rahimahullâh .[4]
Kesimpulannya, nasihat adalah kata yang dipakai untuk mengungkapkan keinginan memberikan kebaikan pada orang yang diberi nasihat.
AGAMA ADALAH NASIHAT
Hadits ini merupakan ucapan singkat dan padat, yang hanya dimiliki Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam. Ucapan singkat, namun mengandung berbagai nilai dan manfaat penting. Semua hukum syari’at, baik ushul (pokok) maupun furu’ (cabang) terdapat padanya. Bahkan satu kalimat “wa li Kitâbihi” saja, ia sudah mencakup semuanya. Karena Kitab Allâh mencakup seluruh permasalahan agama, baik ushul maupun furu’, perbuatan maupun keyakinan.
Allâh Ta'ala berfirman:
Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun dalam Kitab ini. (Qs al-An’âm/6:38)
Oleh karena itu, ada ulama yang berpendapat hadits ini merupakan poros ajaran Islam.
Dalam hadits ini Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam menamakan agama sebagai nasihat. Padahal beban syari’at sangat banyak dan tidak terbatas hanya pada nasihat. Lalu apakah maksud Beliau Shallallâhu 'Alaihi Wasallam tersebut?
Para ulama telah memberikan jawaban.
Pertama, hal ini bermakna, bahwa hampir semua agama adalah nasihat, sebagaimana halnya sabda Beliau Shallallâhu 'Alaihi Wasallam:
الْحَخُّ عَرَفَةُ
Haji itu adalah wukuf di ‘Arafah.[5]
Kedua, agama itu seluruhnya adalah nasihat. Karena setiap amalan yang dilakukan tanpa disertai ikhlas, maka tidak termasuk agama.[6]
Setiap nasihat untuk Allâh Ta'ala menuntut pelaksanaan kewajiban agama secara sempurna. Inilah yang disebut derajat ihsân. Tidaklah sempurna nasihat untuk Allâh tanpa hal ini. Tidaklah mungkin dicapai, bila tanpa disertai kesempurnaan cinta yang wajib dan sunnah, tetapi juga diperlukan kesungguhan mendekatkan diri kepada Allâh Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan sunnah-sunnah secara sempurna dan meninggalkan hal-hal yang haram dan makruh secara sempurna pula.[7]
Ketiga, nasihat meliputi seluruh bagian Islam, iman, dan ihsân, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits Jibril.
Dengan demikian jelaslah keterangan para ulama tentang maksud sabda beliau Shallallâhu 'Alaihi Wasallam “agama itu nasihat”. Karena nasihat, adakalanya bermakna pensifatan sesuatu dengan sifat kesempurnaan Allâh, Kitab-Nya, dan Rasul-Nya. Adakalanya merupakan penyempurnaan kekurangan yang terjadi, berupa nasihat untuk pemimpin dan kaum Muslimin pada umumnya, sebagaimana rincian selanjutnya dalam hadits ini.
SYARAH HADITS
1. Nasihat untuk Allâh Ta'ala.
Al-Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi rahimahullâh (wafat 294H) berkata:
"Nasihat hukumnya ada dua. Yang pertama wajib, dan yang kedua sunnah. Adapun nasihat yang wajib untuk Allâh. Yaitu perhatian yang sangat dari pemberi nasihat untuk mengikuti semua yang Allâh cintai, dengan melaksanakan kewajiban, dan dengan menjauhi semua yang Allâh haramkan. Sedangkan nasihat yang sunnah, adalah dengan mendahulukan perbuatan yang dicintai Allâh daripada perbuatan yang dicintai oleh dirinya sendiri. Yang demikian itu, bila dua hal dihadapkan pada diri seseorang, yang pertama untuk kepentingan dirinya sendiri dan yang lain untuk Rabb-nya, maka dia memulai mengerjakan sesuatu untuk Rabb-nya terlebih dahulu dan menunda semua yang diperuntukkan bagi dirinya sendiri."
Demikian ini penjelasan nasihat untuk Allâh Ta'ala secara global, baik yang wajib maupun yang sunnah. Adapun perinciannya akan kami sebutkan sebagiannya agar bisa dipahami dengan lebih jelas.
Nasihat yang wajib untuk Allâh, ialah menjauhi larangan-Nya dan melaksanakan perintah-Nya dengan seluruh anggota badannya selagi mampu melakukannya. Apabila ia tidak mampu melakukan kewajibannya karena suatu alasan tertentu, seperti sakit, terhalang, atau sebab-sebab lainnya, maka ia tetap berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban tersebut, apabila penghalang tadi telah hilang.
Allâh Ta'ala berfirman:
Tidak ada dosa (lantaran tidak pergi berjihad) atas orang-orang yang lemah,
atas orang-orang yang sakit dan atas orang-orang yang
tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila mereka menasihati kepada Allah dan Rasul-Nya (cinta kepada Allah dan Rasul-Nya).
Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.
Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Qs at-Taubah/9:91)
Allâh Ta'ala menamakan mereka sebagai “al-muhsinîn” (orang-orang yang berbuat kebaikan), karena perbuatan mereka berupa nasihat untuk Allâh Ta'ala dengan hati mereka yang ikhlas ketika mereka terhalang untuk berjihad dengan jiwa raganya.
Dalam kondisi tertentu, terkadang seorang hamba dibolehkan meninggalkan sejumlah amalan, tetapi tidak dibolehkan meninggalkan nasihat untuk Allâh Ta'ala, meskipun disebabkan sakit yang tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu dengan anggota tubuhnya, bahkan dengan lisan, dan lain-lain, namun akalnya masih sehat, maka belum hilang kewajiban memberikan nasihat untuk Allâh Ta'ala dengan hatinya. Yaitu dengan penyesalan atas dosa-dosanya dan berniat dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan Allâh Ta'ala kepadanya, dan meninggalkan apa-apa yang di larang Allâh Ta'ala.
Jika tidak (yaitu tidak ada amalan hati, berupa cinta, takut, dan harap kepada Allâh Ta'ala dan niat untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan-Nya), maka ia tidak disebut sebagai pemberi nasihat untuk Allâh Ta'ala dengan hatinya.
Juga termasuk nasihat untuk Allâh Ta'ala, ialah taat kepada Rasul-Nya dalam hal yang beliau wajibkan kepada manusia berdasarkan perintah Rabb-nya. Dan termasuk nasihat yang wajib untuk Allâh Ta'ala, ialah dengan membenci dan tidak ridha terhadap kemaksiatan orang yang berbuat maksiat, dan cinta kepada ketaatan orang yang taat kepada Allâh Ta'ala dan Rasul-Nya.
Sedangkan nasihat yang sunnah (bukan yang wajib), ialah dengan berjuang sekuat tenaga untuk lebih mengutamakan Allâh Ta'ala daripada segala apa yang ia cintai dalam hati dan seluruh anggota badan bahkan dirinya sendiri, lebih-lebih lagi dari orang lain. Karena seorang penasihat, apabila bersungguh-sungguh kepada orang yang dicintainya, dia tidak akan mementingkan dirinya, bahkan berupaya keras melakukan hal-hal yang membuat orang yang dicintainya itu merasa senang dan cinta, maka begitu pula pemberi nasihat untuk Allâh Ta'ala.
Barangsiapa yang melakukan ibadah nafilah (sunnah) untuk Allâh Ta'ala tanpa dibarengi dengan kerja keras, maka dia adalah penasihat berdasarkan tingkatan amalnya, tetapi tidak melaksanakan nasihat dengan sebenarnya secara sempurna.[8]
Imam an-Nawawi rahimahullâh menyebutkan, termasuk nasihat untuk Allâh Ta'ala adalah dengan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada-Nya dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allâh Ta'ala. Adapun makna nasihat untuk Allâh Ta'ala, ialah beriman kepada Allâh Ta'ala, menafikan sekutu bagi-Nya, tidak mengingkari sifat-sifat- Nya, mensifatkan Allâh Ta'ala dengan seluruh sifat yang sempurna dan mulia, mensucikan Allâh Ta'ala dari semua sifat-sifat yang kurang, melaksanakan ketaatan kepada-Nya, menjauhkan maksiat, mencintai karena Allâh Ta'ala, benci karena-Nya, loyal (mencintai) orang yang taat kepada-Nya, memusuhi orang yang durhaka kepada-Nya, berjihad melawan orang yang kufur kepada-Nya, mengakui nikmat-Nya, dan bersyukur atas segala nikmat-Nya …[9]
Ibnu Rajab rahimahullâh menyebutkan, termasuk nasihat untuk Allâh Ta'ala, ialah dengan berjihad melawan orang-orang yang kufur kepada-Nya dan berdakwah mengajak manusia ke jalan Allâh Ta'ala.[10]
Syaikh Muhammad Hayât as-Sindi rahimahullâh (wafat 1163 H) berkata,
”Maksud nasihat untuk Allâh Ta'ala, ialah agar seorang hamba menjadikan dirinya ikhlas kepada Rabb-nya dan meyakini Dia adalah Ilah Yang Maha Esa dalam Uluhiyyah-Nya, dan bersih dari noda syirik, tandingan, penyerupaan, serta segala apa yang tidak pantas bagi-Nya. Allâh Ta'ala mempunyai segala sifat kesempurnaan yang sesuai dengan keagungan- Nya. Seorang muslim harus mengagungkan-Nya dengan sebesar-besarnya pengagungan, melakukan amalan zhahir dan batin yang Allâh Ta'ala cintai dan menjauhi apa-apa yang Allâh Ta'ala benci, mencintai apa-apa yang Allâh Ta'ala cintai dan membenci apa-apa yang Allâh Ta'ala benci, meyakini apa-apa yang Allâh Ta'ala jadikan sesuatu itu benar sebagai suatu kebenaran, dan yang bathil itu sebagai suatu kebathilan, hatinya dipenuhi dengan rasa cinta dan rindu kepada-Nya, bersyukur atas nikmat-nikmat-Nya, sabar atas bencana yang menimpanya, serta ridha dengan taqdir-Nya.”[11]
2. Nasihat untuk Kitâbullâh.
Al-Imam Ibnu Nashr al-Marwazi rahimahullâh berkata,
”Sedangkan nasihat untuk Kitabullah, ialah dengan sangat mencintai dan mengagungkan kedudukannya karena Al-Qur’an itu adalah Kalâmullâh, berkeinginan kuat untuk memahaminya, mempunyai perhatian yang besar dalam merenunginya, serius dan penuh konsentrasi membacanya untuk mendapatkan pemahaman maknanya sesuai dengan yang dikehendaki Allâh untuk dipahami, dan setelah memahaminya ia mengamalkan isinya. Begitu pula halnya seorang yang menasihati dari kalangan hamba, dia akan mempelajari wasiat dari orang yang menasihatinya. Apabila ia diberi sebuah buku dengan maksud untuk dipahaminya, maka ia mengamalkan apa-apa yang tertulis dari wasiat tersebut. Begitu pula pemberi nasihat untuk Kitâbullâh, dia dituntut untuk memahaminya agar dapat mengamalkannya karena Allâh; sesuai dengan apa yang Allâh cintai dan ridhai, kemudian menyebarluaskan yang dia pahami kepada manusia, dan mempelajari Al-Qur-an terus-menerus didasari rasa cinta kepadanya, berakhlak dengan akhlaknya, serta beradab dengan adab-adabnya.”[12]
Hal ini diwujudkan dalam bentuk iman kepada Kitab-kitab samawi yang diturunkan Allâh Ta'ala dan meyakini Al-Qur‘ân merupakan penutup dari semua Kitab-kitab tersebut. Al-Qur‘an adalah Kalâmullâh yang penuh dengan mukjizat, yang senantiasa terpelihara, baik dalam hati maupun dalam lisan. Allâh Ta'ala sendirilah yang menjamin hal itu.
Allâh Ta'ala berfirman:
Sesungguhnya Kami yang menurunkan adz-Dzikr (Al-Qur‘ân) dan Kami sendiri yang menjaganya.(Qs al-Hijr/15:9)[13]
Menurut Syaikh Muhammad Hayât as-Sindi rahimahullâh, nasihat untuk kitab-Nya adalah dengan meyakini Al-Qur‘ân itu Kalâmullâh. Wajib mengimani apa-apa yang ada di dalamnya, wajib mengamalkan, memuliakan, membacanya dengan sebenar-benarnya, mengutamakannya daripada selainnya, dan penuh perhatian untuk mendapatkan ilmu-ilmunya. Dan di dalamnya terdapat ilmu-ilmu mengenai Uluhiyyah Allâh yang tidak terhitung banyaknya. Dia merupakan teman dekat orang-orang yang berjalan menempuh jalan Allâh, dan merupakan wasilah (jalan) bagi orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allâh. Dia sebagai penyejuk mata bagi orang-orang yang berilmu. Barangsiapa yang ingin sampai di tempat tujuan, maka ia harus menempuh jalannya. Karena kalau tidak, ia pasti tersesat. Seandainya seorang hamba mengetahui keagungan Kitâbullâh, niscaya ia tidak akan meninggalkannya sedikitpun.[14]
Secara rinci, nasihat untuk Kitâbullâh dilakukan melalui beberapa hal berikut.
a.Membaca dan menghafal Al-Al-Qur‘ân.
Dengan membaca al-Al-Qur‘ân akan didapatkan berbagai ilmu dan pengetahuan. Disamping itu akan melahirkan kebersihan jiwa, kejernihan perasaan, dan mempertebal ketakwaan. Membaca Al-Qur‘ân merupakan kebaikan dan merupakan syafa’at yang akan diberikan pada hari Kiamat kelak.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Bacalah Al-Qur‘ân, karena pada hari Kiamat ia akan datang untuk memberi syafa’at kepada orang yang membacanya.[15]
Sedangkan menghafal Al-Qur‘ân merupakan keutamaan yang besar. Melalui hafalan, hati akan lebih hidup dengan cahaya Kitâbullâh, manusia juga akan segan dan menghormatinya. Bahkan dengan hafalan itu, derajatnya di akhirat akan semakin tinggi, sesuai dengan banyaknya hafalan yang dimiliki.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Dikatakan kepada orang yang shahib (orang yang mengilmui dan mengamalkannya) Al-Qur‘ân,
”Bacalah dan naiklah! Bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia dengan tartil. Karena kedudukanmu (di surga) sesuai dengan ayat terakhir yang engkau baca”. [16]
Membacanya dengan tartil dan suara yang bagus, sehingga bacaannya dapat masuk dan diresapi.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Bukan golongan kami orang yang tidak membaca Al-Qur‘ân dengan irama.[17]
b.Mentadabburi nilai-nilai yang terkandung dalam setiap ayatnya.
Allâh Ta’ala berfirman:
Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur‘ân
ataukah hati mereka terkunci? (Qs Muhammad/ 47:24)
c.Mengajarkannya kepada generasi muslim agar ikut berperan dalam menjaga Al-Qur‘ân.
Mempelajari dan mengajarkan Al-Qur‘an adalah kunci kebahagiaan dan ‘izzah (kejayaan) umat Islam.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari
dan mengajarkan Al-Qur‘ân.[18]
d.Memahami dan mengamalkannya.
Seorang muslim wajib membaca Al-Qur‘ân dan harus berusaha memahaminya serta berusaha untuk mengamalkannya. Bagaimanapun, buah membaca Al-Qur‘ân baru akan kita peroleh setelah memahami dan mengamalkannya. Oleh karena itu, alangkah buruknya jika kita memahami ayat Al-Qur‘ân namun tidak mau mengamalkannya.
Allâh Ta'ala berfirman:
Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allâh bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (Qs ash-Shaff/61:2-3)[19]
3. Nasihat untuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
Al-Imam Ibnu Nashr al-Marwazi rahimahullâh berkata:
"Sedangkan nasihat untuk Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam pada masa hidupnya, ialah dengan mengerahkan segala kemampuan secara sungguh-sungguh dalam rangka taat, membela, menolong, memberikan harta (untuk perjuangan menegakkan agama Allâh) bila beliau menginginkannya, dan bersegera untuk mencintai beliau. Adapun setelah Beliau wafat, maka dengan perhatian dan kesungguhan untuk mencari Sunnah-nya, akhlak, dan adab-adabnya, mengagungkan perintahnya, istiqâmah dalam melaksanakannya, sangat marah dan berpaling dari orang yang menjalankan agama yang bertentangan dengan Sunnah-nya, marah terhadap orang yang menyia-nyiakan Sunnah beliau hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia, meskipun ia meyakini akan kebenarannya, mencintai orang yang memiliki hubungan dengan Beliau, dari kalangan karib kerabat atau familinya, juga dari kaum Muhajirin dan Anshar, atau dari seorang sahabat yang menemani Beliau sesaat di malam atau siang hari, dan dengan mengikuti tuntunan beliau dalam hal berpenampilan dan berpakaian."[20]
Yang dimaksud dengan nasihat untuk Rasul-Nya, ialah dengan meyakini Beliau adalah seutama-utama makhluk dan kekasih-Nya. Allâh mengutusnya kepada para hamba-Nya, agar Beliau mengeluarkan mereka dari segala kegelapan kepada cahaya, menjelaskan kepada mereka semua yang membuat mereka bahagia dan semua yang membuat mereka sengsara, menerangkan kepada mereka jalan Allâh yang lurus agar mereka lulus mendapatkan kenikmatan surga dan terhindar dari kepedihan api neraka, dan dengan mencintainya, memuliakannya, mengikutinya serta tidak ada kesempitan di dadanya terhadap semua yang Beliau putuskan. Tunduk serta patuh kepada Beliau, seperti orang yang buta mengikuti petunjuk jalan orang yang tajam matanya.
Orang yang menang, adalah orang yang menang membawa kecintaan dan ketaatan pada Sunnahnya. Dan orang yang rugi, adalah orang yang terhalang dari mengikuti ajarannya. Barangsiapa yang taat kepada Beliau, maka ia taat kepada Allâh. Barangsiapa yang menentangnya, maka ia telah menentang Allah dan kelak akan diberi balasan setimpal.[21]
Hal ini diaplikasikan dalam bentuk membenarkan risalahnya, membenarkan semua yang disampaikan, baik dalam Al-Qur‘an maupun as-Sunnah, serta mencintai dan mentaatinya. Mencintai Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam ialah dengan ittibâ’ (mengikuti) beliau dan taat kepadanya.
Allâh Ta’ala berfirman:
Katakanlah (hai Muhammad): “Jika kalian mencintai Allâh, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya kalian dicintai Allâh”.
(Qs Ali ‘Imran/3:31)
Ketaatan kepada Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam merupakan bentuk ketaatan kepada Allâh Ta’ala.
Allâh Ta’ala berfirman:
Barangsiapa yang taat kepada Rasul, maka ia telah mentaati Allâh.
(Qs an- Nisâ‘/4:80)
4. Nasihat untuk Para Pemimpin Kaum Muslimin.
Al-Imam Ibnu Nashr al-Marwazi rahimahullâh berkata,
”Sedangkan nasihat untuk para pemimpin kaum Muslimin, ialah dengan mencintai ketaatan mereka kepada Allâh, mencintai kelurusan dan keadilan mereka, mencintai bersatunya umat di bawah pengayoman mereka, benci kepada perpecahan umat dengan sebab melawan mereka, mengimani bahwa taat kepada mereka ialah demi ketaatan kepada Allâh, membenci orang yang keluar dari ketaatan kepada mereka (yaitu membenci orang yang tidak mengakui kekuasaan mereka dan menganggap darah mereka halal), dan mencintai kejayaan mereka dalam taat kepada Allâh.”[22]
Syaikh Muhammad Hayât as-Sindi rahimahullâh berkata,
”Makna ‘nasihat untuk para pemimpin kaum Muslimin’, ialah nasihat yang ditujukan kepada para penguasa mereka. Yaitu dengan menerima perintah mereka, mendengar, dan taat kepada mereka dalam hal yang bukan maksiat, karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Al-Khaliq. Tidak memerangi mereka selama mereka belum kafir, berusaha untuk memperbaiki keadaan mereka, membersihkan kerusakan mereka, memerintahkan mereka kepada kebaikan, melarangnya dari kemungkaran, serta mendo’akan mereka agar mendapatkan kebaikan. Karena, dalam kebaikan mereka berarti kebaikan bagi rakyat, dan dalam kerusakan mereka berarti kerusakan bagi rakyat.”[23]
Yang dimaksud dengan pemimpin kaum Muslimin, ialah para penguasa, wakil-wakilnya, atau para ulama. Agar penguasa ditaati, maka penguasa tersebut harus dari orang Islam sendiri.
Allâh Ta’ala berfirman:
Hai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allâh, taatlah kepada Rasul dan penguasa dari kalian.(QS. An-Nisaa’: 59)
Nasihat untuk pemimpin, ialah dengan mencintai kebaikan, kebenaran, dan keadilannya, bukan lantaran individunya. Karena, melalui kepemimpinannyalah kemaslahatan kita bisa terpenuhi. Kita juga senang dengan persatuan umat di bawah kepemimpinan mereka yang adil dan membenci perpecahan umat di bawah penguasa yang semena-mena.
Nasihat untuk para pemimpin dapat juga dilakukan dengan cara membantu mereka untuk senantiasa berada di atas jalan kebenaran, menaati mereka dalam kebenaran, dan mengingatkan mereka dengan cara yang baik. Termasuk prinsip Ahlus Sunnah wal-Jama’ah, ialah tidak melakukan provokasi atau penghasutan untuk memberontak kepada penguasa, meskipun penguasa itu berbuat zhalim. Tidak boleh melakukan provokasi, baik dari atas mimbar, tempat khusus maupun umum, atau media lainnya. Karena yang demikian menyalahi petunjuk Nabi Shallallâhu 'Alaihi Wasallam dan Salafush-Shalih.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkan dengan terang-terangan. Hendaklah ia pegang tangannya lalu menyendiri dengannya. Bila penguasa itu mau mendengar nasihat tersebut maka itu yang terbaik.
Dan bila si penguasa itu enggan (tidak mau menerima)maka sungguh ia telah melaksanakan kewajiban amanah yang dibebankan kepadanya.[24]
Sesungguhnya tidak ada kebaikan bagi masyarakat yang tidak mau menasihati penguasanya dengan cara yang baik. Juga tidak ada kebaikan, bagi penguasa yang menindas rakyatnya dan membungkam orang-orang yang berusaha menasihatinya, bahkan menutup telinganya rapat-rapat agar tidak mendengar suara-suara kebenaran. Dalam kondisi seperti ini, yang terjadi justru kerendahan dan kehancuran. Ini sangat mungkin terjadi jika masyarakat muslim telah menyeleweng dan jauh dari nilai-nilai Islam.
Adapun para ulama, nasihat yang dilakukan untuk Kitâbullâh dan Sunnah Rasûlullâh, dilakukan dengan jalan membantah berbagai pendapat sesat berkenaan dengan Al-Qur‘an dan as-Sunnah. Menjelaskan berbagai hadits, apakah hadits tersebutshahih atau dha’if.
Para ulama juga mempunyai tanggung-jawab yang besar untuk selalu menasihati para penguasa, dan senantiasa menyerukan agar para penguasa berhukum dengan hukum Allâh dan Rasul-Nya. Jika mereka lalai dalam mengemban tanggung jawab ini sehingga tidak ada seorang pun yang menyerukan kebenaran di depan penguasa, maka kelak Allâh akan menghisabnya.
Kepada para ulama, hendaklah mereka terus-menerus berusaha datang menyampaikan kebenaran dan nasihat yang baik kepada pemerintah (penguasa) dan sabar dalam melakukannya, karena menyampaikan kalimat yang baik termasuk seutama-utama jihad.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Jihad yang paling utama adalah mengatakan keadilan (dalam riwayat lain: kebenaran) di hadapan penguasa yang semena-mena.[25]
Para ulama juga akan dimintai pertanggung-jawaban, jika mereka justru memuji penguasa yang semena-mena, bahkan kemudian menjadi corong mereka. Sedangkan nasihat kita untuk para ulama, ialah dengan senantiasa mengingatkan mereka akan tanggung jawab tersebut, mempercayai hadits-hadits yang mereka sampaikan, jika memang mereka orang yang bisa dipercaya. Juga dengan jalan tidak mencerca mereka, karena hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan dan membuat mereka sebagai bahan tuduhan.
5. Nasihat untuk Kaum Muslimin.
Makna “nasihat untuk kaum Muslimin pada umumnya”, ialah dengan menolong mereka dalam kebaikan, melarang mereka berbuat keburukan, membimbing mereka kepada petunjuk, mencegah mereka dengan sekuat tenaga dari kesesatan, dan mencintai kebaikan untuk mereka sebagaimana ia mencintainya untuk diri sendiri, karena mereka semua adalah hamba-hamba Allâh. Maka seorang hamba harus memandang mereka dengan landasan yang satu, yaitu kacamata kebenaran.[26]
Nasihat untuk masyarakat muslim, dilakukan dengan cara menuntun mereka kepada berbagai hal yang membawa kebaikan dunia dan akhiratnya. Sangat disayangkan, kaum Muslimin telah mengabaikan tugas ini. Mereka tidak mau menasihati muslim yang lain, khususnya berkaitan dengan urusan akhirat.
Nasihat yang dilakukan seharusnya tidak terbatas dengan ucapan, tetapi harus diikuti dengan amalan. Dengan demikian, nasihat tersebut akan terlihat nyata dalam masyarakat muslim, sebagai penutup keburukan, pelengkap kekurangan, pencegah terhadap bahaya, pemberi manfaat, amar ma’ruf nahyu mungkar, penghormatan terhadap yang besar, kasih sayang terhadap yang lebih kecil, serta menghindari penipuan dan kedengkian.[27]
6. Nasihat yang Paling Baik Di antara Kaum Muslimin.
Nasihat yang paling baik, ialah nasihat yang diberikan ketika seseorang dimintai nasihat.
Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam bersabda:
Jika seseorang meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah ia.[28]
Termasuk nasihat yang paling baik, yaitu nasihat yang dilakukan seseorang kepada orang lain ketika orang tersebut (yang dinasihati) tidak ada di hadapannya. Yaitu dilakukan dengan cara menolong dan membelanya.
7. Kedudukan Orang yang Memberikan Nasihat.
Amal para rasul ialah menasihati manusia kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat.
Allâh Ta'ala berfirman menceritakan hamba-Nya, Nabi Hud 'alaihissalam :
Aku menyampaikan amanat-amanat Rabb-ku kepadamu
dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. (Qs al-A’râf/7: 68)
Allâh Ta'ala juga menceritakan Nabi Shalih 'alaihissalam yang berbicara kepada kaumnya:
Maka Shalih meninggalkan mereka seraya berkata:
“Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Rabb-ku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu,tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat”.(Qs Al-A’râf/7:79)
Seseorang seharusnya merasa cukup mulia dengan melaksanakan amalan hamba-hamba Allâh yang paling mulia, yaitu para nabi dan rasul. Demikianlah hakikat nasihat. Mudah-mudahan Allâh Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang selalu saling menasihati. Sehingga memiliki sebagian sifat-sifat orang yang beruntung, sebagaimana telah digariskan Allâh Ta'ala dengan firman-Nya:
Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat-menasihati supaya menetapi kesabaran. (Qs al-‘Ashr/103:1-3)
HUKUM MEMBERIKAN NASIHAT
Diriwayatkan dari Jarir bin ‘Abdillah radhiyallâhu'anhu, ia berkata:
Aku membai’at Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam
(dengan isi kandungan bai'at, aku akan) tetap mengerjakan shalat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim.[29]
Imam Nawawi rahimahullâh berkata,
”Hukum memberi nasihat ialah fardhu kifayah. Artinya, apabila ada seseorang yang sudah mengerjakannya maka gugurlah kewajiban atas yang lain. Dan nasihat ini adalah wajib menurut kadar kemampuan.”
Syaikh Nazhim Muhammad Sulthân berkata,
”Saya berpendapat, hukum memberi nasihat dengan maknanya yang menyeluruh sebagaimana sudah dijelaskan, ada yang fardhu ‘ain, ada yang fardhu kifayah, ada yang wajib, dan ada juga yang sunnah. Karena Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam menjelaskan, agama adalah nasihat. Sedangkan hukum-hukum agama ada yang wajib, sunnah, fardhu ‘ain, dan fardhu kifayah.”[30]
ADAB-ADAB MEMBERI NASIHAT
Di antara adab memberi nasihat dalam Islam, yaitu menasihati saudaranya dengan tidak diketahui orang lain. Karena, barangsiapa menutupi keburukan saudaranya maka Allâh Ta'ala akan menutupi keburukannya di dunia dan akhirat. Sebagian ulama berkata, barangsiapa menasihati seseorang dan hanya ada mereka berdua, maka itulah nasihat yang sebenarnya.
Barangsiapa menasihati saudaranya di depan banyak orang maka yang demikian itu mencela dan merendahkan orang yang dinasihati. Fudhail bin Iyadh rahimahullâh berkata,
"Seorang mukmin, ialah orang yang menutupi aib dan menasihati. Sedangkan orang fasik, ialah orang yang merusak dan mencela."[31]
Al-Imam Ibnu Hibbân rahimahullâh (wafat 354 H) berkata,
"Sebagaimana telah kami sebutkan, memberi nasihat merupakan kewajiban seluruh manusia, tetapi dalam cara menyampaikannya -tidak boleh tidak- harus secara rahasia. Karena, barangsiapa menasihati saudaranya di hadapan orang lain, berarti ia telah mencelanya. Dan barangsiapa yang menasihatinya secara rahasia, berarti ia telah memperbaikinya. Sesungguhnya menyampaikan dengan penuh perhatian kepada saudaranya sesama muslim adalah kritik yang membangun, lebih besar kemungkinannya untuk diterima daripada menyampaikan dengan maksud mencelanya."
Kemudian al-Imam Ibnu Hibban rahimahullâh menyebutkan dengan sanadnya sampai kepada Sufyan, ia berkata:
"Saya bertanya kepada Mis’ar, ‘Apakah engkau suka bila ada orang lain memberitahukan kekurangan-kekuranganmu?’
Ia menjawab, ’Apabila yang datang adalah orang yang memberitahukan kekurangan-kekuranganku dengan cara menjelek-jelekkanku, maka aku tidak senang. Tetapi bila yang datang kepadaku seorang pemberi nasihat, maka aku senang’.”
Abu Hatim (Imam Ibnu Hibban) rahimahullâh mengatakan,
”Nasihat, apabila dilakukan seperti apa yang telah kami sebutkan maka akan melanggengkan kasih sayang dan menjadi penyebab terwujudnya hak ukhuwah (persaudaraan).”[32]
Al-Imam Abu Muhammad bin Ahmad bin Sa’id Ibnu Hazm rahimahullâh (wafat 456 H) berkata,
”Maka wajib bagi seseorang untuk selalu memberi nasihat, baik yang diberi nasihat itu suka maupun benci, tersinggung maupun tidak tersinggung. Apabila engkau memberikan nasihat maka sampaikan secara rahasia, jangan di hadapan orang lain dan cukup dengan memberikan isyarat, tanpa secara terus-terang. Kecuali, orang yang dinasihati tidak memahami isyaratmu maka harus secara terus-terang. Janganlah memberi nasihat dengan syarat harus diterima. Jika engkau melampaui batas adab-adab tersebut maka engkau orang yang zhalim, bukan pemberi nasihat, dan gila ketaatan serta gila kekuasaan, bukan pemberi amanat dan pelaksana hak ukhuwah. Ini bukanlah termasuk hukum akal dan hukum persahabatan, melainkan hukum rimba seperti seorang penguasa dengan rakyatnya, dan tuan dengan hamba sahayanya.”[33]
Imam asy-Syafi’i rahimahullâh berkata dalam sya’irnya:
Tutupilah kesalahanku dengan nasihatmu ketika aku seorang diri.
Hindarilah menasihatiku di tengah khalayak ramai.
Karena memberikan nasihat di hadapan banyak orang.
Sama saja dengan memburuk-burukkan, aku tidak sudi mendengarnya.
Jika engkau menyalahiku dan tidak mengikuti ucapanku.
Maka janganlah engkau kaget bila nasihatmu tidak ditaati. [34]
FAWAID HADITS
* Nasihat memiliki kedudukan yang besar dan agung dalam agama Islam.
* Nasihat ditujukan kepada Allah, Kitab-Nya, Rasul- Nya, pemimpin kaum Muslimin, dan kepada kaum Muslimin pada umumnya.
* Wajib ikhlas dalam beribadah kepada Allah Ta’ala.
* Wajib ikhlas dalam memberikan nasihat.
* Tidak boleh khianat dalam memberikan nasihat.
* Bolehnya mengakhirkan keterangan dari waktu ketika menyampaikan nasihat.
* Nasihat dikatakan sebagai agama, karena iman terdiri dari perkataan dan perbuatan.
* Nasihat termasuk dari iman. Karena itulah Imam al-Bukhari berkata dalam Shahîh-nya, dalam Kitâbul- Imân.
* Baiknya Rasûlullâh Shallallâhu 'Alaihi Wasallam dalam mengajarkan agama kepada para sahabatnya.
* Para sahabat radhiyallâhu'anhum sangat berkeinginan keras untuk mendapatkan ilmu.
Dakwah itu harus dimulai dari yang paling penting kemudian yang penting.
Marâji’:
Al-Wâfî fî Syarhil-Arba’în an-Nawawiyyah, Dr. Musthafa al-Bugha dan Muhyidin Mustha.
An-Nihâyah fî Gharîbil Hadîts, Ibnul-Atsîr.
Fiqih Nasihat, Fariq bin Ghasim Anuz.
Fat-hul Bâri, al-Hafizh Ibnu Hajar al-‘Atsqalani.
Irwâ-ul Ghalîl fii Takhriiji Ahâdîts Manâris-Sabîl, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
Jâmi’ul ‘Ulum wal-Hikam, Ibnu Rajab al-Hanbali. Tahqiq: Syaikh Syu’aib al-Arnauth dan Ibrahim Bâjis.
Qawâ’id wa Fawâ-id minal-‘Arba’în an-Nawawiyyah, karya: Syaikh Nazhim Muhammad Sulthan.
Shahîh Muslim, dan lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam takhrij hadits.
Silsilah al-Ahâdîts ash-Shahîhah, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani.
Syarah Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, Yazid bin Abdul Qadir Jawas.
Syarah Shahîh Muslim, karya: al-Imam an-Nawawi
Syarhul-Arba’în an-Nawawiyyah, al-‘Allamah Muhammad Hayat as-Sindi. Tahqiq: Hikmat bin Ahmad al-Hariri, Daar Ramaadi, Cetakan I, Tahun 1415 H.
Syarhul- Arba’în an-Nawawiyyah, Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin.
Syarhus-Sunnah, al-Imam al-Baghawi.
Ta’zhîm Qadrish-Shalâh, Imam Muhammad bin Nashr al-Marwazi. Tahqiq dan Takhrij: Dr. ‘Abdurrahman bin ‘Abdul-Jabbar al-Fariyuwa’i, Maktabah ad-Dâr Madinah an-Nabawiyyah, Cetakan I.
Dan kitab-kitab lainnya yang disebutkan dalam catatan kaki.
---------------
[1] Siyar ‘Alâmin Nubalâ (II/442-448), al-Ishâbah fî Tamyîzish-Shâhâbah (I/183-184), dan Tahdzîbut- Tahdzîb (I/449, no. 951).
[2] Lisânul-Arab (XIV/158-159) bagian kata “Nashaha”. Daar Ihyâ-ut Turats al-‘Arabi, Cetakan I, Tahun 1408H.
[3] Syarah Shahîh Muslim (II/37).
[4] Jâmi’ul-‘Ulûm wal-Hikam (I/219). Lihat juga an-Nihâyah fî Gharîbil-Hadits (V/63).
[5] HR Abu Dawud (no. 1949), an-Nasâ-i (V/256), at-Tirmidzi (no. 2975). Lihat Fat-hul Bâri (I/138).
[6] Fat-hul Bâri (I/138).
[7] Jâmi’ul-‘Ulûm wal-Hikam (I/218).
[8] Ta’zhîmu Qadrish-Shalâh, (II/691-692).
[9] Syarah Shahîh Muslim (II/38) oleh Imam an-Nawawi.
[10] Jâmi’ul-‘Ulûm wal-Hikam (I/222).
[11] Syarhul-Arba’în an-Nawawiyah, hlm. 47-48.
[12] Ta’zhîm Qadrish-Shalâh (II/693).
[13] Al-Wâfî fî Syarh al-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 42.
[14] Syarhul-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 48.
[15] HR Muslim (no. 804), dari Sahabat Abu Umamah al-Bahili radhiyallâhu'anhu.
[16] HR Abu Dawud (no. 1464) dan at-Tirmidzi (no. 2914), dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Amr radhiyallâhu'anhu.
[17] HR al-Bukhari (no. 7527), dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallâhu'anhu.
[18] HR al-Bukhari (no. 5027), dari Sahabat ‘Utsman bin ‘Affan radhiyallâhu'anhu.
[19] Al-Wâfî fî Syarh al-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 42-43.
[20] Ta’zhîmu Qadrish-Shalâh (II/693).
[21] Syarhul-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 48.
[22] Ta’zhîm Qadrish-Shalâh (II/693-694).
[23] Syarhul-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 48.
[24] HR Ibnu Abi ‘Ashim dalam as-Sunnah, Bab: Kaifa Nashihatur-Ra’iyyah lil-Wulât (II/ 507-508 no. 1096, 1097, 1098), Ahmad (III/403-404) dan al-Hakim (III/290) dari ‘Iyadh bin Ghunm rahimahullâh.
[25] HR Abu Dawud (no. 4344), at-Tirmidzi (no. 2174), dan Ibnu Majah (no. 4011), dari Sahabat Abu Sa’id al-Khudri. Lihat Silsilah al- Ahâdîts ash-Shahîhah, no. 491.
[26] Syarhul-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 48.
[27] Al-Wâfî fî Syarah al-Arba’iin an-Nawawiyyah, hlm. 45.
[28] HR Muslim (no. 2162), dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallâhu'anhu.
[29] HR al-Bukhari (no. 57) dan Muslim (no. 56 [97]).
[30] Qawâ’id wa Fawâ-id minal-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 95.
[31] Al-Wâfî fî Syarh al-Arba’în an-Nawawiyyah, hlm. 46.
[32] Raudhatul-‘Uqalâ’ wa Nuzhatul-Fudhalâ`, hlm. 176-177.
[33] Akhlâq was Siyar fî Mudâwâtin Nufûs (hal. 45).
[34] Diwân Imam asy-Syafi’i, dikumpulkan dan disusun oleh Muhammad ‘Abdur-Rahim, Darul-Fikr, hlm. 275.
(Majalah As-Sunnah Edisi 05/Tahun XI)
http://majalah-assunnah.com/
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 8:11 am 0 comments
Labels: ~ Aqidah Sohihah ~, ~ Bekalan Rohani ~, ~ Ilmu Dan Dakwah ~
Saturday, 4 December 2010
~ Bid'ah Merosak Keindahan Islam ~

Telah kita bahas di dalam bab yang pertama bahwa islam adalah agama yang mudah, dan Allah menginginkan kemudahan untuk kita dan tidak menginginkan kesulitan, maka karena ibadah adalah beban, Allah haramkan sampai ada dalil yang memerintahkannya. Dan yang harus kita fahami adalah bahwa meninggalkan lebih mudah dari melakukan, oleh karena itu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menggantungkan perintah dengan kemampuan hamba, dan tidak menggantungkan larangan dengan kemampuan, karena semua hamba mampu meninggalkan larangan. Sabdanya :
فَإِذاَ نَهَْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوْا ِمنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ.
“Apabila aku melarang sesuatu, tinggalkanlah. Dan apabila aku memerintahkan kepada sesuatu, lakukanlah semampu kamu”. (HR Bukhari dan Muslim).
Banyak kerusakan yang ditimbulkan oleh bid’ah, diantaranya adalah :
1. Bid’ah memberikan kesulitan kepada hamba, karena telah membebani manusia dengan sesuatu yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rosul-Nya.
2. Bid’ah menyebabkan manusia keluar dari ketaatan kepada Rasul. Karena Allah Ta’ala berfirman :
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.
“Katakanlah, Jika kamu mencintai Allah ikutilah aku (Muhammad) niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu.” (QS Ali Imran : 31).
Ibnu Katsir rahimahullah berkata,” Ayat yang mulia ini adalah sebagai hakim bagi orang mengaku mencintai Allah, sementara ia tidak di atas tata cara (ibadah) Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, dimana ia dusta dalam klaimnya tersebut sampai mengikuti syari’at Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam pada seluruh perkataan, perbuatan dan keadaan beliau, sebagaimana telah ada dalam kitab Ash Shahih Nabi bersabda :
مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
“Barang siapayang beramal dengan suatu amal yang tidak diperintahkan oleh kami maka amal tersebut tertolak.” (HR Muslim).
3. Bid’ah meniadakan kesempurnaan syahadat Muhammad Rosulullah.
Karena tujuan di utusnya Rosul adalah dalam rangka menjelaskan kepada manusia tentang ibadah yang diridlai oleh Allah, karena ibadah adalah hak Allah dan tentunya Allah ingin diibadahi sesuai dengan apa yang Dia cintai dan ridlai, bukan sesuai selera manusia. Dan yang Allah cintai dan ridlai adalah yang Allah wahyukan kepaa Rosul-nya.
4. Bid’ah adalah tikaman terhadap kesempurnaan islam.
Karena orang yang berbuat bid’ah konskwensinya adalah menyatakan dengan perbuatannya atau lisannya bahwa syari’at islam belum sempurna sehingga butuh penambahan, kalaulah ia meyakini islam telah sempurna di seluruh lininya tentu ia tidak akan berbuat bid’ah.
5. Bid’ah adalah tikaman terhadap sifat amanah Rosulullah Sallallahu’alaihi wasallam.
Ibnul Majisyun berkata,” Aku mendengar imam Malik berkata,”Barang siapa yang berbuat bid’ah di dalam islam yang ia anggap baik, ia telah menganggap Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, karena Allah berfirman,”Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu.” Maka yang pada hari itu tidak termasuk agama, pada hari inipun tidak termasuk agama.”
6. Bid’ah melenyapkan sunah, karena berapa banyak sunnah yang hilang dan digantikan oleh bid’ah, seperti adzan awal subuh, salawat, dll.
Berkata Hassan bin ‘Athiyyah,” Tidaklah suatu kaum berbuat bid’ah dalam agama mereka kecuali Allah akan mencabut sunnah yang semisal.” (HR Ad Darimi).
7. Bid’ah penyebab utama terjadinya perpecahan umat. Karena pada zaman Rosulullah dan sahabatnya belum terjadi bid’ah tapi ketika muncul orang-orang yang mengikuti selain petunjuk mereka mulailah terjadi perpecahan.
8. Amalan pelaku bid’ah tertolak. (HR Muslim).
9. Allah menghalangi ahli bid’ah untuk bertaubat selama dia tidak meninggalkan bid’ahnya. Sebagaimana sabda Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :
إِنَّ اللهَ حَجَبَ التَّوْبَةَ عَنْ كُلِّ صَاحِبِ بِدْعَةٍ حَتَّى يَدَعَ بِدْعَتَهُ.
“Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid’ah sampai ia meninggalkan bid’ahnya.” (HR Thabrany dan disahihkan oleh syeikh Al Bani).
10. Pelaku bid’ah akan menanggung dosa orang yang mengikutinya. Sebagaimana sabda Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam :
مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ. وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ.
“Barangsiapa mencontohkan suatu perbuatan baik di dalam islam, maka ia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan barang siapa mencontohkan suatu perbuatan buruk di dalam islam, maka ia akan memperoleh dosanya dan dosa orang-orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa dikurangi sedikitpun dari dosa mereka.” (HR Muslim).
11. Orang yang melindungi ahli bid’ah dilaknat oleh Allah. sebagaimana sabda Nabi :
لَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا
“Semoga Allah melaknat orang yang melindungi orang yang mengada-ada (kebid’ahan)”.(HR Muslim).
12 Pelaku bid’ah akan semakin jauh dari Allah.
Al Hasan Al Bashry rahimahullah berkata :” pelaku bid’ah tidaklah ia menambah ibadah (yang bid’ah) kecuali semakin jauh dari Allah “. (Ibnu Baththah, Al Ibanah).
13. Pelaku bid’ah memposisikan dirinya pada kedudukan yang menyerupai pembuat syari’at, karena yang berhak membuat syari’at hanyalah Allah saja. Firman-Nya :
أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوْا لَهُمْ مِّن الدِّيْنِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ.
“Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diidzinkan oleh Allah.”
14. Bid’ah lebih buruk dari maksiat.
Syaikhul islam ibnu Taimiyah berkata,”Sesungguhnya ahli bid’ah lebih buruk dari ahli maksiat yang mengikuti syahwatnya berdasarkan sunnah dan ijma’ ulama… kemudian beliau menyebutkannya.
15. Bid’ah lebih disukai iblis dari maksiat.
Ibnul Ja’ad meriwayatkan dalam musnadnya (no 1885) dari Sufyan Ats Tsauri berkata,”Bid’ah lebih disukai oleh iblis dari pada maksiat.” Karena jika engkau bertanya kepada pencuri misalnya,”Apakah engkau meyakini mencuri itu maksiat ? ia akan menjawab “ya”. Sedangkan ahli bid’ah menganggap baik perbuatannya sehingga sulit diharapkan taubatnya.
16. Dan lain-lain.
Ibnu Katsir, Tafsir ibnu katsir 2/24 tahqiq Hani Al haaj.
Ilmu ushul bida’ hal 20.
Al I’tisham 1/49.
Sunan Ad Darimi 1/58 no 98 tahqiq Fawwaz Ahmad dan sanadnya shahih.
Dalam shahih targhib wa tarhib no 54.
Muslim 2/705 no 1017.
Majmu’ fatawa ibnu Taimiyah 10/9.
-------------------
Penulis: Al-Ustadz Badrusalam
http://abuyahyabadrusalam.com/
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 10:51 pm 0 comments
Labels: ~ Aqidah Sohihah ~, ~ Sunnah Dan Bid'ah ~
Friday, 3 December 2010
~ Mengenal Hakikat BID'AH ~

Definisi bid’ah.
Pembaca yang budiman, para ulama ketika mendefinisikan sesuatu, mereka selalu membawakan definisi dari sisi bahasa dan istilah. Karena makna syar’i bila bertentangan dengan makna lughawi (bahasa), maka lebih didahulukan makna syar’I sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ushul fiqih.
Contohnya adalah sholat, secara bahasa artinya do’a, dan secara istilah syari’at artinya perbuatan dan perkataan yang khusus yang dimulai dengan takbirotul ihram dan di akhiri dengan salam.
Bila ada orang yang berpendapat bahwa orang yang berdo’a sudah mencukupinya sehingga tidak perlu sholat lagi, dengan alasan bahwa sholat secara bahasa artinya do’a. tentu pendapat ini sangat batil, karena yang dimaksud dengan sholat yang diperintahkan oleh Allah dan Rosul-Nya adalah sholat dengan tata cara yang telah kita ketahui bersama.
Demikian pula bid’ah, makna bid’ah secara bahasa tidak boleh dibawa kepada makna bid’ah secara istilah syari’at, namun ia berhubungan sebagaimana akan kita jelaskan.
Ibnu Katsir rahimahullah berkata,” Bid’ah ada dua macam: bid’ah syari’at seperti sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam :
فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ
“Sesungguhnya setiap yang ada-adakan adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat”.
Dan bid’ah lughowiyah (bahasa) seperti perkataan umar bin Khaththab ketika mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih :”Inilah sebaik-baiknya bid’ah”.
Dan yang harus difahami adalah bahwa Allah dan Rosul-Nya selalu menyampaikan syari’at ini dengan makna syari’at, seperti bila Allah dan Rosul-Nya menyebutkan sholat, maka maknanya adalah perbuatan dan perkataan yang dimulai dengan takbirotul ihram dan diakhiri dengan salam. demikian pula kata bid’ah, bila diucapkan oleh pemilik syari’at maka harus dibawa kepada makna syari’at, bukan makna bahasa.
Bid’ah secara bahasa.
Secara etimologi, bid’ah artinya setiap perkara baru yang diadakan atau diciptakan tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Sebagaimana firman Allah Ta’ala :
بَدِيْعُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ.
“Allah pencipta langit dan bumi (tanpa contoh)”. (QS Al Baqarah : 117).
Makna secara bahasa ini mencakup perkara dunia dan akhirat, sehingga dapat kita katakan bahwa mobil, kereta, pesawat, handphone, ilmu mushtolah hadits dan lain-lain adalah bid’ah secara bahasa, karena tidak ada contoh sebelumnya. Namun sesuatu yang menurut bahasa bid’ah, belum tentu secara istilah dianggap bid’ah.
Bid’ah secara istilah.
Memang tidak ada dalam Al Qur’an dan assunnah nash yang menyebutkan definisi bid’ah secara istilah syari’at, akan tetapi para ulama memberikan definisi setelah mengumpulkan nash-nash syari’at.
Para ulama berbeda-beda ungkapan dalam mendefinisikan bid’ah. Imam Asy Syafi’I rahimahullah dalam riwayat Ar Rabie’ berkata :” Bid’ah adalah sesuatu yang menyelisihi al qur’an, atau sunnah, atau atsar para shahabat Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam “.
Asy Syathibi rahimahullah berkata,” Bid’ah adalah sebuah tata cara dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syari’at yang maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta’ala”.
Ibnu Rajab rahimahullah berkata,” Yang dimaksud dengan bid’ah adalah setiap yang diadakan dari apa-apa yang tidak ada asalnya dalam syariat yang menunjukkan kepadanya, adapun bila ada asal (dalil) syari’at yang menunjukkan kepadanya maka bukanlah bid’ah secara syari’at walaupun dianggap bid’ah secara bahasa”.
As suyuthi rahimahullah berkata,”Bid’ah adalah ungkapan tentang perbuatan yang bertabrakan dengan syari’at dengan cara menyelisihinya atau melakukannya dengan cara menambah atau mengurangi”.
Dari definisi para ulama di atas dapat kita simpulkan dalam beberapa poin :
1. Ruang lingkup bid’ah secara istilah hanya terbatas dalam masalah agama (ibadah), ini di tunjukkan oleh definisi As Syathibi. Bid’ah inilah yang maksud oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa setiap bid’ah adalah sesat.
Maka keluar dari batasan “agama” adalah masalah yang bersifat duniawi. Mengapa demikian ? karena dalil-dalil syari’at menunjukkan bahwa pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah duniawi adalah halal dan suci, diantaranya adalah firman Allah Ta’ala QS Al Baqarah ayat 29 :
هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيْعًا
“Dialah (Allah) yang menciptakan untukmu semua yang ada di bumi ini”.
Redaksi ayat ini dalam rangka imtinan (mengungkit kenikmatan) dan imtinan pastilah dengan sesuatu yang mubah dan halal.
Dalam Hadits Muslim dari ‘Aisyah, Tsabit dan Anas, sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan (bunga kurma), maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda.” Kalau kamu tidak lakukan itu, ia tetap akan bagus”. Maka pohon kurma itu mengeluarkan buah yang jelek. Suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melewati mereka lagi dan bersabda,”Ada apa dengan pohon kurma kalian ? Mereka berkata,” Engkau mengatakan begini dan begitu “. Beliau bersabda :
أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمْرِ دُنْيَاكُمْ.
“Kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian “.
Maka urusan menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, demikian juga pensyari’atan ibadah, serta penjelasan jumlah, tata cara dan waktunya, dan peletakan kaidah-kaidah umum dalam mu’amalat hanya berasal dari Allah dan Rosul-Nya, bukan urusan ulil amri dari kalangan ulama ataupun umara’. Kita dan mereka setara dalam masalah ini, maka segala perselisihan dalam urusan ini tidak boleh dikembalikan kepada mereka, namun harus dikembalikan kepada Allah dan Rosul-Nya.
Adapun untuk urusan dunia mereka lebih faham dari kita, para ahli pertanian lebih mengetahui apa yang dapat memperbaiki dan meningkatkan kwalitasnya, apabila mereka mengeluarkan sebuah perintah yang berhubungan dengan pertanian, maka kewajiban umat adalah mentatati mereka. Demikian juga ahli perniagaan dan ekonomi ditaati dalam urusan yang berhubungan dengannya.
Kembali kepada ulil amri dalam kemashlahatan umum sama dengan kembali kepada para dokter dalam mengetahui obat yang berbahaya agar tidak dikonsumsi dan obat yang bermanfaat agar dapat digunakan.
Namun ini bukan berarti dokter yang menghalalkan kepada kita yang bermanfaat dan mengharamkan yang berbahaya, akan tetapi ia hanya sebagai pembimbing saja. Yang menghalalkan dan mengharamkan hanyalah Allah saja, sebagaimana firman-Nya :
وَيُحِلُّ لَهُمْ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ.
“(Allah) Yang menghalalkan untuk mereka segala yang baik dan mengharamkan atas mereka segala yang buruk”. (QS Al A’raaf : 157).
Ini adalah madzhab jumhur ushuliyyin (ahli ushul fiqih) dan Muhaqqiqin, bahwa pada asalnya segala sesuatu yang berhubungan dengan urusan dunia ini adalah halal, maka kita boleh memproduksi apa saja yang bermanfaat dalam kehidupan dunia ini, walaupun di zaman Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak ada, seperti berbagai jenis perabotan, sarana transportasi, pengeras suara, dan berbagai kemajuan tekhnologi lainnya. Walaupun ini semua dikatakan bid’ah, namun hanya sebatas bid’ah secara bahasa saja dan bukan bid’ah secara istilah syari’at.
Sedangkan ibnu Abi Hurairah dari Syafi’iyyah dan mu’tazilah baghdad serta Rafidlah berpendapat bahwa pada asalnya sesuatu yang berhubungan dengan dunia ini adalah haram, alasan mereka yang paling kuat adalah bahwa bumi milik Allah, sedangkan pada asalnya milik orang lain adalah terlarang kecuali dengan idzin pemiliknya.
Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena Allah telah memberikan idzin kepada manusia untuk mempergunakan apa yang ada di bumi ini selama tidak haram atau tidak menimbulkan mudlarat yang besar, sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat dan hadits di atas.
Ketika ibnus Subki Asy Syafi’i menemukan sebagian syafi’iyah berpendapat bahwa pada asalnya segala sesuatu itu haram, beliau berkata dalam (Al Ibhaj 1/138) :” Al Qadli Abu Bakar menyebutkan dalam attalkhish bahwa mereka itu tidak mempunyai kekokohan dalam ilmu kalam, dan barang kali mereka membaca kitab-kitab mu’tazilah dan menganggap baik kaidah tersebut, sehingga mereka berpendapat dengan pendapat tersebut, dan lalai bahwa kaidah tersebut adalah keluar dari pokok firqah Qodariyah”.
Kaidah dalam masalah ibadah.
Bila kita telah mengetahui bahwa masalah duniawi pada asalnya adalah halal, maka yang harus kita ketahui juga adalah bahwa masalah ibadah pada asalnya adalah haram kecuali bila ada dalil yang memerintahkan.
Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam I’lamul muwaqqi’in :” Telah diketahui bahwa tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Allah dan rosul-Nya, dan tidak ada dosa kecuali yang dianggap dosa oleh Allah dan rosul-Nya. Sebagaimana tidak ada yang wajib kecuali yang diwajibkan oleh Allah dan rosul-Nya, dan tidak ada agama kecuali yang Allah syari’atkan. Maka pada asalnya dalam ibadah adalah terlarang sampai tegak dalil yang memerintahkannya. Sedangkan dalam ‘aqad dan mu’amalat pada asalnya adalah sah sampai tegak dalil yang membatalkannya.
Perbedaan antara keduanya adalah bahwa sesungguhnya Allah tidak diibadahi kecuali sesuai dengan apa yang Dia syari’atkan melalui lisan para rosul-Nya, karena ibadah itu hak Allah atas hamba-hambaNya, dan hak-Nya adalah yang Allah ridlai dan syari’atkan “.
Maka oleh karena ibadah itu adalah hak Allah semata, maka tidak mungkin tata caranya diserahkan kepada selera manusia, karena yang menurut manusia baik belum tentu disisi Allah baik. Maka sangat aneh ketika seseorang yang melakukan bid’ah diingkari, ia berkata,” Mana dalilnya kalau perbuatan itu terlarang (bid’ah) ? padahal justru karena tidak ada dalilnya perbuatan itu jadi terlarang, sebab pada asalnya ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang memerintahkannya.
2. Bid’ah adalah sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh dalil dalam syari’at, adapun yang ditunjukkan oleh kaidah-kaidah syari’at maka bukanlah bid’ah secara istilah syari’at walaupun dari sisi bahasa ia dikatakan bid’ah.
Ini ditunjukkan oleh definisi ibnu Rajab. Maka yang bersumber dari Al Qur’an dan sunnah bukanlah bid’ah secara istilah syari’at walaupun dianggap bid’ah secara bahasa, contohnya adalah mengumpulkan al qur’an, shalat tarawih berjama’ah dengan satu imam, mengadakan adzan jum’at kedua, mengharokati dan memberi titik kepada Al Qur’an, dan menyusun ilmu-ilmu syari’at seperti ilmu Nahwu, shorof, mustholah hadits, ushul fiqih dan lain-lain.
Dan inilah makna perkataan Umar bin Khaththab ketika mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama’ah dengan satu imam :” Inilah sebaik-baik bid’ah “. Maksudnya adalah bid’ah menurut bahasa bukan menurut istilah syari’at, karena bagaimana mungkin perkataan Umar tersebut dibawa kepada bid’ah menurut istilah syari’at, padahal Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam sendiri yang mencontohkannya, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam sunannya no 1373 ia berkata haddatsana Al Qo’nabi dari Malik bin Anas dari ibnu Syihab dari ‘Urwah bin Zubair dari Aisyah istri Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah sholat (tarawih) di masjid, maka orang-orang mengikuti sholatnya, kemudian di hari kedua beliau sholat lagi, maka manusia menjadi banyak yang hadir, kemudian di malam yang ketiga manusia telah berkumpul, akan tetapi Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam tidak keluar. Di pagi harinya beliau bersabda :
قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ فَلَمْ يَمْنَعْنِيْ مِنَ الْخُرُوْجِ إِلَيْكُمْ إِلاَّ أَنِّيْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
“Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, tidak ada yang menghalangiku keluar kepada kalian kecuali karena aku takut diwajibkan atas kalian “. Dan itu terjadi pada bulan Ramadlan.
Sanad hadits ini tidak diragukan lagi keshahihannya, karena semua perawinya masyhur akan ketsiqohannya.
Al Hafidz ibnu Rajab berkata,” Adapun yang ada pada perkataan ulama salaf terdahulu yang menganggap baik sebagian bid’ah, maka ia adalah bid’ah menurut bahasa bukan bid’ah menurut istilah syari’at, diantaranya adalah perkataan Umar bin Khaththab :” inilah sebaik-baiknya bid’ah”. Maksud beliau adalah bahwa belum dilakukan dengan cara seperti itu sebelum waktu tersebut. Akan tetapi ia mempunyai asal dalam syari’at yang menjadi rujukan, diantaranya adalah anjuran Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam untuk qiyam ramadlan, dan adalah manusia di zamannya melakukan shalat (qiyamulail) di masjid menjadi beberapa jama’ah yang terpencar dan ada juga yang melakukannya sendirian, kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam shalat bersama para shahabatnya di bulan Ramadlan lebih dari satu malam, kemudian beliau berhenti dengan alasan takut diwajibkan kepada mereka, dan alasan ini telah hilang setelah beliau shallallahu ‘alaihi wasallam wafat”.
Ini pula yang diinginkan oleh imam Asy Syafi’I, beliau membagi bid’ah menjadi dua macam : bid’ah mahmudah (yang terpuji), dan bid’ah madzmumah (yang tercela). Beliau mendefinisikan bid’ah yang terpuji sebagai bid’ah yang sesuai dengan sunnah atau tidak bertentangan dengan Al Qur’an, Sunnah, Atsar maupun ijma’.
Sesuatu yang sesuai dengan sunnah tidak boleh disebut bid’ah menurut istilah syari’at, walaupun dianggap bid’ah menurut bahasa. Sedangkan yang bertentangan dengan sunnah maka itulah hakikat bid’ah yang sesat, sebuah contoh adalah bahwa imam Asy Syafi’I menganggap tahlilan sebagai sesuatu yang diharamkan, beliau berkata :
وأكره المأتم وهي الجماعة وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذالك يجدد الحزن
“ Dan aku mengharamkan ma’tam yaitu berkumpul (di rumah keluarga mayit), meskipun disitu tidak ada tangisan, karena hal itu malah akan menimbulkan kesedihan baru”.
Bahkan madzhab Asy Syafi’iyah sendiri mengharamkan tahlilan dan menganggapnya sebagai bid’ah yang mungkar, sebagaimana disebutkan dalam kitab I’anatu thalibin 2/165. Yang anehnya sebagian orang berdalil dengan perkataan imam Syafi’I untuk menetapkan adanya bid’ah hasanah diantaranya adalah tahlilan, padahal imam Syafi’I dan para pengikutnya menganggapnya sebagai bid’ah yang mungkar.
3. setiap perkara yang menyelisihi Al Qur’an, atau sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam atau atsar para shahabatnya adalah bid’ah yang sesat.
Ini ditunjukkan oleh definisi imam Asy Syafi’I dalam riwayat Rabie’ di atas. lalu apakah yang dimaksud menyelisihi dalam perkataan beliau tersebut ? diantara maknanya adalah melakukan suatu ibadah atau tata cara ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya. Oleh karena itu imam Asy Syafi’I mengharamkan ma’tam (tahlilan) sebagaimana telah kita sebutkan diatas. Dan ini yang ditunjukkan oleh perkataan para ulama setelahnya.
Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan An Najm : 39, merajihkan tidak sampainya pahala bacaan Al Qur’an kepada mayat, beliau beralasan,” Karena Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menyunnahkannya kepada umatnya, tidak pula menganjurkannya, dan tidak pula membimbing untuk melakukannya baik dengan nash maupun dengan isyarat, dan perbuatan itu juga tidak pernah dinukil dari para shahabat seorang pun, kalaulah itu baik tentu mereka telah mendahului kita kepada perbuatan tersebut. Dan masalah qurubat (ibadah) hanya terbatas dengan apa yang ada dalam nash dan tidak boleh dipergunakan pada qiyas tidak juga ra’yu. Adapun do’a dan shodaqoh maka ia sampai kepada mayat dengan kesepakatan ulama karena adanya nash dari Asy Syari’ (Allah)”.
Beliau beralasan karena hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya.
Imam An Nawawi Rahimahullah ketika menganggap shalat raghaib dan nishfu Sya’ban sebagai bid’ah yang mungkar beliau berkata,” Alhamdulillah, dua sholat tadi tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam tidak juga seorangpun dari shahabat tidak pula imam yang empat, tidak pernah juga dilaksanakan oleh ulama yang dijadikan panutan, dan tidak sah satupun hadits mengenai hal itu, ia baru diadakan pada generasi-generasi terakhir, dan mengerjakan dua sholat tersebut termasuk bid’ah yang mungkar…”.
Syaikh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ketika menetapkan keyakinan bahwa Allah bersemayam di atas ‘Arasy, beliau berkata,” Bersemayam dzat-Nya di atas ‘Arasy bukan dengan makna duduk menyentuh sebagaimana yang dikatakan oleh mujassimah dan karomiyah, bukan juga dengan makna berkuasa sebagaimana yang dikatakan oleh mu’tazilah, karena syari’at ridak menyebutkan demikian, tidak pula ada nukilan dari para shahabat, tabi’in dan salafusshalih dari kalangan ashhabul hadits seorang pun juga “.
Perkataan-perkataan para ulama di atas memberi pemahaman kepada kita, bahwa setiap ibadah atau keyakinan yang tidak pernah dilakukan atau tidak pernah diyakini oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya adalah bid’ah yang mungkar, dan ini berlaku kepada banyak amalan di zaman ini seperti perayaan maulud Nabi, perayaan isra mi’raj, perayaan tahun baru dan lain-lain karena semua itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para shahabatnya, walaupun diperbolehkan dengan dalih adanya fatwa sebagian ulama, karena ulama dapat diterima perkataannya bila tidak menyelisihi Al Qur’an, sunnah dan atsar para shahabat.
4. Bahwa bid’ah (menurut makna syari’at) semuanya sesat, maka tidak ada bid’ah hasanah, karena bid’ah bertentangan dengan syari’at sehingga semuanya tercela.
Kaidah ini ditunjukkan oleh sunnah dan ijma’ para shahabat. Jabir radliyallahu ‘anhu berkata,” Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam biasa berkata di dalam khutbahnya : memuji Allah dan menyanjung-Nya sesuai dengan keagungan-Nya, kemudian beliau bersabda :
مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الأُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ.
“Siapa saja yang Allah tunjuki maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa saja yang Dia sesatkan maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam. Dan seburuk-buruknya perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan di dalam api Neraka”. (HR An Nasai, ibnu Khuzaimah dan lainnya).
Dalam hadits ini, Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap bid’ah adalah sesat, dan kata “kullu” adalah termasuk lafadz-lafadz yang umum sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab ilmu ushul fiqih dan bahasa arab. Dan ini dikuatkan oleh pemahaman para shahabat sebagaimana yang dikeluarkan oleh Al laalikai dalam kitab syarah I’tiqad ahlissunnah wal jama’ah dengan sanadnya kepada Abdullah bin Umar radliyallahu ‘anhuma ia berkata,” Setiap bid’ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia”.
Di dalam kisah yang terkenal dari ibnu Mas’ud radliyallahu ‘anhu ketika beliau melewati masjid yang ada padanya suatu kaum yang sedang duduk berhalaqoh-halaqoh, mereka membaca takbir, tahlil dan tasbih dengan tata cara yang tidak pernah dilakukan oleh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya. Ibnu Mas’ud mengingkari mereka dan berkata :
عُدُّوْا سَيِّئَاتِكُمْ فَأَنَا ضَاِمٌن أَنْ لاَ يَضِيْعَ مِنْ حَسَنَاتِكُمْ شَيْءٌ, وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ مَا أَسْرَعَ هَلَكَتَكُمْ ! هَؤُلاءِ صَحَابَةَ نَبِيِّكُمْ مُتَوَافِرُوْنَ وَ هَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ. وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ أَهْدَى مِنْ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ أَوْ مُفْتَتِحُوا بَابَ ضَلاَلَةٍ. قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا أَرَدْنَا إِلاَّ الْخَيْرَ. قَالَ : وَكَمْ مِنْ مُرِيْدٍ لِلْخَيْرِ لَنْ يُصِيْبَهُ.
“Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, aku jamin tidak akan sia-sia kebaikan kalian sedikitpun. Celaka kalian wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kebinasaan kalian ! Mereka para shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam masih banyak, dan ini bajunya belum lusuh, dan bejananya pun belum pecah. Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, apakah kalian berada di atas hidayah lebih tertunjuki dari agama Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wasallam, ataukah kalian membuka pintu kesesatan ?
Mereka berkata,” Wahai Abu Abdirrahman, kami hanya menginginkan kebaikan”. Beliau menjawab,”Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun ia tidak mendapatkannya”.
Kisah ini diriwayatkan oleh Ad Darimi dalam sunannya : Akhbarona Al Hakam bin Al Mubarok akhbarona ‘Umar bin Yahya aku mendengar ayahku menceritakan dari ayahnya :” Kami duduk-duduk di depan rumah Abdullah bin Mas’ud sebelum sholat shubuh, apabila beliau telah keluar, kamipun berjalan bersamanya menuju masjid, lalu Abu Musa Al Asy’ari mendatangi kami dan berkata,” Apakah Abu Abdirrahman telah keluar ? setelah kami berkata tidak, ia pun duduk bersama kami hingga beliau keluar, ketika beliau telah keluar, kami semua bangkit kepadanya. Abu Musa Al Asy’ari berkata,” Wahai Abu Abdirrahman, tadi aku melihat di masjid suatu perbuatan yang aneh, dan aku memandangnya sebagai sebuah kebaikan alhamdulillah”. Ia berkata,” Apa itu ? ia menjawab,” Jika masih hidup, engkau akan melihatnya. Aku melihat di masjid suatu kaum berhalaqoh-halaqoh duduk menunggu shalat, setiap halaqoh dipimpin satu orang dan ditangan mereka terdapat batu kerikil, apabila pemimpinnya berkata,” bertakbirlah seratus kali ! mereka pun bertakbir seratus kali. Tahlil 100 kali, merekapun bertahlil seratus kali, bertatsbihlah 100 kali, merekapun melakukannya. Ibnu Mas’ud berkata,” Apa yang engkau katakan kepada mereka ? ia menjawab,” Aku tidak mengatakan apa pun kepada mereka karena menunggu pendapatmu atau menunggu perintahmu…dst.
Qultu : sanad hadits ini jayyid, Al Hakam bin Al mubarok di tsiqohkan oleh ibnu Mandah dan ibnu hibban namun ibnu ‘Adi mengisyaratkan bahwa ia termasuk perawi yang mencuri hadits sehingga Al Hafidz ibu Hajar mengatakan tentangnya : shoduq rubbama wahim, sementara Adz Dzahabi dalam Al kasyif berkata,” Tsiqah”.
Sedangkan ‘Umar bin Yahya yang benar adalah Amru bin yahya yaitu bin Amru bin salamah, ibnu Ma’in dalam riwayat Ahmad bin Abi Yahya berkata,” Laisa bisyai’ “. Namun Ahmad bin Abi yahya ini adalah Al Anmathi ia kadzdzab sebagaimana yang dikatakan oleh Adz Dzahabi dalam Al Mizan, dan dalam riwayat Al Laits bin ‘Abdah ibnu Ma’in berkata,” La yurdla (tidak diridlai) “. (Al Kamil ibnu ‘Adi) Namun perawi dari Al Laits adalah Ahmad bin Ali yaitu Al Madaaini, ibnu yunus berkata,” laisa bidzaaka”. (Mizanul I’tidal 1/122). Sementara dalam riwayat Ishaq bin Manshur, ibnu Ma’in berkata,” Tsiqah “. (Al Jarhu watta’dil ibnu Abi Hatim 6/269). Dan ini adalah riwayat yang paling kuat. Adapun perkataan ibnu Kharrasy mengenai ‘Amru :” Laisa bimardliyy (tidak diridlai)”. Adalah jarh yang mubham tidak mufassar sehingga dapat kita simpulkan bahwa ‘Amru bin yahya adalah perawi yang tsiqah, karena ibnu Ma’in seorang ulama yang dikategorikan mutasyaddid dalam tautsiq, maka apabila beliau mentsiqohkan seorang perawi maka gigitlah kuat-kuat, kecuali bila bertentangan dengan jumhur. Wallahu a’lam.
Kisah ini adalah praktek dari hadits Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam bahwa semua bid’ah adalah sesat. Dalam kisah tersebut mereka berhujjah dengan niat dan tujuan yang baik, sehingga mereka memandang baik perbuatan tersebut, lebih-lebih yang mereka ucapkan adalah dzikir-dzikir yang asalnya disyari’atkan.
Namun Abdullah bin Mas’ud radliyallahu ‘anhu tidak memandang dari asal hukum dzikir, beliau memandang dari sisi tata caranya yang tidak pernah dilakukan oleh Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya. Beliau berkata,” Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun ia tidak mendapatkannya”. Artinya sebatas niat yang baik tidaklah cukup bila tata caranya tidak sesuai dengan praktek Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dan para shahabatnya.
Inilah yang difahami oleh para shahabat Rosulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, yaitu bahwa semua bid’ah adalah sesat, Dan pendapat mereka tidak diselisihi oleh shahabat lainnya sehingga menjadi hujjah, imam Asy Syafi’I berkata,” dan jika salah seorang dari mereka (para shahabat) berpendapat dan tidak diselisihi oleh shahabat lain, kamipun tetap mengambil pendapatnya “. adapun perkataan Umar bin Khaththab :” Inilah sebaik-baiknya bid’ah”. Maksudnya adalah bid’ah menurut bahasa bukan menurut istilah syari’at sebagaimana telah kita bahas.
Bila ada yang bertanya, benarkah kata kullu selalu berarti semua ? jawabnya adalah benar, karena semua ahli ushul fiqih menyatakan bahwa kullu adalah termasuk lafadz-lafadz umum. Dalam kitab Nuzhatul khatir syarah kitab roudlatunnaadzir disebutkan :” Lafadz-lafadz umum ada lima macam yaitu… macam keempat : Kullu dan jamii’. Dan lafadz yang umum tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil, dan tidak ada dalil yang memalingkan hadits kullu bid’ah dlolalah (setiap bid’ah adalah sesat).
Ibnu Katsir, Tafsir Al Qur’anil ‘Adziem 1/223. Cet. Maktabah taufiqiyah, Tahqiq Hani Al Haaj.
Mana dalilnya, hal 13. Dan makna ini adalah benar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, namun sayang penulis kitab mana dalilnya tidak memahami tujuan makna bid’ah secara bahasa dan istilah.
I’lamul muwaqqi’in 2/151, tahqiq Masyhur Hasan Salman.
Al I’tishom 1/50, tahqiq Salim bin ‘Ied Al Hilali.
Jami’ul ‘ulum wal hikam 2/127 tahqiq Syu’aib Al Arnauth.
Al Amru bil ittiba’ wan nahyu ‘anil ibtida’ hal 88.
Muslim 4/1836 no 2363. Tarqim Muhammad Fuad Abdul Baqi.
Muhammad Ahmad Al’Adawi, Ushul fil bida’ wassunan hal 94.
At Tahqiqat wattanqihat assalafiyat ‘ala matnil waraqat, karya Syaikh Masyhur Salman hal 588-589.
Lihat ilmu ushul bida’ karya Syaikh Ali Hasan hal. 70.
Ibnu Rajab, Jami’ul ulum wal hikam 2/128. Tahqiq Syu’aib Al Arnauth.
Lihat buku mana dalilnya hal 14-15.
Al Umm 1/248.
Ibnu Katsir, Tafsir AlQur’anil ‘Adziem 7/356-357 cet. Maktabah Taufiqiyah ta’liq Hani Al Haaj.
Lihat kitab Al Bida’ al hauliyah 265-266.
Al Gunyah 1/56.
An Nasai 3/209 no 1577 cet. Ke III Darul ma’rifah Beirut, dan ibnu Khuzaimah dalam shahihnya 3/143 no 1785 cet. II Al Maktabul islami. Dari jalan Abdullah bin Mubarak dari Sufyan Ats Tsauri dari Ja’far bin Muhammad dari ayahnya dari Jabir bin Abdillah. Qultu : sanad hadits ini shahih, Ja’far bin Muhammad yaitu Ash shodiq di tsiqohkan oleh ibnu Ma’in dan Abu Hatim serta imam Asy Syafi’I rahimahumullah. Lihat Al Kasyif 1/295 tahqiq Muhammad ‘Awwamah.
1/104 no 126, dan ibnu Baththah no 205 dari jalan Syababah haddatsana Hisyam bin Al Ghaaz dari Nafi’ dari ibnu ‘Umar. Qultu : sanad hadits ini shahih, Syababah yaitu bin Sawwaar Al Madaaini, ia tsiqah sebagaimana yang dikatakan oleh Al Hafidz ibnu Hajar dalam attaqrib.
1/68-69 cet. daar ihya ussunnah annabawiyyah
I’lamul muwaqqi’in karya ibnu Qayyim 2/150 tahqiq Masyhur Hasan Salman.
2/108 cet. Pertama darul hadits beirut.
---------------
Oleh: Al-Ustadz Badrusalam
http://abuyahyabadrusalam.com/
Posted by NbI @ NuRiHSaN at 4:04 pm 0 comments
Labels: ~ Aqidah Sohihah ~, ~ Sunnah Dan Bid'ah ~